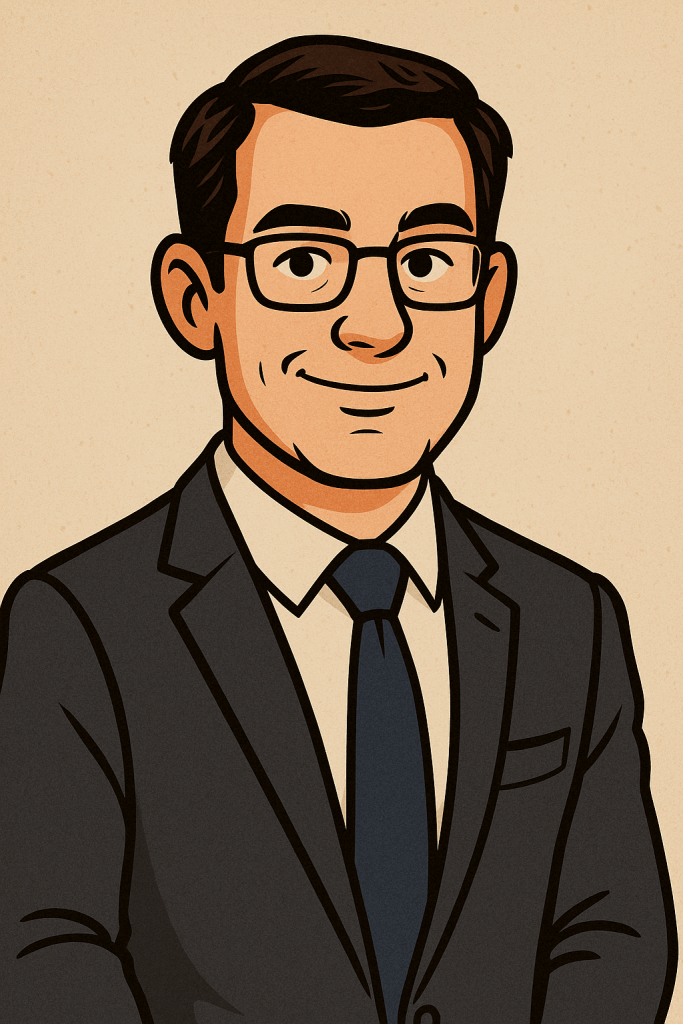
Ale, seru Risa usai meeting dengan relasi sambil melangkah keluar, “Kamek lapal!” Saya mengerling, lalu bertanya santai, “Kitak bedau makan siang? Kenapa?”
Kami berdua berjalan santai menyusuri Orchard Road yang ramai. Risa menarik napas panjang, “Kamek makan lambat tadi, dari pagi sibuk meeting.” Melihat jam di tangan saya, saya menggandeng tangannya ke Sheraton Hotel yang megah, “Makan di sini aja,” ajak saya lembut.
“Ale!” Risa berteriak ceria. “Kan kak Florence lagi di Singapura, di kantor Yuan. Undang makan bareng, yuk!” Tanpa menunggu lama, saya langsung menghubungi Florence, yang antusias untuk datang.
Saat kami duduk dan perut mulai keroncongan, saya menyapa Risa, “Yang bikin kangen itu gaya bicara bahasa Melayu Pontianak kamu, dengan aksen Tionghoa. Enggak bisa sebut er. Saya tersenyum sambil berbicara dalam bahasa Inggris perlahan, seraya menoleh ke Risa. Ia cepat-cepat menutup wajahnya dengan tangan, malu-malu.
Saya tertawa, “Enggak usah malu. Itulah identitas kamu. Wanita kampung orisinil.” Risa tersipu, tapi matanya berbinar, seolah ia bangga dengan akar budayanya. Saya, Florence dan Risa bertiga bersahabat sejak muda. Selalu berbagi tawa dalam suasana hangat.
Kini, Risa Wakil Chairman MNC di Beijing, tampak begitu bersinar. Tak berselang lama, Florence pun tiba. Setelah kami duduk dan menunggu hidangan, terdengar suara Florence “Sa, berapa rasio utang China terhadap PDB?” ujarnya sambil meletakkan menu di meja.
Saya menatap kedua sahabat ini, menyadari bahwa pertemuan sederhana di Sheraton ini bukan sekadar makan siang. Ini adalah pesta persahabatan dan diskusi cerdas. Dari dulu memang begitu.
Risa menarik napas sejenak, lalu memulai penjelasan dengan tenang “Utang pemerintah pusat dan daerah sudah mencapai sekitar 70% dari PDB China. Tapi kalau ditambah LGFV—Local Government Financing Vehicles—yang off-balance‑sheet, totalnya bisa menyentuh 120% dari PDB.”
Saya hanya tersenyum mendengar penjelasan teknis Risa, dan untungnya Florence lulusan ekonomi juga. Jadi percakapan kami tetap seru.
Florence lalu menatap Risa penuh penasaran, “Kalau ditotal dengan utang publik plus utang korporat, termasuk BUMN, berapa?”
Risa menjawab santai, “Wah, kalau semua dihitung barengan, bisa mencapai lebih dari 300% dari PDB. Ingat, PDB China sekarang sekitar USD 19 triliun. Coba hitung sendiri berapa total utangnya dan bebannya dalam bentuk bunga.”
Mata Florence membesar, “Wah, gila ya, besar sekali utangnya!”
Tapi Risa cuma tersenyum tenang, “Enggak juga, Florence. Lihat total aset BUMN China, lebih dari 800 triliun yuan, atau sekitar USD 100 triliun. Jadi utang 300% itu cuma setengah dari total aset mereka. Ekonomi China itu seperti samudera, luas dan dalamnya unpredictable.”
Florence mengernyit, masih kebingungan, “Tapi kenapa PDB bisa jauh lebih kecil daripada total aset BUMN-nya?”
Saya ikut membantu menjelaskan, “Itu karena PDB dan aset adalah dua hal berbeda. Bayangkan kamu punya rumah, mobil, tabungan dengan nilai total Rp 5 miliar, tapi pendapatan tahunanmu hanya Rp 500 juta. Asetmu besar, tapi pendapatan tahunan jauh lebih kecil. Sama halnya dengan negara.”
Risa menambahkan sambil melayangkan senyum penuh arti, “Betul. Aset adalah akumulasi kekayaan yang dibangun bertahun‑tahun. Sedangkan PDB adalah aliran pendapatan dalam periode tertentu, misalnya satu tahun. Jadi memang bisa jauh berbeda.”
Florence masih terdiam sejenak, lalu akhirnya tersenyum pelan, “Ooh… jadi seperti itu ya. Aku mengerti sekarang, perbandingan antara aliran pendapatan dan akumulasi kekayaan.”
Risa menatap Florence yang masih menyimpan tanda tanya di wajahnya.
“Mungkin kelihatan aneh buat kamu,” ujar saya lembut, menyingkap pembanding dari kisah Indonesia. “Utang pemerintah kita setara 40% dari PDB—sekitar hampir Rp 9.000 triliun—sedangkan total aset BUMN hanya Rp 16.000 triliun, masih di bawah PDB Rp 22.000 triliun. Aset kita rendah, sebagian besar karena tingkat value PDB kita rendah dan juga masalah korupsi. Makanya sulit menjadikan utang sebagai leverage efektif.”
Florence mengangguk pelan.“Ya, artinya utang kita sudah bikin bego,” katanya dengan nada polos, tapi tajam.
Perhatian mereka kini tertuju ke sisi teknis. Florence menoleh ke Risa. “Terus, mampu nggak China bayar utang dan bunganya? Apa seperti Indonesia yang terpaksa bayar utang pakai utang?”
Risa mengangkat bahu ringan, lalu menjawab. “Kalau dihitung dari pendapatan ekspor, hanya 6,5% dipakai untuk bayar bunga dan utang. Dari pendapatan pajak, bahkan cuma 3,4%. Jadi bagi pemerintah China, utang ini bukan big deal.”
Saya lalu menyambar untuk menegaskan “Bandingkan dengan Indonesia: tahun ini 60% penerimaan pajak kita untuk bayar utang dan bunga. Itu—big problem! Big deal!”
Florence tampak terhenyak. “Duh, kalau begitu benar-benar negara kita salah urus,” katanya lirih. “China, dengan penduduk empat kali kita, bisa kelola ekonomi sepintar ini. Padahal SDA kita bisa lebih besar—mereka impor nikel, batubara, dan CPO dari kita.”
Nuansa diskusi berubah jadi refleksi. Florence menatap Risa penuh rasa ingin tahu “Gimana China bisa sehebat itu urus negerinya?”
Risa tersenyum, seolah menikmati suasana renungan ini. Dia mundur sejenak, memberi saya kesempatan menerjemahkan perspektif structural.
“China ini unik. Elitnya tahu diri. Presiden berfungsi sebagai visioner—talenta, kreativitas, inovasi. Dia tahu arah negara. Tapi dalam eksekusi, ada ‘Perdana Menteri’, dipilih bukan karena politik, tapi skill manajerial. Biasanya mereka sudah kenal personal sejak lama. Jadi ketika presiden bilang sedikit, PM langsung tahu arti strategisnya.”
Saya melanjutkan dengan analogi yang mudah dipahami “Bayangkan orkestra. Presiden sebagai composer. Beri notasi inti. PM jadi konduktor. Terjemahkan ke seluruh pemain atau Menteri menteri. Menteri teknokrat menjalankan rencana, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dari tingkat pusat sampai desa, sistemnya saling sinergi. Jadi terdengar harmonis seperti simfoni.”
Risa mengangguk, kemudian menutup penjelasan. “Menteri-meneri di China bukan politisi. Mereka profesional teknokrat. Itu kuncinya. Bukan yang acak tapi yang implementatif.”
Florence menatap penuh rasa ingin tahu. “Contohnya?”
Saya pun melanjutkan dengan penuh antusias. Era Jiang Zemin (1993–2002). Pemerintah menetapkan visi, transparansi anggaran dan pengawasan publik. Perdana Menteri mengubah visi ini menjadi strategi digital, membangun sistem e-Government sejak tingkat kementerian sampai Pemda. Meluncurkan e-KTP, digital signature, infrastruktur data center nasional, dan jaringan TI yang menyeluruh. Ini bukan proyek parsial, tapi terintegrasi lintas lembaga. Era Hu Jintao (2002–2012). Reformasi dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menerapkan keterbukaan ekonomi dan birokrasi, menekankan meritokrasi teknokrat di lingkungan pemerintahan.
Era Xi Jinping (2012–sekarang). Visi diperluas lagi, dorongan untuk distribusi modal yang lebih adil, memastikan kemakmuran menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pencapaian teknologi konkret misalnya peluncuran sistem digital ID nasional (RealDID) dan Virtual ID, yang memperkuat ekosistem pemerintahan digital sejak 2023–2024.
Florence merenung, lalu menarik kesimpulan “Artinya, negarawan itu visioner dan tahu siapa yang mampu menjalankan visinya.”
Saya menimpali, “Betul! Great leaders don’t do everything—they build systems, hire experts, and guide the whole.”
Risa pun menegaskan. ” Pemisahan antara visionary leader dan professional manager itu esensial dalam organisasi kompleks seperti negara. Kalau nggak dipisah, visi bisa terjebak oleh rutinitas birokrasi. Terlalu teknokratis, inovasi terhambat, tanpa eksekusi, visi cuma wacana kosong. Harus ada orkestrasi.”
Wajah Florence tampak tercerahkan. Percakapan yang awalnya ringan kini berubah jadi sesi refleksi mendalam. Dari e-KTP hingga digital ID RealDID—contoh nyata bagaimana visi diubah menjadi sistem, lalu dieksekusi secara teknis. Dari Jiang ke Hu ke Xi, terlihat kesinambungan dan evolusi strategi pemerintahan digital dengan tujuan yang jelas dan berbeda tiap era.
Memimpin negara besar—atau organisasi mana pun—bukan soal kerja sendirian. Ini soal, Menentukan visi yang kuat dan relevan. Menjabarkannya sebagai sistem, memilih teknokrat yang tepat untuk mengelola. Memastikan pelaksanaan sistematis, dari perencanaan hingga pengawasan.
Dan di meja makan siang simple itu, indikator pentingnya: pertanyaan Florence yang penasaran, Risa yang menjelaskan dengan lugas, serta saya yang membantu menautkan narasi dengan analogi—semuanya membuat diskusi jadi hidup, menumbuhkan inspirasi, dan bahkan air mata Florence mengambang. Betapa dia merindukan Indonesia dipimpin dengan cara ini.
“ Di China, pemisahan antara visionary leader dan manager profesional justru dikedepankan. Presiden fokus pada visi, sementara PM dan menteri profesional yang teknokrat—yang dipilih karena kompetensi—bertanggung jawab pada perumusan dan pelaksanaan sistem secara detail. Sehingga organisasi berjalan sebagai orkestra yang harmonis, bukan sekedar kumpulan solis yang berlomba menarik perhatian” Risa menambahkan.
Florence menatap kami dengan mata berkaca, penuh penasaran.
“Gimana bisa jadi orkestrasi yang apik?” tanyanya lirih.
Risa tersenyum mengamati peluangnya menjelaskan. “Nah, itu tergantung leader-nya. Umumnya seorang pemimpin cenderung dominan di satu sisi—otak kanan—tapi kemampuan otak kirinya juga kuat. Dia tahu kriteria siapa yang pantas mendampingi, sehingga kepemimpinannya sukses tanpa mendominasi. Bahasa mesranya, humble ! dicintai bukan karena power, tapi karena inspirasi.”
Saya melihat perlahan air mata mengalir di mata Florence . Sebuah cerminan harapan dan kesadarannya. Mungkin dia membayangkan kesulitan menerapkan ini di Indonesia. Memang dari muda Florence aktifis Marhaen di Kampus. Dia sadar bahwa menempatkan orang yang tidak kompeten pada posisinya akan berdampak kerusakan sistematis pada setiap organisasi.
Extract dari East Asia Forum mengindikasikan bahwa kabinet Indonesia, di bawah Presiden Prabowo, banyak dipenuhi loyalis partai, bukan teknokrat efektif, sehingga “pressure to deliver but allegiance still prized. Mantan Kabinet Jokowi pernah diwarnai patronase dan politisasi demi kepentingan partai, bukan kompetensi—seperti dilaporkan Time dan Reuters . Amplifikasi ini membuat banyak menteri dan kepala daerah yang “mau jadi boss semua”—dan minim yang mau jadi manager professional.
“ Mengapa hal ini sulit di Indonesia? Tanya Florence.
“ Pertama karena Politik patronase dan pemilu. Banyak jabatan tinggi diisi oleh elit partai atau loyalis, bukan karena kompetensi teknis—termasuk sebagian besar Kabinet Prabowo. Kedua karena ukuran kabinet yang besar dan birokratis. Kabinet saat ini terbesar sejak era Orde Baru, dengan 108 posisi. Mengundang keraguan soal efektivitas dan duplikasi tugas. Ketiga karena ketergantungan pada loyalitas bukan kapabilitas. Banyak pejabat lebih ingin memperoleh jabatan daripada benar-benar bekerja, sehingga keputusan sering dipolitisasi dan eksekusi terhambat. “Kata saya.
“ Kesimpulannya, Risa menambahkan. “ jika Indonesia ingin membentuk orkestra pemerintahan yang apik, maka harus ada transformasi budaya politik dan birokrasi. Dari pejabat loyalis menjadi operator kompeten. Dari kabinet yang ribet menjadi tim profesional yang efektif. Dari dominasi visi presiden semata menjadi model kepemimpinan, visionary leader plus professional manager.”
“ Visi besar saja tidak cukup, harus diubah menjadi sistem & dieksekusi oleh orang yang tepat. Seperti yang Risa ungkap, kepemimpinan sukses bukan karena power, tapi karena inspirative. Itu adalah orkestra leadership yang sesungguhnya. “ Kata saya.
Disharmonisasi bahasa dan budaya, dialek Melayu Pontianak ala Risa, aksen Tionghoa yang khas dari Florence, bahkan selorohan ringan tentang identitas kampung, menyatukan diskusi serius kami, menjadikan pertemuan di Sheraton lebih dari sekadar makan siang: ini adalah kesempatan memperkaya perspektif dan menguatkan persahabatan.

Tinggalkan Balasan ke moeryonomoelyo Batalkan balasan