
Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia mencapai Rp6,97 juta per bulan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara statistik, angka ini tampak sebagai kabar baik dan sering dijadikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun, bagi sebagian besar pekerja—khususnya mereka yang berpenghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR) atau bekerja di sektor informal—angka tersebut terasa jauh dari pengalaman hidup sehari-hari. Perbedaan persepsi ini bukan sekadar soal perasaan, melainkan persoalan metodologi dan struktur ekonomi.
Secara metodologis, BPS tidak melakukan kesalahan. Angka Rp6,97 juta dihitung menggunakan mean aritmatika (rata-rata), yakni total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Namun, dalam literatur statistik dan ekonomi distribusi, rata-rata dikenal sangat sensitif terhadap nilai ekstrem. Kehadiran kelompok kecil dengan pendapatan sangat tinggi dapat mendorong rata-rata naik, meskipun pendapatan mayoritas penduduk tidak berubah secara signifikan.
Ilustrasinya sederhana. Bayangkan terdapat 1.000 orang. Satu orang berpenghasilan Rp5 miliar per bulan, sementara 999 orang lainnya secara kolektif hanya menghasilkan Rp1 miliar per bulan. Total pendapatan kelompok tersebut adalah Rp6 miliar. Ketika dibagi rata kepada 1.000 orang, pendapatan rata-rata menjadi Rp6 juta per orang per bulan. Dalam skenario ini, kenaikan rata-rata sepenuhnya ditentukan oleh satu individu berpendapatan sangat tinggi, bukan oleh peningkatan kesejahteraan mayoritas.
Fenomena inilah yang terjadi dalam skala nasional. Kenaikan rata-rata pendapatan terutama didorong oleh kelompok berpendapatan tinggi—pemilik modal, professional, elite, eksekutif, dan penerima rente ekonomi. Sementara itu, mayoritas pekerja Indonesia masih berada pada kisaran pendapatan Rp2,5–3,5 juta per bulan, bahkan sebagian mengalami tekanan pendapatan riil akibat kenaikan biaya hidup seperti pangan, energi, dan transportasi.
Karena itu, dalam analisis ketimpangan, median pendapatan dipandang jauh lebih representatif dibandingkan rata-rata, terutama di negara dengan distribusi pendapatan yang timpang. Literatur ekonomi, termasuk kajian World Bank, secara konsisten menegaskan bahwa median lebih mampu menangkap kondisi mayoritas rumah tangga. Jika median pendapatan Indonesia yang digunakan, besar kemungkinan angkanya jauh di bawah Rp6,97 juta dan lebih dekat dengan realitas pekerja mayoritas. Fakta ini sejalan dengan rasio Gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masih tinggi dan cenderung persisten.
Ketimpangan pendapatan di Indonesia bukan anomali statistik, melainkan konsekuensi struktural. Salah satu akar utamanya adalah struktur pendidikan tenaga kerja. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sekitar 65% tenaga kerja Indonesia berpendidikan SD hingga SLTA, sekitar 6% berpendidikan diploma, dan hanya 5–6% lulusan perguruan tinggi, dengan porsi pascasarjana sekitar 1%. Dengan komposisi seperti ini, mayoritas angkatan kerja berada pada kategori low education dan low skill.
| Tingkat Pendidikan | Persentase Tenaga Kerja |
| Tidak/Belum Tamat SD | ± 12% |
| Tamat SD/Sederajat | ± 28% |
| SLTP/Sederajat | ± 25% |
| SLTA/SMK/MA | ± 23% |
| Diploma (D1–D3) | ± 6% |
| S1/Sederajat | ± 5% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | ± 1% |
Dalam human capital theory (Becker, 1964), pendidikan berhubungan langsung dengan produktivitas, tingkat upah, mobilitas sosial, dan daya tawar individu di pasar kerja. Pendidikan bukan sekadar atribut sosial, melainkan determinan utama kemampuan seseorang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Struktur pendidikan yang didominasi lulusan dasar dan menengah membuat sebagian besar pekerja Indonesia secara sistemik terkunci pada pekerjaan berupah rendah, sektor informal, dan aktivitas ekonomi bernilai tambah minimal. Mobilitas menuju kelas menengah secara riil menjadi sangat terbatas, bukan karena kurangnya kerja keras, tetapi karena keterbatasan struktur kesempatan.
Ketimpangan pendidikan ini menciptakan segmentasi pasar tenaga kerja. Minoritas berpendidikan tinggi terserap ke sektor formal bernilai tambah tinggi—keuangan, teknologi, jasa profesional, dan manajemen—serta memiliki akses pada kepemilikan modal. Sebaliknya, mayoritas berpendidikan rendah bertahan di sektor informal, padat karya tradisional, atau subsisten.
Dalam struktur seperti ini, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional secara alami lebih banyak “ditangkap” oleh kelompok kecil berpendidikan tinggi, sementara mayoritas hanya mengalami kenaikan nominal yang tidak mampu mengimbangi inflasi. Inilah mekanisme struktural yang menjelaskan paradoks: rata-rata pendapatan naik, tetapi pendapatan median stagnan dan persepsi publik merasa tidak ikut sejahtera.
Atas dasar tersebut, World Bank menggunakan pendekatan absolute poverty line berbasis Purchasing Power Parity (PPP) dan standar hidup global, bukan sekadar UMR lokal atau garis kemiskinan administratif nasional. Pendekatan ini menilai apakah pendapatan seseorang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar menurut standar produktivitas dan konsumsi global. Dengan metodologi tersebut, sekitar 60–65% penduduk Indonesia dikategorikan miskin atau rentan miskin. Ini bukan manipulasi angka, melainkan refleksi dari rendahnya human capital, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan lemahnya kemampuan naik kelas secara struktural.
Implikasi kebijakan dari struktur ini sangat jelas. Model pembangunan Indonesia yang bertumpu pada pengolahan sumber daya alam (SDA) tidak selaras dengan kondisi demografis dan kualitas tenaga kerja nasional. Sektor SDA dan turunannya bersifat padat modal, berteknologi tinggi, dan terotomasi. Ia menghasilkan nilai tambah tinggi, tetapi menyerap tenaga kerja sangat terbatas dan memiliki keterkaitan lemah dengan ekonomi lokal.
Berdasarkan data BKPM, BPS, dan studi World Bank, investasi di sektor tambang, refinery, dan smelter rata-rata hanya menyerap ±800–1.200 tenaga kerja per Rp1 triliun investasi. Upahnya memang tinggi, tetapi hanya dinikmati oleh sedikit orang, sehingga efek kesejahteraan massalnya sangat terbatas. Model ini lebih cocok bagi negara kecil, capital-rich, dan berpenduduk sedikit—bukan bagi Indonesia yang padat penduduk dan didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah.
Sebaliknya, manufaktur padat karya—seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik ringan, dan FMCG—menunjukkan karakter jauh lebih inklusif. Sektor-sektor ini mampu menyerap 8.000–15.000 tenaga kerja per Rp1 triliun investasi, bahkan hingga 20.000 pekerja pada industri tekstil dan garmen. Manufaktur menengah seperti komponen otomotif masih menyerap 3.000–6.000 tenaga kerja, tetap beberapa kali lebih efektif dibandingkan sektor SDA.
| Sektor | Tenaga Kerja / Rp 1T |
| SDA & Smelter | ±1.000 |
| Manufaktur Menengah | 3.000–6.000 |
| Manufaktur Padat Karya | 8.000–15.000 |
Inilah inti diagnosis World Bank tentang middle income trap Indonesia. Indonesia tumbuh, tetapi tidak naik kelas. Masalahnya bukan kurang pertumbuhan, melainkan pertumbuhan dengan struktur yang salah. Pertumbuhan didorong oleh akumulasi modal, bukan peningkatan produktivitas tenaga kerja. PDB meningkat, tetapi output per pekerja stagnan, upah riil sulit naik, dan kelas menengah rapuh.
Solusi.
Perdebatan tentang middle income trap sering berhenti pada angka pertumbuhan dan struktur sektor, namun melupakan satu fondasi kunci: kualitas institusi. Literatur World Bank, Acemoglu & Robinson, hingga OECD menegaskan bahwa negara tidak hanya terjebak karena salah memilih mesin pertumbuhan, tetapi juga karena institusi yang gagal menegakkan aturan, meritokrasi, dan akuntabilitas. China dan India—dengan pendekatan berbeda—menunjukkan bahwa keluar dari jebakan pendapatan menengah menuntut kombinasi industrialisasi yang tepat dan institusi yang berfungsi.
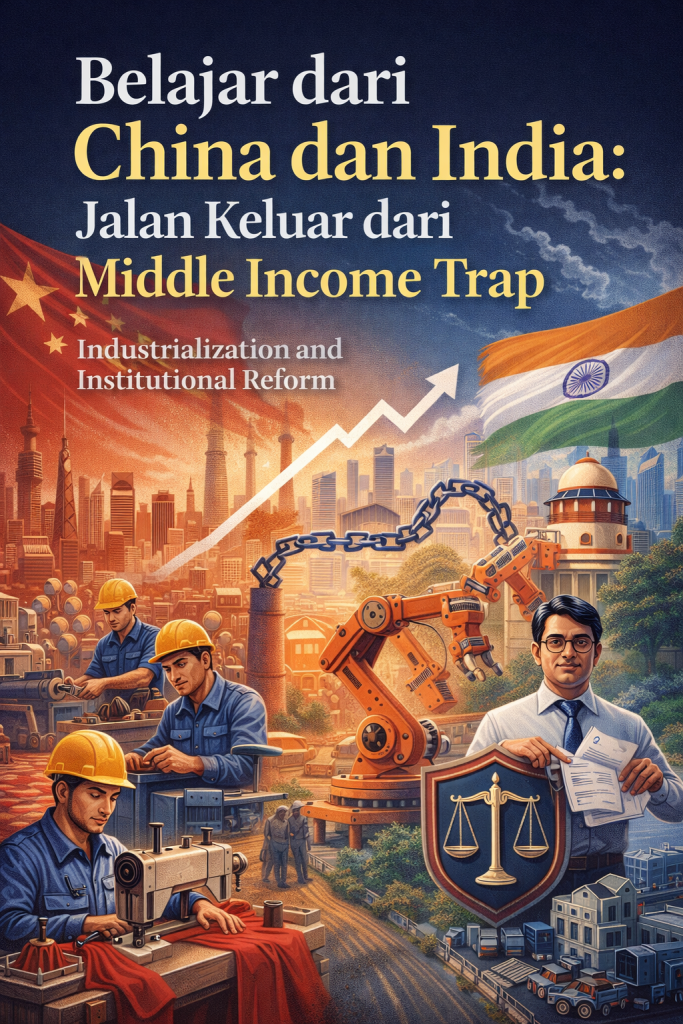
Keberhasilan China tidak semata hasil lonjakan teknologi, melainkan disiplin urutan kebijakan (sequencing) yang dijalankan oleh negara yang kapabel (capable state). Sejak reformasi akhir 1970-an, China memulai dari manufaktur padat karya berorientasi ekspor. Zona Ekonomi Khusus seperti Shenzhen dirancang bukan sebagai pusat teknologi tinggi, tetapi sebagai mesin penyerapan tenaga kerja massal dengan aturan yang jelas, kepastian kontrak, dan infrastruktur yang siap.
Kunci yang sering diabaikan adalah kepastian kebijakan dan penegakan aturan. Investor mendapat sinyal yang konsisten: kontrak dihormati, izin jelas, dan target kinerja birokrasi terukur. Meritokrasi internal Partai dan birokrasi—meski dalam sistem non-demokratis—menciptakan insentif kinerja yang kuat. Upah naik setelah produktivitas naik; industrial upgrading dilakukan setelah basis manufaktur mapan. Ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Justin Yifu Lin dalam New Structural Economics, industri harus mengikuti keunggulan faktor produksi pada tiap tahap. World Bank mencatat, kombinasi industrialisasi massal dan institusi yang mampu mengeksekusi memungkinkan China melewati fase pendapatan menengah tanpa stagnasi upah dan produktivitas.
India menempuh jalur berbeda—lebih plural dan demokratis—namun tetap menunjukkan pelajaran institusional penting. Reformasi 1991 membuka ekonomi, tetapi terobosan kunci datang dari penguatan institusi ekonomi: reformasi pajak nasional (GST) untuk transparansi dan efisiensi, liberalisasi FDI sektoral dengan rule-based governance, serta digitalisasi layanan publik untuk mengurangi rent-seeking.
India memanfaatkan skala pasar domestik sebagai mesin pertumbuhan, menyerap output melalui konsumsi internal, sembari memperkuat manufaktur melalui Make in India. Meski penegakan hukum dan birokrasi masih menjadi tantangan, arah kebijakan yang lebih transparan dan meritokratik—khususnya di sektor teknologi, farmasi, dan jasa profesional—mendorong produktivitas dan investasi jangka panjang. World Bank menilai, kemampuan India menjaga momentum pertumbuhan berasal dari kombinasi pasar besar, reformasi institusional bertahap, dan kepastian aturan, sehingga pertumbuhan tidak sepenuhnya bergantung pada komoditas primer.
Dari China dan India, satu benang merah penting yaitu, mesin pertumbuhan yang tepat tidak akan bekerja tanpa institusi yang kredibel. Industrialisasi padat karya, vokasi massal, dan upgrading teknologi hanya efektif jika didukung oleh penegakan hukum yang konsisten (kontrak, kepemilikan, kepastian usaha). Transparansi kebijakan (aturan jelas, perubahan tidak mendadak). Meritokrasi birokrasi (promosi berbasis kinerja, bukan patronase). Akuntabilitas demokratis (pengawasan publik dan lembaga). Sebaliknya, negara yang terlalu cepat melompat ke industri padat modal, bertumpu pada SDA, dan membiarkan tata kelola lemah, cenderung mengalami pertumbuhan elitis—tinggi di atas kertas, rapuh secara sosial.
Diagnosis World Bank terhadap Indonesia harus dibaca dalam kerangka ini. Indonesia bukan kekurangan pertumbuhan, tetapi tumbuh dengan struktur dan institusi yang belum selaras. Ketergantungan pada SDA dan industri padat modal membatasi penciptaan kerja; di saat yang sama, ketidakpastian kebijakan, penegakan hukum yang inkonsisten, dan lemahnya meritokrasi meningkatkan risk premium dan menahan investasi produktif.
Pelajaran dari China dan India jelas, yaitu keluar dari middle income trap menuntut reorientasi mesin pertumbuhan (manufaktur padat karya, substitusi impor, ekspor bernilai tambah) sekaligus penguatan institusi demokrasi—penegakan hukum, transparansi, dan meritokrasi. Tanpa itu, kenaikan PDB akan terus berulang sebagai statistik, bukan sebagai mobilitas sosial yang nyata. Middle income trap bukan kutukan ekonomi; ia adalah konsekuensi pilihan kebijakan dan kualitas institusi. Negara yang berani membenahi keduanya dapat naik kelas. Negara yang menunda akan terus tumbuh—tetapi tidak pernah benar-benar maju.
Referensi.
World Bank (2020) Worldwide Governance Indicators (WGI), rule of law, government effectiveness, dan corruption control. World Bank (2018) World Development Report: Learning to Realize Education’s Promise. World Bank (2012) China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society Washington, DC: World Bank. World Bank (2023) Avoiding the Middle-Income Trap: East Asia’s Lessons for Indonesia Washington, DC. World Bank (2024) Indonesia Economic Prospects.
Eichengreen, B., Park, D., & Shin, K. (2013) “Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap” Journal of Economic Growth, 18(2), 111–138. Felipe, J., Abdon, A., & Kumar, U. (2012) “Tracking the Middle-Income Trap: What Is It, Who Is in It, and Why?” ADB Economics Working Paper No. 306. Becker, G. S. (1964) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis Chicago: University of Chicago Press. OECD (2020) Education at a Glance. Lin, J. Y. (2012) New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development Washington, DC: World Bank. Rodrik, D. (2016) “Premature Deindustrialization” Journal of Economic Growth, 21(1), 1.33. UNIDO (2022) Industrial Development Report.
Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012) Why Nations Fail New York: Crown Business. North, D. C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance Cambridge University Press. Badan Pusat Statistik (BPS) Sakernas & Statistik Pendapatan Penduduk (berbagai tahun). BKPM / Kementerian Investasi (2022–2025) Realisasi Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja. ILO (2021) Global Employment Trends for Industry. Asian Development Bank (ADB) (2020) Asia’s Manufacturing Renaissance?

Tinggalkan komentar