
Di negara agraris, harga beras seharusnya menjadi jangkar stabilitas ekonomi. Ia semestinya menenangkan inflasi, menjaga daya beli, dan memberi rasa aman sosial. Namun di Indonesia, beras justru berperan sebaliknya: menjadi sumber inflasi struktural, tekanan berkelanjutan bagi konsumsi rumah tangga, dan paradoks kebijakan yang terus berulang.
Harga beras domestik secara konsisten lebih mahal dibandingkan beras impor, bahkan ketika produksi nasional diklaim surplus. Ini bukan kegagalan cuaca. Ini kegagalan desain sistem. Masalah beras Indonesia tidak terletak di sawah, melainkan pada model bisnis pangan nasional—pada cara negara memproduksi, mendistribusikan, dan membaca pasar.

Produksi padi nasional masih bertumpu pada petani kecil, lahan terfragmentasi, dan mekanisasi terbatas. Model ini melahirkan biaya per unit yang tinggi, produktivitas yang stagnan, serta ketergantungan kronis pada subsidi input. Secara bisnis, Indonesia memproduksi beras dengan struktur biaya artisanal, lalu memaksakannya masuk ke pasar konsumsi massal. Di sinilah mismatch struktural terjadi: model produksi skala kecil dipaksa melayani pasar besar yang menuntut efisiensi.
Sebaliknya, beras impor lahir dari pertanian skala industri—lahan luas, mekanisasi penuh, pascapanen efisien, dan logistik bulk yang terintegrasi. Harga impor yang lebih murah bukan akibat praktik tidak adil, melainkan keunggulan struktur biaya. Pasar global memberi pelajaran sederhana: skala dan efisiensi menentukan harga, bukan slogan kedaulatan.
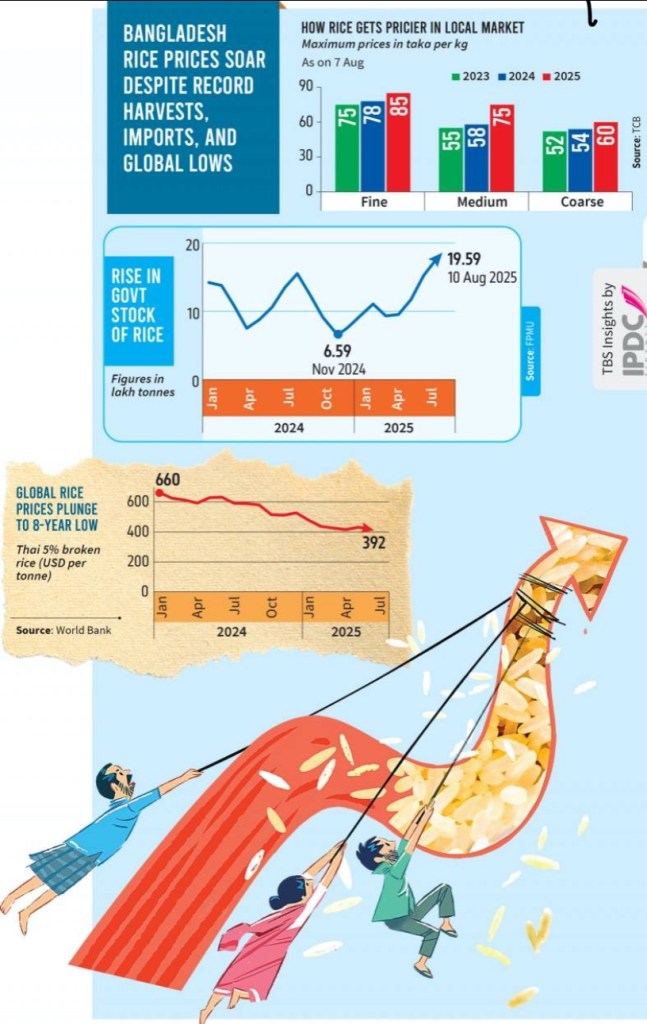
Namun persoalan beras domestik tidak berhenti di produksi. Harga melonjak bukan karena petani menikmati margin besar. Justru sebaliknya, petani hanya menerima sekitar sepertiga dari harga akhir. Sisanya terserap dalam rantai distribusi yang panjang dan terfragmentasi: penggilingan, broker, distributor, grosir, hingga pengecer. Setiap mata rantai menambahkan margin, menahan stok, dan memainkan waktu.
PETANI ████████░░░░░░░░░░ 32% Rp4.500
PENGGILINGAN ███░░░░░░░░░░░░░░░ 13% Rp1.800
DISTRIBUTOR/TRADER █████░░░░░░░░░░░░░ 18% Rp2.500
GROSIR ███░░░░░░░░░░░░░░ 11% Rp1.500
PENGEcer ███░░░░░░░░░░░░░░ 12% Rp1.700
LOGISTIK & STOK ████░░░░░░░░░░░░░ 14% Rp2.000
Ini bukan value chain yang menciptakan efisiensi, melainkan rent-seeking supply chain. Dalam bahasa ekonomi industri, pasar beras menunjukkan ciri oligopoli terselubung: pemain terbatas, koordinasi informal, dan harga yang tidak responsif terhadap surplus. Akibatnya, mekanisme pasar kehilangan fungsi koreksi. Harga tidak turun saat panen raya. Kelangkaan dikelola. Konsumen membayar, petani tetap miskin.
Distorsi ini diperkuat oleh kebijakan protektif yang tidak disertai reformasi struktural. Pembatasan impor sering dibungkus dengan narasi perlindungan petani dan swasembada. Namun proteksi yang berdiri sendiri hanya mengunci inefisiensi. Negara melindungi tata niaga, bukan produktivitas. Subsidi input tidak berujung pada modernisasi. Konsolidasi lahan tidak berjalan. Distribusi tetap panjang dan mahal.
Dalam kacamata bisnis, kebijakan ini setara dengan mempertahankan perusahaan tidak kompetitif tanpa restrukturisasi, lalu berharap harga turun dengan sendirinya. Mustahil. Impor seharusnya berfungsi sebagai price anchor—referensi efisiensi dan alat disiplin pasar. Ketika impor diposisikan sebagai musuh ideologis, pasar domestik kehilangan pembanding. Inflasi pangan pun menjadi struktural, bukan temporer.
Model yang berjalan hari ini melahirkan paradoks klasik. Beras mahal, petani tetap miskin, dan negara terus mengulang siklus intervensi. Beban jatuh ke konsumen, terutama kelas menengah bawah. Daya beli tergerus, dan inflasi pangan menular ke sektor lain. Ini bukan sekadar isu pangan. Ini isu daya saing ekonomi nasional.
Pertanyaannya kemudian, mengapa distorsi ini terus terjadi, dan mengapa negara tampak gagal membacanya? Jawabannya bukan karena negara tidak tahu, melainkan karena insentif kebijakan, struktur birokrasi, dan narasi politik membuat distorsi terlihat normal—bahkan dianggap keberhasilan. Dalam desain kebijakan pangan nasional, indikator keberhasilan masih didominasi oleh luas tanam, volume produksi, angka surplus, dan serapan gabah. Sementara indikator harga riil di konsumen, margin tata niaga, dan konsentrasi pelaku pasar jarang menjadi variabel utama. Akibatnya, negara merasa berhasil saat panen tinggi, meski harga di pasar tetap mahal. Ini blind spot struktural: kebijakan membaca sawah, bukan pasar.
Masalah ini diperparah oleh data pangan yang terfragmentasi. Kementerian teknis, lembaga pangan, BUMN, dan pemerintah daerah menggunakan basis data, metodologi, dan kepentingan pelaporan yang berbeda. Produksi, stok, distribusi, dan harga tidak pernah berada dalam satu dashboard kebijakan yang utuh. Yang muncul adalah paradoks administratif. Surplus di laporan, kelangkaan di pasar, dan inflasi di konsumen. Bukan karena data palsu, tetapi karena data tidak pernah disatukan secara fungsional.
Lebih jauh, pangan telah lama menjadi instrumen politik, bukan agenda reformasi struktur. Sebagai isu elektoral paling sensitif, kebijakan pangan cenderung diarahkan pada stabilisasi jangka pendek, operasi pasar simbolik, narasi swasembada, dan distribusi bantuan. Reformasi yang menyentuh kartel distribusi, konsolidasi lahan, restrukturisasi penggilingan, atau pembukaan impor sebagai price anchor sering dihindari karena tidak populer, berisiko konflik elite, dan tidak menghasilkan efek instan. Maka kebijakan pangan menjadi reaktif, bukan korektif.
Di sisi lain, distorsi tata niaga menguntungkan terlalu banyak pihak. Rantai distribusi panjang bukan kecelakaan, melainkan ekosistem rente yang melibatkan tengkulak besar, penggilingan dominan, trader stok, logistik regional, bahkan sebagian aktor lokal. Dalam struktur seperti ini, harga mahal bukan kegagalan sistem, melainkan hasil yang diharapkan oleh sebagian pelaku. Biaya politik untuk membongkarnya tinggi, manfaat fiskalnya kecil, dan resistensinya luas.
Ironinya, negara begitu takut pada impor—dipandang sebagai ancaman kedaulatan dan simbol kegagalan nasional—namun tidak takut pada inflasi pangan yang permanen. Padahal secara ekonomi, impor adalah instrumen disiplin pasar, pembanding efisiensi, dan penahan spekulasi stok. Ini bukan kesalahan teknis, melainkan kesalahan paradigma.
Semua ini terjadi karena birokrasi dirancang untuk menjalankan program, bukan mengevaluasi sistem. Aparatur didorong untuk menyerap anggaran, melaksanakan kegiatan, dan melaporkan output—bukan untuk mengukur dampak harga, menilai struktur pasar, atau menantang desain kebijakan. Distorsi tidak terlihat karena tidak ada insentif institusional untuk mencarinya.
Jika beras ingin murah tanpa memiskinkan petani, arah kebijakan harus bergeser secara fundamental: dari proteksi ke produktivitas, dari subsidi ke investasi mekanisasi, dari rantai panjang ke integrasi distribusi, dan dari larangan impor ke benchmark harga global. Impor bukan ancaman kedaulatan. Ia adalah alat disiplin pasar. Petani tidak perlu dilindungi dari harga murah, tetapi dari biaya tinggi akibat sistem yang salah.
Pada akhirnya, harga beras yang mahal adalah cermin dari desain ekonomi yang keliru. Selama negara memilih menjaga rente alih-alih efisiensi, beras akan tetap mahal dan petani akan tetap berada di tepi sistem. Nasionalisme pangan tidak diukur dari seberapa tinggi harga dipertahankan, melainkan dari seberapa efisien negara memberi makan rakyatnya. Di sinilah ekonomi diuji, bukan pada slogan, melainkan pada struktur. ***
Referensi.
FAO. The State of Agricultural Commodity Markets. World bank. Food Price Volatility and the Role of Market Structure. OECD. Agricultural Policies and Market Distortions. ADB. Food Security and Market Integration in Asia.International Food Policy Research Institute(IFPRI).Political Economy of Food Price Policies. BPS.Statistik Harga Konsumen & Produksi Padi. Badan Pangan Nasional. Laporan Neraca Pangan dan Stabilitas Harga. Bulog. Peran Cadangan Pangan dan Operasi Pasar. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.Data Luas Tanam, Produksi, dan Subsidi Input.IMF.Inflation Dynamics in Emerging Markets.Timmer, C. Peter.Food Prices and Market Behavior in Developing Countries.Stiglitz, Joseph E.The Role of the State in Market Economies.

Tinggalkan komentar