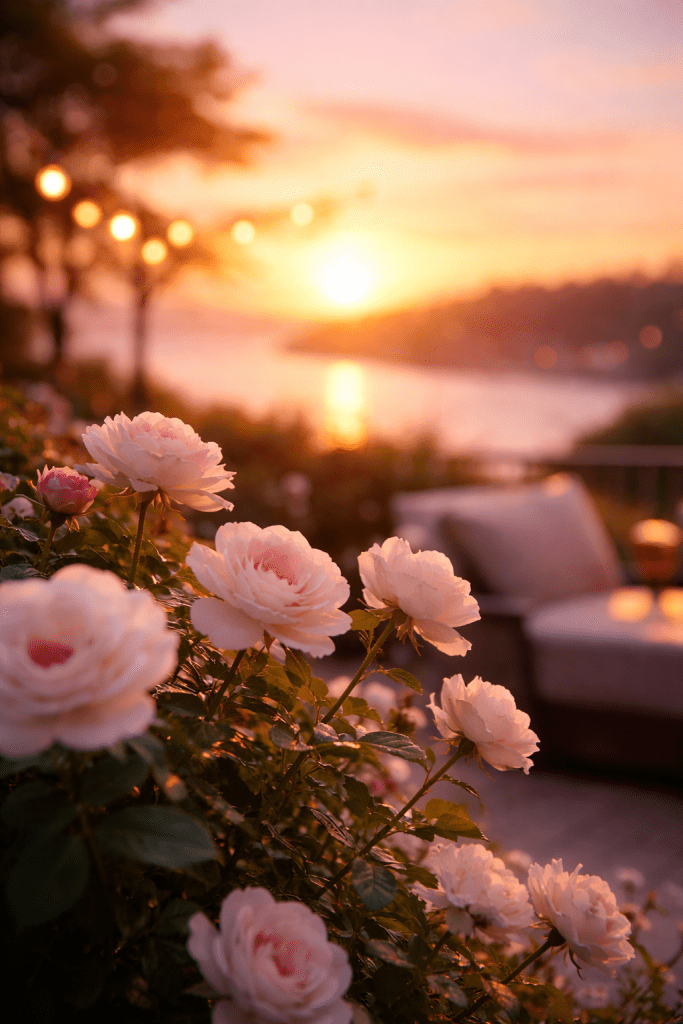
Aku mengenal Ale pada tahun 1985, di sebuah ruang kursus manajemen. Gedungnya tidak megah, tapi ada di jantung kota dan Kawasan Menteng. Peserta kursus umumnya adalah pegawai BUMN dan wirasausaha. Ale termasuk yang wirausaha. Ia duduk di baris tengah, selalu sedikit menunduk. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, seperti seseorang yang terlalu lama hidup di bawah matahari dan terlalu jarang diberi jeda. Bajunya sederhana, rapi, tapi tidak berusaha menonjol. Ia tidak pernah lebih dulu bicara, tidak pernah memotong pembicaraan. Jika ditanya, ia menjawab singkat, tepat, tanpa bumbu. Jika tidak ditanya, ia diam, diam yang tidak kosong, melainkan penuh perhatian. Banyak yang mengira ia bodoh. Atau setidaknya tidak ambisius. Dalam ruang seperti itu, diam sering dianggap tidak punya isi.
Aku berbeda. Aku datang dengan kesadaran penuh tentang diriku sendiri. Aku bekerja pada peruahaan Papa ku. Walau bukan konglomerat tapi termasuk kelas menengah. Aku tahu aku cantik. Aku tahu senyumku bekerja seperti kunci. Aku tahu bagaimana menatap tanpa terlihat menantang, bagaimana tertawa tanpa terdengar murahan. Aku sudah belajar sejak awal bahwa perempuan sepertiku tidak diberi kemewahan untuk hanya pintar. Kami harus menyenangkan, luwes, dan tahu kapan harus mendekat. Aku tidak malu mengakui itu. Dunia tidak pernah adil untuk perempuan, maka kami belajar menyesuaikan diri.
Di tempat kursus itu, aku cepat dikenal. Aku mendengar rencana bisnis, gosip proyek, juga bisik-bisik tentang siapa anak siapa. Aku tahu jaringan adalah mata uang yang nilainya lebih stabil dari ijazah. Pamanku petinggi milter dan tentu tidak sulit bagiku masuk dalam lingkaran. Ale tak pernah masuk lingkaran itu. Ia selalu duduk dengan buku catatan lusuh, mencoret-coret sesuatu yang tak pernah kutanyakan. Kadang, saat istirahat, aku melihatnya membaca ulang modul dengan penuh kesabaran, seperti seseorang yang percaya bahwa pengetahuan bisa menyelamatkan hidupnya.
Sekali waktu, instruktur bertanya tentang efisiensi produksi. Ruangan riuh. Banyak yang menjawab panjang, berputar-putar. Ale mengangkat tangan—pelan, seolah takut mengganggu.
“Kalau efisiensi,” katanya, “bukan soal memangkas orang. Tapi memangkas pemborosan proses. Dan itu perlu teknologi.” Semua menoleh. Suaranya datar, hampir tanpa intonasi. Ia menyebut angka. Rasio. Contoh kecil. Logis. Bersih. Ruangan mendadak sunyi. Instruktur mengangguk. Aku memperhatikannya lama. Untuk pertama kali. Namun kekaguman bukan sesuatu yang tumbuh mudah dalam diriku. Aku sudah terlalu sering melihat orang pintar gagal karena tidak punya pelindung. Dan Ale… ia terlalu jujur untuk dunia yang penuh perantara.
Kami mulai berbicara karena kebetulan. Satu sore, hujan turun deras. Banyak orang berteduh di lorong. Ale berdiri agak jauh, menunggu hujan reda. Maklum Jakarta ketika hujan datang, macetpun datang. Aku menghampirinya.
“Kamu selalu pulang sendiri?” tanyaku.
“Iya,” katanya.
“Kamu tidak ikut nongkrong?”
Ia menggeleng. “Tidak perlu.”
Jawabannya membuatku tertawa kecil. Tidak perlu. Kalimat yang terlalu bersih untuk zaman yang penuh kepentingan.
Sejak itu kami sering berbincang. Ia tidak pernah menggoda. Tidak pernah memuji. Ia bertanya hal-hal yang aneh. Tentang buku yang kubaca, tentang mengapa aku memilih kelas ini, tentang apa yang menurutku adil dalam hidup. Aku, yang terbiasa dibanjiri pujian, justru merasa kikuk. Ada sesuatu dalam caranya memandang. Bukan menilai, bukan menginginkan, hanya melihat.
Beberapa bulan kemudian aku tahu ia sedang mengerjakan sesuatu. Mesin tenun. Ia menyebutnya sambil lalu, seperti orang menyebut cuaca. “Mesin impor mahal,” katanya. “Padahal prinsipnya bisa disederhanakan.”
Ia menunjukkan sketsa. Rumit, tapi masuk akal. Ia bicara tentang efisiensi, tentang memotong biaya tanpa menurunkan mutu. Tentang bagaimana industri dalam negeri bisa berdiri jika tidak terus bergantung.
Aku mendengarkan, setengah tertarik, setengah skeptis.
“Kamu mau bikin pabrik?” tanyaku.
“Iya,” katanya pelan.
Aku tertawa, bukan mengejek, tapi refleks. Dunia ini tidak ramah pada mimpi semacam itu.
“Kamu punya modal?” tanyaku.
Ia menggeleng.
“Koneksi?”
Ia tersenyum kecil.
“Belum.”
Saat itu aku tahu. Ale sedang berdiri di tepi jurang yang sering kulihat, tempat orang jujur jatuh karena percaya dunia bekerja sesuai buku. Namun aku tidak mengatakan itu padanya. Aku hanya berkata, “Kalau kamu mau, aku bisa kenalkan ke orang-orang.”
Matanya menyala. Tidak berlebihan. Tapi cukup untuk membuatku sadar. Aku baru saja membuka pintu yang tidak sepenuhnya kumengerti.
Hari-hari berikutnya, kami semakin sering bertemu. Ia bercerita tentang mesin, tentang efisiensi, tentang bagaimana teknologi bisa membebaskan orang dari ketergantungan. Aku bercerita tentang orang-orang yang kutemui, tentang bagaimana keputusan dibuat bukan di meja rapat, melainkan di ruang makan dan kamar hotel. Kami datang dari dua dunia yang berbeda, tapi untuk sementara, kami berdiri di persimpangan yang sama. Aku tidak tahu saat itu bahwa persimpangan ini kelak akan menjadi titik luka.
Aku juga tidak tahu bahwa lelaki kurus yang duduk di hadapanku, dengan suara tenang dan mata jujur, kelak akan menjadi cermin paling keras dalam hidupku. Cermin yang kelak memantulkan bukan wajahnya, tetapi diriku sendiri. Dan bahwa suatu hari, aku akan menyadari. Ada orang yang berjalan lambat bukan karena ia lemah, melainkan karena ia menolak berlari di jalan yang kotor.
***
Aku mulai sering menemani Ale ke bengkel kecil di pinggir kota. Bangunannya bekas gudang, lantainya retak, atap sengnya bocor di beberapa bagian. Di sanalah teamnya bekerja, kadang hingga malam, membongkar, menyetel, mengukur ulang mesin yang dirakit sendiri. Aku perhatikan semua team sangat patuh kepada Ale. Dia tidak terkesan boss, tetapi lebih terkesan sahabat. Ia tidak pernah mengeluh. Tapi matanya menyala setiap kali berbicara tentang rasio putaran, efisiensi daya, atau ketahanan komponen.
“Mesin ini bisa menurunkan biaya sampai seperlima,” katanya suatu sore. “Bukan karena murah, tapi karena tidak boros.” Ia bicara seperti seseorang yang yakin dunia bisa diperbaiki dengan perhitungan yang benar. Aku mendengarkan sambil bersandar di dinding, rokku sedikit kotor oleh debu. Aku tahu, di tempat seperti itu, mimpi sering lahir, dan sering mati sebelum sempat diberi nama.
“Ale,” kataku akhirnya, “kamu tahu berapa banyak orang yang punya ide bagus tapi tidak pernah jadi apa-apa?”
Ia menoleh.
“Karena mereka tidak punya akses,” lanjutku. “Bukan karena idenya jelek.”
Ia mengangguk pelan. “Makanya aku belajar,” katanya. “Supaya suatu hari, aku tidak bergantung.” Kalimat itu terdengar tulus. Terlalu tulus.
Aku menatapnya lama. Dalam kepalaku, sudah terbentuk peta lain, bukan mesin, bukan efisiensi, tapi nama-nama. Orang-orang yang bisa membuka pintu. Orang-orang yang bisa membuat sesuatu “resmi”.
“Aku bisa kenalkan kamu ke seseorang,” kataku akhirnya. Ia menatapku dengan mata berbinar. Bukan penuh nafsu, bukan ambisi liar, melainkan rasa percaya. Rasa percaya yang polos, yang membuatku, entah mengapa, merasa sedikit bersalah.
Orang itu bernama Andi. Ia anak dari ring kekuasaan. Kekuasaan mereka tidak selalu terlihat, tapi terasa di mana-mana. Di meja rapat, di kantor bank, di balik telepon yang langsung diangkat tanpa dering panjang. Ia muda, rapi, dan terbiasa dilayani. Ketika berbicara, orang lain menyesuaikan nada. Kami bertemu di sebuah restoran yang terlalu tenang untuk kota ini. Lampunya redup, pelayannya berbisik. Andi datang dengan senyum tipis, senyum orang yang sudah tahu ia akan diuntungkan, tinggal menunggu bagaimana.
Ale mempresentasikan mesinnya. Data, skema, uji coba. Ia bicara hati-hati, berusaha tidak berlebihan. Aku melihat kekaguman kecil di mata Andi, bukan kekaguman pada Ale, melainkan pada peluang.
“Menarik,” katanya akhirnya. “Biaya rendah, margin tinggi.”
Ale mengangguk, menahan napas.
“Kita bisa bikin pabrik,” lanjut Andi. “Skala menengah dulu. Kalau jalan, kita kembangkan.” Ia bicara seolah semuanya sederhana. Dan memang, bagi orang seperti dia, segalanya selalu tampak sederhana.
Seminggu kemudian, MoU ditandatangani. Aku masih ingat wajah Ale hari itu. Senyum kecil, hampir tidak percaya. Ia menatap kertas itu seperti seseorang yang akhirnya mendapat bukti bahwa dunia tidak sepenuhnya kejam. Aku ikut tersenyum. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang dingin bergerak perlahan. Aku tahu, kertas hanyalah kertas. Dan dalam dunia orang-orang seperti Andi, kertas bisa diganti, ditafsirkan ulang, atau diabaikan bila perlu.
6 bulan kemudian, pabrik berdiri. Tanpa memberi tahu Ale. Justru Ale tahu dari orang lain. Aku dan Adi bermitra dalam bisnis yang ide dan design dari Ale. Berkali kali Ale telp aku untuk bertemu. Aku selalu menolak. Akhirnya aku temui juga dia.
“Mengapa Mey? Apa salahku ” tanyanya lirih.
“Ale,” kataku akhirnya, “kamu naif! .”
Ia menatapku lama. Aku bisa melihat kebingungan bercampur luka. Tapi juga sesuatu yang lebih dalam, pengkhianatan.
“Dari awal aku percaya kamu, Mey,” katanya. “Mengapa ?
Aku tidak menyangkal. Aku tidak menjelaskan. Karena pada titik itu, penjelasan hanyalah bentuk lain dari pembenaran.
“Bahkan teamku kamu bajak juga ?” Katanya sambil geleng geleng kepala
Ia terdiam.
“Kamu mau melawan?” aku lanjutkan. “Dengan apa? Dengan idealisme?”
Ia tidak menjawab.
“Kamu pintar,” kataku lagi, nadaku kini dingin. “Tapi kamu tidak punya urat kaya. Kamu hanya orang kampung. Dunia ini tidak dibangun oleh orang jujur, Ale. Dunia ini dibangun oleh orang yang tahu kapan harus membengkok.”
Ia menatap lantai.
Aku tahu aku sedang kejam. Tapi aku juga tahu, kejujuran seringkali hanya kemewahan bagi mereka yang tidak perlu bertahan hidup.
“Aku kecewa padamu,” katanya akhirnya. Suaranya tidak tinggi. Tidak marah. Justru itu yang membuatnya menyakitkan. Aku ingin berkata sesuatu. Apa saja. Tapi yang keluar justru kalimat paling buruk “Itu bukan urusanku.” Kataku ketus.” Bagiku kamu bukan siapa siapa.”
Ia pergi tanpa suara.
Dan sejak hari itu, aku tahu, aku telah memilih jalan yang tidak bisa kutinggalkan tanpa kehilangan sesuatu dari diriku sendiri. Ale menghilang dari hidupku. Aku dengar kabar ia tetap berbisnis tetap membuat ide baru, berpindah-pindah, jatuh dan bangun. Aku tidak mencarinya. Aku sibuk naik. Dunia memberiku panggung, akses, relasi. Aku belajar berbicara seperti mereka, berpikir seperti mereka, menertawakan apa yang mereka tertawakan.
Namun ada malam-malam tertentu, ketika lampu kota terlalu terang dan kota terlalu sunyi, wajah Ale muncul begitu saja, dengan tatapan itu. Tatapan orang yang tidak menuntut penjelasan, tapi membuatmu ingin menjelaskan segalanya. Aku belum tahu saat itu bahwa pertemuan kami belum selesai. Bahwa waktu, seperti mesin yang ia rancang, bekerja diam-diam. Menyimpan energi, menunggu saat yang tepat untuk berputar kembali.
***
Aku tidak pernah bermimpi menjadi orang baik. Sejak awal aku hanya ingin bertahan. Di negeri ini, bertahan sering kali berarti tahu kapan harus menunduk, kapan harus tersenyum, dan kapan harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah peristiwa dengan Ale, aku belajar satu pelajaran penting. Dunia tidak menghukum pengkhianatan, dunia hanya menghukum kegagalan. Apapun alasanya. Kegagalan itu karena kelemahan dan kebodohan. Dan aku tidak berniat gagal.
Aku masuk lebih dalam ke ruang-ruang yang dulu hanya kulihat dari jauh. Ruang berpendingin dingin, berkarpet tebal, penuh pria yang berbicara pelan tetapi memutuskan nasib banyak orang. Di sana, keputusan tidak dibuat lewat argumen, melainkan lewat kesepahaman tak tertulis. Siapa berguna, siapa bisa dipercaya, siapa bisa diam. Begitu rezim orde baru dibangun. Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sudah seperti air susu ibu.
Aku belajar membaca bahasa tubuh. Mengetahui kapan sebuah senyum berarti undangan, dan kapan berarti peringatan. Aku belajar bahwa dalam dunia ini, kejujuran hanya berguna jika dibungkus kecerdikan. Dan kesetiaan hanyalah nama lain dari kepentingan yang belum diuji.
Aku mulai dikenal. Sebagai pengusaha, yang punya akses lobi politik. Seseorang yang bisa membuka pintu. Yang tahu siapa harus diajak bicara, siapa harus dihindari. Aku tahu cara menyebut angka tanpa menyebutnya. Cara menjanjikan tanpa menjanjikan. Cara membuat orang merasa aman tanpa benar-benar memberi jaminan. Aku tidak bangga. Tapi aku juga tidak menyesal.
Dalam lingkaran itu, perempuan seperti aku jarang dipandang sebagai subjek. Kami dilihat sebagai ornamen, penghangat suasana, atau jembatan lunak yang membuat negosiasi terasa lebih manusiawi. Aku memanfaatkan itu. Jika dunia hanya memberiku peran sempit, aku akan menguasainya sampai ke detail paling halus.
Dan begitulah aku menjauh dari Ale. Bukan karena benci. Tapi karena ia mengingatkanku pada sesuatu yang berbahaya, rasa bersalah. Ia terlalu jujur. Terlalu percaya bahwa niat baik akan menemukan jalannya sendiri. Padahal aku tahu, jalan itu sering dipotong oleh mereka yang tidak sabar.
Tahun-tahun berlalu. Aku berpindah dari satu lingkar ke lingkar lain. Aku belajar bahwa kekuasaan tidak selalu berisik. Ia sering datang dalam bentuk undangan makan malam, perjalanan singkat ke luar negeri, atau panggilan telepon larut malam. Aku belajar bahwa banyak lelaki kuat justru rapuh di hadapan pengakuan. Mereka ingin dikagumi, diakui, dan diyakinkan bahwa mereka penting. Aku tahu bagaimana caranya. Aku juga tahu harga yang harus dibayar.
Kadang aku bertanya pada diriku sendiri. Kapan tepatnya aku berhenti merasa bersalah? Aku tidak tahu. Barangkali rasa itu menipis perlahan, seperti suara radio tua yang makin jauh. Yang tersisa hanya kewaspadaan. Tahun 1998, terjadi krisis moneter. Aku tidak peduli. Siapapun rezim yang berkuasa. Old money tetap yang berkuasa. Tahun 2004 aku dengar dari ring kekuasaan, bahwa Ale hijrah ke China. Aku tersenyum saja mendengar itu. Membayangkan wajah naif nya. Di negeri sendiri saja dia tidak berharga, apalagi di negeri orang.
***
Tahun 2011. Aku mendengar nama Ale lagi. Kali ini bukan sebagai teknisi, bukan sebagai pemimpi, melainkan sebagai pemilik holding investasi di Hong Kong. Orang-orang menyebutnya dengan nada berbeda. Lebih hati-hati. Lebih hormat. Aku terkejut. Tidak iri—lebih seperti heran. Orang seperti dia, yang dulu tampak tak cocok dengan dunia keras, ternyata bertahan.
Aku mencari tahu. Ia tidak menonjol. Tidak muncul di media. Tidak gemar konferensi. Tapi namanya muncul di balik struktur, di belakang perusahaan, dalam dokumen yang jarang dibaca orang awam. Ia bergerak perlahan, nyaris tak terlihat. Seperti air tanah.
Pada saat yang sama, aku sedang terjerat dalam satu perkara besar. Akibat harga batubara terjun bebas.. Empat IUP ku dari empat perusahaan. Semuanya tampak kokoh di atas kertas, tapi rapuh di dalam. Utang menumpuk. Harga komoditas tak menentu. Kami butuh dana segar—USD 150 juta untuk menunda kehancuran. Aku hanya pemegang saham minoritas. Pemegang mayoritas adalah elite yang diwakili keluarganya. Walau kami bisa kuasai akses dalam negeri, namun soal financial resource luar negeri kami tidak punya kemampuan.
Aku menyarankan satu nama Ale kepada pemegang saham lainnya. Awalnya mereka ragu. “Dia siapa?”
Aku berkata, “Dia tahu bagaimana bicara dengan uang.” Itu setengah bohong. Tapi cukup meyakinkan.
Melalui sahabatnya Abeng, aku bisa dapat nomor telp Ale. Aku menghubunginya. Mengejutkanku, ia mau bertemu. Tidak marah. Tidak menyinggung masa lalu. Ia hanya bertanya satu hal “Kamu yakin ?” Aku tidak menjawab. Karena aku sendiri tidak yakin.
Akhirnya aku dan pemegang saham lain bertemu di Hong Kong. Kota itu seperti selalu cepat, terang, tak peduli pada luka siapa pun. Ale datang tenang. Rambutnya sedikit pendek disbanding tahun 80an. Matanya tetap sama—tajam, tapi tidak menghakimi. Ia mendengar penjelasan para pemilik tambang dengan sabar. Ia bertanya sedikit, mencatat banyak. Aku tahu dari caranya bertanya, ia sudah melihat lubangnya.
“Ini bukan pembiayaan,” katanya akhirnya. “Ini penundaan kematian.”
Ruangan hening.
Namun mereka masih percaya pada nama, pada koneksi, pada kekuasaan lama. Mereka meminta skema utang konversi. USD 150 juta. Dengan janji akan membereskan semuanya. Ale tahu, uang itu bisa habis tanpa jejak. Tapi ia juga tahu, mereka belum siap jatuh. Ia setuju, dengan syarat waktu tiga bulan. Financial closing. Konfirmasi dana dari luar negeri valid. Pintu terbuka. Ale menunjuk kan kelas nya sebagai bisnis kelas dunia. Aku berdiri di sisinya. Untuk pertama kalinya, sungguh-sungguh berdiri. Dia tidak menolak. Menerima dengan tangan terbuka.
Selama tiga bulan itu, aku ikut rapat, ikut terbang, ikut duduk di ruang-ruang dingin yang penuh kalkulasi. Aku melihat bagaimana Ale bekerja keras, tidak teatrikal. Ia tidak menjual mimpi. Ia membangun struktur. Ia berbicara dengan bankir bukan sebagai peminta, tetapi sebagai penyusun risiko.
Namun waktu habis. Waktu tiga bulan habis. Ale minta di extend. Pemegang saham mayoritas menolak perpanjangan. Padahal Ale bersia bayar Penalti USD 1,5 juta untuk perpanjangan tiga bulan. Ditolak juga. Ale hanya diam. Dia kalah. Ale tidak tahu. Sebenarnya semua informasi yang kudapat dari selama disisi Ale mengalir ke pemegang saham lain. Dan mereka menggunakan consultant international untuk deal langsung dengan lender tanpa perlu lewat Ale.
Berkat sukses penggalangan dana itu, pemegang saham mayoritas yang sudah menduda melamarku jadi istri. Maka kekuasaan absolut dalam bisnis holding tambang ada ditanganku. Ale tahu. Aku tahu ia tahu. Ketika akhirnya kami bertemu lagi, ia berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri:
“Ada apa May? Mengapa kamu pergi dariku.” Kata Ale, tapi kali ini tidak dengan nada getir. Dia tersenyum, senyum penuh arti. “Dan kamu bantu mereka?” tanyanya.
Aku mengangguk.
“Kenapa?” katanya.
Aku menjawab tanpa berputar “Aku tidak melihat kamu sebagai sumber daya.”
Ia diam lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan kecewa, melainkan kelelahan.
“Jangan naif,” kataku, hampir membela diri. “Dunia ini tidak hidup dari niat baik. Apalagi hanya modal kenal doang. Kamu engga punya apa apa kecuali network. Dan network kamu hanya percaya kepada pemilik asset, bukan pemilik mimpi.”
Ia tidak membantah. Ia hanya menatapku, seolah mencoba memahami bagaimana seseorang bisa begitu jauh terseret dari dirinya sendiri. Kami berpisah tanpa pertengkaran. Tanpa drama. Seperti dua orang yang pernah berdiri di satu titik, lalu memilih jalan berbeda dan tidak pernah benar-benar kembali.
Aku pikir itu akhir.
Aku salah.
***
Tidak ada runtuh yang datang dengan bunyi keras. Yang ada hanyalah suara kecil yang mula-mula diabaikan. Seperti retak rambut di dinding tua. Tidak mencolok, tapi pelan-pelan menjalar. Pada awalnya, semua masih tampak berjalan. Surat-surat masih dikirim. Rapat masih digelar. Angka-angka masih ditata seolah hidup. Namun di baliknya, mesin sudah kehilangan tenaga. Kredit tidak lagi mengalir. Jadwal pembayaran mulai bergeser. Telepon yang dulu cepat dijawab kini berdering lebih lama. Aku tahu tanda-tanda itu. Terlalu tahu.
Tapi seperti banyak orang yang hidup dari ilusi kendali, aku memilih percaya bahwa semuanya bisa diatur. Bahwa satu pertemuan lagi, satu kesepakatan lagi, satu janji lagi akan cukup untuk menahan runtuhnya bangunan yang sejak awal berdiri di atas tanah rapuh.
Suamiku—lelaki yang dulu kupilih karena kekuasaan—mulai berubah. Ia lebih diam. Tatapannya sering kosong. Ia bicara tentang “jalan keluar” seperti orang menghafal doa, bukan sebagai rencana. Ia menyebut nama-nama besar, seolah nama masih punya daya magis.
Aku tahu ia takut. Utang konversi itu jatuh tempo seperti palu yang tidak bisa ditawar. Kreditur datang bukan dengan teriakan, melainkan dengan dokumen. Tidak ada makian. Tidak ada emosi. Hanya paragraf-paragraf dingin yang menyatakan kepemilikan berpindah tangan. Hari ketika semuanya resmi berpindah, hujan turun deras. Tidak dramatis. Tidak simbolik. Hanya hujan biasa, seperti hari lain di kota ini. Tapi bagiku, dunia terasa kosong.
Suamiku terkena stroke tak lama setelahnya. Tubuhnya lumpuh sebagian. Kata-katanya tak lagi utuh. Lelaki yang dulu bicara tentang ekspansi dan valuasi kini kesulitan mengucapkan namaku dengan jelas. Anak-anaknya—yang bukan darahku—menatapku seperti benda asing. Aku bukan lagi bagian dari rumah itu. Aku tahu kapan seseorang berhenti dibutuhkan. Nada suara berubah lebih cepat dari kata-kata.
Aku pergi tanpa pertengkaran. Tanpa drama. Satu koper. Beberapa pakaian. Beberapa buku. Dan satu kesadaran pahit, kekuasaan tidak pernah memberi rasa aman. Ia hanya menunda kehancuran.
Aku kembali menjadi seseorang yang harus menghitung hari. Dari tabunganku, aku berusaha bertahan. Tapi ongkos pergaulan sangat mahal. Aku masih berusaha bangkit dengan tetap menjaga hubunganku dengan elite kekuasaan. Akhirnya uang habis. Teman menghilang. Akupun sudan malu bertemu dengan network ku di ring kekuasaan. Mana ada pembicaraan tanpa uang. Dan aku sudah bagnkrut. Pintu tertutup sudah.
Aku bekerja sebagai pemandu wisata. Mengantar orang-orang lanjut usia melihat dunia yang ingin mereka ingat sebelum lupa. Aku tersenyum, menjelaskan sejarah kota dengan suara lembut, menjawab pertanyaan yang berulang, dan mendengar cerita hidup orang lain tanpa pernah benar-benar menceritakan hidupku sendiri.
Di sela perjalanan itu, aku sering berpikir tentang Ale. Aku bertanya-tanya, apakah ia pernah jatuh sedalam aku? Dan jika iya, bagaimana ia bisa berdiri lagi?
***
Tahun 2018.
Beijing. Hari itu dingin. Aku sedang mengantar rombongan lansia dari Asia Tenggara. Mereka ingin makan siang di Peninsula. Hotel itu megah, seperti museum kemewahan yang enggan mengakui usia. Aku berdiri agak jauh ketika melihat sosok yang kukenal.

Ale.
Ia duduk di sudut lounge, mengenakan jas. Rambutnya sedikit memutih. Posturnya tetap tegak. Di seberangnya duduk seorang perempuan, berpakaian rapi, berbicara pelan. Ia tidak terlihat seperti sekretaris. Lebih seperti rekan.
Aku ragu. Sangat ragu.
Namun entah dari mana keberanian itu muncul, aku melangkah mendekat.
“Koh… apa kabar?”
Ia menoleh. Matanya membesar sesaat, lalu tersenyum.
“Mey?”
Ia berdiri dan memelukku singkat, wajar, tanpa canggung. Tidak ada sisa dendam di geraknya. Tidak ada dingin.
“Kamu di sini?” tanyanya.
Aku mengangguk. “Kerja.” Seraya menyerahkan kartu namaku.
Ia tersenyum kecil. “Duduklah.” Dan ia melirik kepada wanita di depannya. Itu sebagai isyarat agar wanita itu pergi. Benarlah, wanita itu pergi seraya menunduk depan dia.
Kami duduk. Aku merasa seperti kembali ke masa lalu, namun dengan tubuh yang lebih letih dan rentan. Kami bicara hal-hal ringan. Tentang cuaca. Tentang kota. Tentang perjalanan. Sampai akhirnya aku tak tahan.
“Aku dengar… kreditur Swiss itu milik koh Ale”
Ia menatapku lama. Bukan marah. Bukan terkejut. Seolah sudah menunggu pertanyaan itu.
“Aku tahu dari teman di Singapura,” lanjutku pelan. “Katanya… setelah itu Koh Ale jual tambang itu ke investor Tiongkok. Dua kali lipat harganya.”
Ia tidak menyangkal.
Aku tertawa kecil, getir. “Jadi waktu itu … aku hanya alat?”
Ia menarik napas panjang. Lama.
“Kamu pintar,” katanya pelan. “Dan cantik. Tapi kamu punya satu kelemahan.”
Aku menegang.
“Kamu terlalu ingin menang cepat.”
Aku hendak membela diri, tapi ia mengangkat tangan.
“Kamu pikir aku mendapatkan akses financial resource itu semudah datang ke rapat. Kamu pikir aku percaya saja atas ketulusan kamu ada disisiku dalam proses pengagalangan dana tambang itu. Kamu pikir aku sudah lupa siapa kamu? Tidak Mey..”
Ia menatapku, bukan menghakimi, hanya menjelaskan.
“Aku menunggu bertahun-tahun. Aku kalah berkali-kali. Aku belajar membaca orang. Dan ketika aku bergerak, aku bergerak diam-diam.”
Aku menunduk.
“Kamu memanfaatkan aku,” kataku.
Ia menggeleng pelan. “Aku memanfaatkan situasi. Memanfaatkan ambisi kamu. “ Katanya. “ Ambisi bukan dosa. Tapi ambisi tanpa kesabaran dan moral membuat orang mudah dipakai. Kamu memilih berdiri di sisi yang salah. “
Aku tak bisa membantah. Hanya bisa berkata dalam lirih” Ale, aku tidak punya suami. Tidak punya anak. “ Airmataku jatuh begitu saja. “ Kalau aku pernah tidur dengan banyak pria itu bukan cinta. Tetapi dengan kamu itu kali pertama dalam hidupku sebagai perempuan dewasa. Dan saat darah keluar dari selaput daraku, aku merasa sempurna sebagai wanita. Karena aku melakukannya untuk alasan cinta. ” Kataku.
Aku menangis. Ale hanya diam.
” Dalam hidup aku banyak membuat kesalahan, namun satu satunya keputusan yang benar, itu saat aku makukannya dengan pria yang tepat. Pria yang aku cintai seutuhnya. “ Lanjutku dengan airmata. Ale tetap tenang mendengar.
“ Kamu tidak pernah menggodaku, apalagi mengatakan cinta.” Kataku. Ale memberi tissue untuk menyeka airmataku. “ Tapi kamu selalu memaklumiku. “ Kataku menyeka airmata.
Aku tatap Ale. “ Hanya karena keegoanku yang muak dengan jalan hidupmu yang lambat dan terlalu berhitung namun naif, membuat aku menjauh darimu. “ Kataku tersendat. “ Tapi cintaku tulus. “ Kataku menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku.
Ale hanya diam.
” Maaf, aku katakan ini bukan bermaksud untuk dikasihani. Tetapi diusia menua ini. Aku tidak ingin mati dengan mata melotot. Seidaknya aku harus jujur dihadapan pria yang kucintai. Cinta pertamaku.” Lanjutku dengan sisa keberanianku dan kini akulah yang naif dihadapan pria yang bertahun tahun aku khianati dan rendahkan.
“Jaga dirimu baik-baik, Mey,” katanya. “Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri.”
Lalu ia pergi. Tanpa salam dan pelukan.
***
Setelah pertemuan di Beijing itu, aku sering memikirkannya. Bukan karena cinta lama, bukan pula karena penyesalan yang ingin ditebus. Lebih karena satu pertanyaan yang terus berputar. Bagaimana seseorang bisa tetap utuh setelah begitu sering dikhianati?
Aku menyadari sesuatu yang dulu luput dariku. Ale tidak pernah berusaha menjadi pemenang. Ia hanya berusaha tidak kehilangan dirinya sendiri. Dalam dunia yang menjadikan kemenangan sebagai ukuran tunggal martabat manusia, sikap semacam itu dianggap aneh—bahkan bodoh. Tetapi justru di sanalah kekuatannya bersembunyi.
Aku mengingat kembali peristiwa-peristiwa lama, kini dengan mata yang berbeda. Ia tidak marah ketika dicurangi. Ia tidak berteriak ketika dilangkahi. Ia tidak membalas ketika dikhianati. Dulu aku mengira itu kelemahan. Kini aku paham, itu disiplin batin. Ale tahu bahwa amarah memberi kepuasan cepat tapi menghabiskan arah. Ia tahu bahwa balas dendam sering kali hanya memperpanjang rantai kekalahan. Ia memilih jalan yang lebih sunyi, menunda reaksi, menyimpan tenaga, dan membiarkan waktu bekerja. Ia tidak menantang dunia. Ia mempelajarinya.
Ia tidak membalas orang-orang yang menjatuhkannya. Ia membiarkan mereka menampakkan diri sendiri. Dalam dunia bisnis, reputasi tidak runtuh karena satu kesalahan, melainkan karena pola. Dan Ale sabar menunggu pola itu selesai menulis dirinya sendiri. Aku baru mengerti satu hal penting. Orang seperti Ale tidak mengalah—mereka menunda kemenangan.
Aku juga baru sadar bahwa selama ini aku hidup dalam ilusi kecepatan. Aku percaya bahwa hidup harus segera berhasil, harus segera naik, harus segera diakui. Aku percaya bahwa nilai seseorang ditentukan oleh seberapa cepat ia sampai. Maka aku memilih jalan pintas. Aku memilih kekuasaan. Aku memilih orang-orang yang tampak menang.
Namun waktu adalah hakim yang tidak bisa disuap. Satu per satu orang-orang yang dulu tampak tak tergoyahkan runtuh oleh keangkuhannya sendiri. Yang bertahan bukan mereka yang paling keras, melainkan mereka yang paling sabar membaca arah angin. Bukan mereka yang paling cepat menancapkan bendera, melainkan yang tahu kapan harus menunggu badai reda. Ale termasuk yang terakhir.
Ia tidak mengumpulkan kekayaan dengan teriakan. Ia membangun struktur, pelan-pelan, lintas negeri, lintas rezim. Ia tidak bergantung pada satu pintu. Ia membuat banyak pintu kecil, yang tidak terlihat megah, tapi selalu bisa dibuka. Ia tidak mencari pengakuan. Itu sebabnya ia jarang diserang. Ia tidak tampil sebagai pemenang, maka tidak ada yang merasa perlu menjatuhkannya.
Aku, sebaliknya, pernah terlalu ingin terlihat berhasil. Dan dunia memberi pelajaran dengan caranya sendiri. Kini, ketika aku mengingat masa lalu, yang tersisa bukan lagi penyesalan, melainkan pemahaman. Bahwa hidup tidak selalu memberi hadiah pada yang paling cerdas, paling cantik, atau paling berani. Kadang ia memberi ruang pada mereka yang sanggup menahan diri. Ale mengajarkanku itu—tanpa pernah bermaksud mengajar.
Ale tidak pernah menuntut pengakuan. Tidak pernah mengungkit luka. Bahkan tidak pernah mengklaim kebenaran. Ia hanya berjalan sesuai keyakinannya sendiri, meski jalan itu sepi. Dan mungkin, justru karena itulah ia tidak hancur walau berkali kali dia jatuh. Ya dia bangkrut secara bisnis tapi secara spiritual dia tidak pernah bangkrut.
Kini aku mengerti. Ada orang yang tampak kalah sepanjang hidupnya, tetapi sesungguhnya sedang menyelamatkan jiwanya dari rusak. Ada pula yang tampak menang, namun perlahan kehilangan dirinya sendiri. Jika kelak ada yang bertanya siapa Ale bagiku, aku akan menjawab pelan. “ Ia adalah orang yang mengajarkanku bahwa kemenangan sejati bukan soal siapa yang lebih cepat sampai, melainkan siapa yang tetap manusia ketika sampai.
Dan mungkin, dalam dunia yang bising oleh ambisi dan angka, orang seperti Ale memang tidak pernah dimaksudkan untuk bersinar terang. Ia hanya dimaksudkan untuk tetap menyala—diam-diam—agar dunia yang terlalu keras ini masih punya cahaya yang tidak membakar.
Sebulan setelah pertemuan di Beijing. Ada pria datang ke tempat kos-ku. Namanya Awi. Dia membelikan aku apartement di pinggir kota dan tabungan untuk masa tuaku. Ale tidak marah dan tidak dendam. Itulah Ale ku…

Tinggalkan komentar