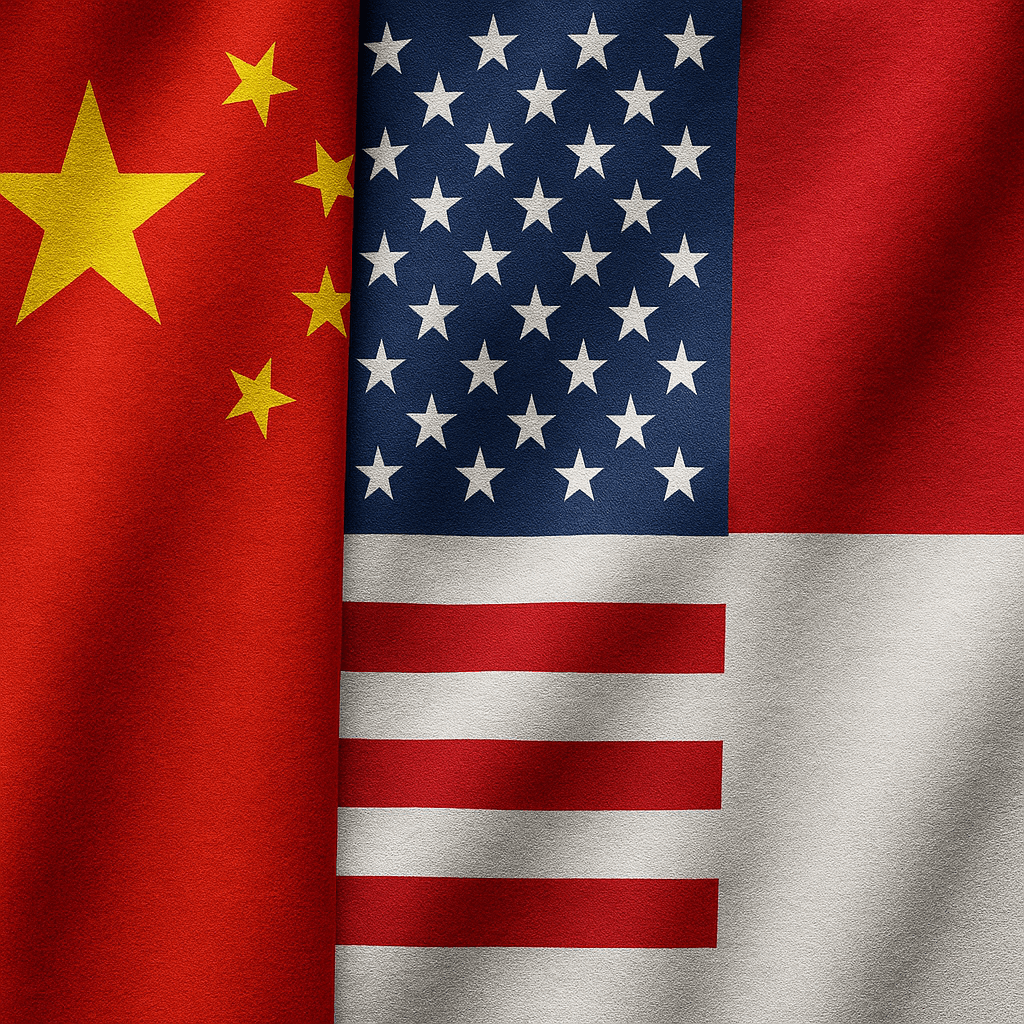
Kantor Abeng di kawasan Cideng bukan kantor biasa. Dari luar terlihat sederhana. Hanya bangunan dua lantai berwarna abu kusam. Tapi begitu saya masuk, bau khas kayu tua dan arsip kertas menyambut saya. Dinding penuh rak berisi dokumen, foto-foto lama yang menceritakan empat dekade perjalanan bisnis nya. Dia mentor saya. Usianya 10 tahun lebih tua dari saya. Namun tubuh tetap tegap.
Walau dia tidak lagi mengelola langsung bisnisnya namun tiap pagi dia sudah di kantor. Menurut saya Abeng beruntung. Walau punya anak perempuan semata wayang, namun mantu nya hebat. Hebat dalam bisnis dan hebat juga dalam karakter. Sejak 10 tahun lalu semua bisnisnya dikelola oleh mantunya. Malah semakin berkembang. Sehingga dia bisa pensiun dengan Bahagia.
Abeng menanti saya di depan lobi kantornya. “ Herman udah ada datang duluan. Yang lain belum datang. Jadi kita bisa ngobrol dulu. “ Katanya menepuk bahu saya. Kami memang rencana mau main ke sauna bareng bareng.
Ale ” katanya sambil duduk, “China itu lagi nggak happy sama kita.”
Herman tersenyum pelan. “Saya juga sudah dengar desas-desusnya. “ katanya. Abeng menghela napas panjang. “Ini bukan desas-desus, Man. Ini real. Banyak orang belum sadar, tapi arah kapal Indonesia itu sudah bergeser.” Kata Abeng.
“ Tapi saya mau tahu versi kamu, Ale.. Kan kamu punya network bisnis di Cina.” Sambung abeng
Saya tidak langsung menjawab. Saya biarkan dia melanjutkan, karena biasanya yang keluar setelah kalimat itu adalah sesuatu yang penting. “Dulu, zaman Jokowi, kita hidup dari nikel dan BRI. Sekarang? Lihat Danantara.” Abeng menatap saya tajam. “Modelnya bukan model Beijing. Itu model Wall Street, model London, model Eropa.”
Saya mengangguk. “Leverage aset BUMN ke pasar keuangan global… itu memang gaya Barat. Tapi kita pernah coba, kan? INA era Jokowi.”
Dia tertawa pendek. “Iya. Dan akhirnya dibonsai sendiri.”
“Karena apa ? tanya Herman.
“Karena memperkuat INA berarti membuka pintu ke arsitektur finansial Barat. Jokowi tidak mau menghadapi konsekuensi geopolitik itu, ya tidak mau dicurigai Beijing.”
Saya mengangguk. “Prabowo berbeda. Danantara adalah deklarasi arah. Dan Beijing tahu itu.”
“Nah,” kata Abeng sambil mencondongkan tubuh. “Buat Beijing, itu tanda Indonesia mulai mengarahkan kapal geostrategisnya ke AS–Eropa.”
Saya diam, memutar gelas kopi saya perlahan.
“Smelter-smelter mereka sudah mulai slow down,” Kata Herman. “Ada yang cut kapasitas, ada yang stop. BYD pun nunda ekspansi. Permintaan batu bara dari China turun. Itu semua bukan kebetulan.”Lanjut Herman.
“Respons geopolitik,” kata saya.
“Exactly.” Abeng mengetuk meja pelan. “China membaca sinyal. Mereka lihat Danantara gandeng Ford, Toyota, dorong bioetanol, bukan EV. Itu pukulan psikologis buat mereka. Karena itu sama dengan bilang, ‘Kami ikut arsitektur energi Barat.’”
Saya tersenyum kecil. “Dan antara Jepang, Korea, Taiwan itu semua satelit industri Amerika.”
“Betul,” jawab Abeng. “Danantara basically sedang bilang ke dunia, kita bukan lagi pemain BRI, kita mau main di pasar global yang dikontrol AS–Eropa.”
Saya menarik napas. “Lalu Australia. Itu juga bagian dari puzzle?”
Abeng tertawa pendek. “Ale, kamu pikir China nggak lihat? Prabowo merapat ke Australia, negara yang paling dekat dengan Washington setelah Jepang. Australia punya critical minerals, punya posisi strategis dalam pembangunan industri Barat. Dan Cina tahu, kalau Indonesia gandeng Australia, itu bukan sekadar diplomasi. Itu pindah haluan.”
Saya melihat lampu-lampu kota mulai menyala di luar jendela. Jakarta sore hari selalu menciptakan nostalgia yang aneh, seakan waktu berjalan lebih lambat.
Abeng diam sejenak.
“Dan satu lagi, Ale… keliatannya Beijing sakit hati dengan narasi politik dalam negeri kita.” Kata Abeng kemudian.
“Sakit hati?” saya mengulang.
Herman mencondongkan tubuh.
“Di Jakarta, mulai ramai politisi dan pejabat yang seolah-olah menyalahkan China atas kerugian kereta cepat. Yang dibilang, bunga pinjaman China tinggi, struktur pembiayaan bikin APBN berat, Beijing memaksakan skema’.”
Saya tersenyum tipis. “Padahal yang negosiasi kan kita sendiri.”
Abeng mengangguk keras. “Itu dia. Beijing merasa mereka disalahkan untuk keputusan yang sebenarnya disetujui pemerintah kita sendiri. ”
“Dan itu membuat mereka…?” tanya saya.
“Tidak happy. Sangat tidak happy. Akibatnya kemungkinan restrukturisasi hutang kereta Cepat engga mudah deh.” Kata Herman. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. “China melihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang menyiapkan narasi publik untuk menjauh dari mereka. Karena kalau sebuah negara mau pindah blok, biasanya mereka mulai mengubah opini publik dulu.”
Saya menarik napas. “Dan China membacanya.”
“Dengan sangat jelas.” Jawab Abeng.
“Jadi,” kata saya perlahan, “China merasa Indonesia menjauh?”
“Bukan menjauh,” koreksi Abeng. “China merasa Indonesia berpindah orbit. Dan itu yang bikin mereka nggak happy. Termasuk narasi politik dalam negeri yang nyerempet-nyerempet proyek kereta cepat sebagai beban APBN, itu makin mengklarifikasi sinyal bahwa kita ingin lepas.”
Saya mengangguk. “Sinyal dalam geopolitik kadang lebih penting daripada kebijakan.”
“Exactly.” Abeng mengangkat tangan, memberi tanda pada OB untuk tambah minum. “China itu baca sinyal halus. Dan sekarang sinyalnya keras: Indonesia lagi gandeng AS lewat pasar finansial, gandeng Jepang–Korea lewat teknologi, dan gandeng Australia lewat Kerjasama militer.”
Saya terdiam sejenak, menatap cairan hitam dalam gelas. “Arah kapal sudah berubah,” saya akhirnya berkata.
Abeng tersenyum. “Iya, Ale. Dan Beijing sudah melihat perubahan arah kemudi itu. Kita pura pura bego aja”
“ Nah apa jadinya kalau AS tidak menepati janjinya dan menunda menunda dukungan leverage untuk pendanaan Danantara ? Tanya saya
Abeng lalu berkata dengan suara berat. “ Ale, kalau Danantara tidak dapat dukungan leverage dari grup AS… itu bisa jadi bencana strategis.”
“Bagaimana?” tanya Herman. Saya senyum aja.
“Indonesia sudah memberi sinyal menjauh dari China. Tapi jika Washington tidak membuka akses pasar, tidak mendukung issuance, tidak mengalirkan institutional fund, atau tidak mau menyentuh aset BUMN…”
Ia menatap saya lama.
“…Indonesia akan terjebak di tengah laut. Tidak lagi dekat Beijing, tapi tidak diterima Washington.”
Saya terdiam.
“Smelter China mundur. Investasi mereka pending. Tapi AS tidak masuk. Itu kondisi paling buruk, strategic orphan.” Kata Abeng.
“ ya benar Beng. “ kata Herman. “ Tanpa support Amerika, Danantara tidak bisa revaluasi aset dalam skala besar, tidak bisa masuk ke pasar green bond Eropa, tidak bisa masuk ke pipeline London–New York, tidak bisa scaling sovereign leverage. Kita kehilangan dua hal sekaligus. modal China dan infrastruktur finansial Barat. Sikua capang sikua capeh. Yang satu terbang yang lain lepas. “
Saya menyandarkan tubuh. “Jadi taruhannya masa depan 20 tahun Indonesia.”
“Exactly.”
Di luar jendela, langit Jakarta memerah keemasan.Abeng memandang ke luar. Saya berkata pelan “Beijing tidak marah karena kita bekerja sama dengan AS. Mereka menghormati pilihan kita. Mereka marah karena kita menyalahkan mereka di depan rakyat sendiri. Itu bagi China adalah tanda perpisahan.”
Abeng hanya diam. Kami sama-sama terdiam. Di luar, lampu-lampu gedung memantul di kaca, seperti bintang buatan manusia. Di saat-saat seperti itu, saya sadar bahwa negara pun sama seperti kapal besar. Perlu waktu panjang untuk berbelok, tapi sekali kemudi diputar, seluruh arah perjalanan akan berubah untuk bertahun-tahun ke depan. Di dunia geopolitik, tidak ada yang lebih berbahaya daripada negara yang sudah berbelok, tapi belum diterima di pelabuhan barunya.
AS Vs China.
Pendahuluan.
Rivalitas AS–China di Indo-Pasifik hari ini bukan sekadar soal siapa lebih berpengaruh, tetapi soal siapa yang berhak mendesain “aturan main”, baik di laut, di pasar keuangan, maupun di jalur logistik dan teknologi. Di titik ini, Indonesia adalah “critical node”, bukan sekadar “negara berkembang yang kebetulan besar”.
Letak Indonesia di Selat Malaka menjadikannya gatekeeper salah satu choke point tersibuk di dunia. Jalur vital untuk perdagangan China, Jepang, Korea, dan bahkan Eropa. ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) menghubungkan Samudra Hindia–Pasifik, menjadikan Indonesia elemen kunci dalam desain maritime domain awareness dan strategi sea lines of communication (SLOCs). Di sisi energi, jalur tanker minyak dan LNG yang melintasi perairan Indonesia berhubungan langsung dengan keamanan energi China dan Asia Timur, namun stabilitasnya tetap sangat dipengaruhi oleh arsitektur keamanan yang dipayungi AS.
Dalam realitas ini, Indonesia berada dalam dilema structural. Butuh AS untuk stabilitas finansial. Butuh China untuk industrialisasi. Namun tidak bisa keduanya. Harus memilih salah satu. Karena keduanya saling jelous. Akibatnya, doktrin “bebas dan aktif” Indonesia secara formal tetap dipertahankan, tetapi “Bebas” menjadi semakin relative. Karena ruang manuver dibatasi oleh ketergantungan finansial pada sistem dolar dan ketergantungan industrial pada ekosistem China. “Aktif” juga berubah makna, bukan sekadar aktif di forum multilateral, tetapi harus aktif mengelola risiko terseret terlalu jauh ke salah satu blok.
Dengan kata lain, Indonesia tidak lagi hanya memainkan politik luar negeri; Indonesia sedang bermain di persimpangan strategi kekuasaan global, di mana setiap langkah akan dibaca sebagai sinyal ke Washington dan Beijing sekaligus.
Benturan kepentingan.
Agar analisis saya tidak berhenti di level opini, saya akan membahas nya melalui pendekatan : Great-Power Competition, Geoeconomics, dan Neo-Classical Realism. Ini jmemberi lensa yang lebih teknis untuk membaca posisi Indonesia.
Great-Power Competition (GPC)
Great-Power Competition (GPC) adalah cara melihat hubungan AS–China bukan sebagai konflik biasa, tetapi sebagai kompetisi antar “kekuatan besar” untuk membentuk struktur tatanan regional dan global.
Dalam kerangka GPC, AS melihat dirinya sebagai penjaga status quo. Menjaga kebebasan navigasi di Indo-Pasifik. Menjaga aliansi (Jepang, Korea Selatan, Australia, Filipina).Menjaga agar tidak muncul “kekuatan dominan baru” yang bisa mengusik hegemoninya.
China bertindak sebagai revisionist power yang ingin mengubah keseimbangan. Menggeser pusat gravitasi ekonomi ke Asia. Mendorong BRI, AIIB, RCEP sebagai alternatif/komplemen lembaga Barat. Memperluas posisi militer & maritim-nya di Laut China Selatan dan sekitarnya.
Bagi Indonesia, GPC berarti, setiap keputusan mengenai pelabuhan strategis, pangkalan militer, akses ALKI, proyek infrastruktur pelabuhan/railway/logistics akan selalu dibaca sebagai mendekat ke AS, atau ke China, atau mencoba membuat bentuk “keseimbangan di tengah”, yang tidak selalu mudah secara praktis. Dengan konsep GPC, Indonesia bukan hanya “negara yang ingin aman dan makmur”, tetapi arena kompetisi desain tatanan baru Indo-Pasifik.
Geoeconomics
Geoeconomics melihat bahwa kekuatan negara tidak lagi (atau tidak hanya) ditunjukkan lewat tank dan rudal, tetapi lewat, trade policy,investasi,sanksi,kontrol teknologi, dan penguasaan supply chain. AS dan China sama-sama memainkan geoeconomics
AS menggunakan Export control teknologi (semikonduktor, AI, high-end manufacturing). Rejim sanksi keuangan dan pembatasan akses dolar. Aturan compliance (FATF, AML, KYC, CAATSA) sebagai alat tekan. China menggunakan Kredit BRI, Investasi infrastruktur dan pabrik. Ketergantungan pada bahan baku/komponen/market China. Kemampuan mobilisasi BUMN dan bank policy-driven.
Dalam konteks Indonesia, Negosiasi pelabuhan, kawasan industri, dan tambang bukan lagi sekadar proyek bisnis, tetapi instrumen geoeconomic alignment. Apakah Indonesia lebih terikat pada platform finansial Barat atau ekosistem industrial China. Kebijakan hilirisasi mineral, pembatasan ekspor bahan mentah, dan pemilihan investor smelter/pabrik akan selalu berimbas ke respon WTO, tekanan mitra dagang, dan sensitivitas AS–China.
Jadi, geoeconomics menjelaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi Indonesia—apalagi terkait energi, mineral, dan logistik—punya dimensi kekuasaan internasional.
Neo-Classical Realism
Neo-Classical Realism mencoba menjembatani dua level. Pertama. Tekanan struktural eksternal (misalnya rivalitas AS–China, struktur sistem internasional). Kedua. Kalkulasi elite domestik (prioritas politik, kepentingan kelompok, kapasitas institusi negara). Secara sederhana. Dunia luar menekan, tapi bagaimana negara merespons sangat ditentukan oleh siapa yang memegang kendali kebijakan di dalam negeri dan bagaimana mereka membaca tekanan itu.
Dalam konteks Indonesia. Di level eksternal, Indonesia melihat kebutuhan jangka panjang akan industrialisasi (yang membuka ruang masuknya China), kebutuhan stabilitas keuangan (yang tetap membuat Indonesia bergantung pada sistem dolar dan kepercayaan pasar Barat), risiko terseret konflik di Laut China Selatan dan blok Indo-Pasifik. Di level domestik, respons Indonesia dipengaruhi oleh koalisi politik penguasa, jaringan oligarki bisnis (yang terhubung ke proyek China, konsesi tambang, energi), technocrats (BI, Kemenkeu, Bappenas, Kemenlu) yang cenderung lebih berhati-hati terhadap risiko finansial global, dan persepsi publik (nasionalisme, isu kedaulatan, sentimen anti-asing).
Neo-Classical Realism membantu kita memahami bahwa kebijakan “bebas aktif” bukan hanya prinsip idealis; ia adalah hasil kompromi antara tekanan eksternal dan kalkulasi internal. Misalnya, Indonesia bisa menerima investasi China untuk smelter dan infrastruktur, tapi tetap mempertahankan komunikasi baik dengan AS, IMF, Bank Dunia, Jepang, dan Eropa untuk menjaga kredibilitas fiskal dan akses pembiayaan.
Dengan kacamata ini, Indonesia bukan sekadar “korban tarikan dua kekuatan”, tetapi aktor yang terus-menerus bernegosiasi di luar negeri dan di dalam negeri sekaligus. Itu bukan hanya sekarang, tetapi dari dulu begitu. Makanya sulit bagi Indonesia menggunakan kartu geopolitiknya untuk kepentingan nasional.
Structural Entrapment.
Posisi Indonesia dalam rivalitas AS–China bukan sekadar “serba salah”, tetapi sudah masuk kategori structural entrapment. Terjebak dalam struktur ketergantungan yang membuat opsi “netral total” praktis mustahil. Di makan roti, bapak mati. Engga dimakan, ibu mati.
Indonesia bukan hanya berhubungan dengan dua negara besar, tetapi menggantungkan dua pilar utama pembangunan pada dua kekuatan yang sedang berkonflik. Pilar industrialisasi, sangat terkait dengan China dan Pilar stabilitas moneter & keuangan, sangat terkait dengan AS dan sistem dolar. Akibatnya, setiap langkah Indonesia selalu memiliki biaya geopolitik.
Memunggungi China ?
Dalam dua dekade terakhir, China telah menjadi mesin utama industrialisasi Indonesia, terutama melalui pembangunan smelter dan fasilitas hilirisasi mineral, investasi di kawasan industri (nikel, stainless steel, baterai EV), pasokan mesin, komponen, dan intermediate goods, integrasi dalam rantai pasok EV dan baterai global.
Jika Indonesia mengambil sikap konfrontatif secara frontal terhadap China, implikasi sangat structural. Hilirisasi berhenti atau melambat drastic. Banyak proyek hilirisasi—nikel, bauksit, tembaga, baterai bertumpu pada modal & teknologi dari entitas terkait China. Tanpa mereka, kapasitas hilirisasi akan turun atau tertunda dalam jangka panjang karena tidak ada investor alternatif yang siap masuk dengan skala dan kecepatan serupa. Smelter tutup atau under-utilized. Smelter yang sudah berdiri capital intensive.
Jika akses modal kerja, teknologi, atau pasokan komponen terganggu, smelter bisa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan berhenti. Efek turunan adalah PHK, tekanan sosial di daerah tambang, dan kegagalan narasi hilirisasi. Runtuhnya supply chain EV dan bater Ambisi Indonesia menjadi hub rantai pasok baterai dan EV global sangat bergantung pada investor Asia Timur, terutama China & Korea, integrasi bahan baku, katoda/anoda, baterai, EV. Jika jalur ke China terganggu, daya saing biaya dan kelengkapan ekosistem akan jatuh.
China adalah salah satu pasar terbesar bagi produk tambang olahan, CPO & turunannya, produk manufaktur tertentu. Gangguan hubungan akan menekan ekspor, memperburuk neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Ringkasnya, memusuhi China sama dengan memukul kaki sendiri di sisi industrialisasi. Indonesia dapat bertahan, tetapi dengan biaya pertumbuhan lebih lambat, hilirisasi tersendat, dan kehilangan momentum transformasi ekonomi.
Memunggungi AS ?
Di sisi lain, sistem keuangan Indonesia tertambat kuat pada orbit dolar AS dan jaringan lembaga keuangan Barat. Konfrontasi dengan AS (baik langsung maupun lewat pelanggaran sanksi berat) membuka pintu krisis moneter yang sangat nyata. Konsekuensi teknisnya ? Cadangan devisa jatuh. Cadangan devisa Indonesia disimpan dalam bentuk aset reserve (banyak dalam USD atau surat berharga terkait).
Jika ada sanksi, tekanan pasar, atau capital outflow masif, BI akan dipaksa menguras cadangan untuk menstabilkan rupiah.Rupiah ambruk. Investor global, terutama yang memegang SBN dan surat utang korporasi, dapat keluar secara agresif jika persepsi risiko Indonesia naik, akses ke sistem dolar terganggu. Mengapa? Dana portofolio asing cenderung keluar dari pasar negara berkembang ketika muncul ketegangan dengan AS. Biaya pinjaman naik, spread obligasi melebar, refinancing utang menjadi lebih sulit. Lembaga rating (S&P, Moody’s, Fitch) sangat sensitif terhadap stabilitas politik, risiko eksternal, hubungan dengan lembaga keuangan global. Penurunan rating. Niaya utang naik membuat beban APBN makin berat.
Potensi pengulangan pola krisis 1997–1998. Polanya sama, tekanan eksternal, pelemahan kurs, pemburukan neraca korporasi dan perbankan, krisis kepercayaan. Bedanya, sekarang lebih kompleks karena utang swasta global lebih besar, integrasi pasar keuangan lebih dalam. Dengan kata lain, memusuhi AS sama dengan membuka peluang krisis moneter dan keuangan yang bisa menyeret Indonesia ke dalam spiral yang nyaris sama dengan 1997, bahkan mungkin lebih rumit.
Menghindari Keduanya? Mustahil Secara Struktural
Secara teori, mungkin muncul argument. “Kalau begitu, Indonesia sebaiknya menjauh saja dari kedua-duanya.” Namun secara struktural, itu mustahil dalam jangka pendek–menengah. Karena tidak ada substitusi untuk USD sebagai mata uang global. Perdagangan internasional, pembayaran impor, utang luar negeri, dan cadangan devisa masih sangat bergantung pada dolar. Alternatif seperti yuan, euro, atau local currency settlement masih berskala terbatas. Mencoba melompat keluar dari sistem USD tanpa jaring pengaman → risiko eksperimental yang terlalu besar.
Tidak ada substitusi realistis untuk China sebagai pemasok manufaktur murah dan mitra industrialisasi. China memiliki kombinasi unik yaitu skala industri raksasa, biaya yang relatif kompetitif, jaringan pasok yang sangat dalam (dari bahan mentah hingga barang jadi). Memindahkan seluruh basis supply chain ke negara lain butuh waktu lama, biaya besar, dan belum tentu ada negara yang siap.
Struktur ekonomi Indonesia sudah terlanjur “dipetakan” ke dua orbit ini. Ekspor–impor, aliran modal, struktur industri, utang luar negeri, dan kontrak jangka panjang sudah terikat pada sistem dolar (AS dan Barat), dan ekosistem manufaktur-investasi (China & Asia Timur).
Inilah yang disebut sebagai dual dependency trap. Indonesia tergantung ganda ke China untuk growth & industrialization, ke AS/sistem Barat untuk stability & finance. Karena itulah kita dapat menyebut situasi ini sebagai Geopolitical No-Exit Condition, kondisi di mana Indonesia tidak punya pintu keluar yang murah atau aman dari rivalitas AS–China, hanya bisa mengelola posisi dan risiko, bukan melompat keluar dari sistem. Memang masa depan yang suram.
Referensi.
Allison, Graham. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? Houghton Mifflin Harcourt, 2017.Friedberg, Aaron L. A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia. W.W. Norton, 2012. Ikenberry, G. John. Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order. Princeton University Press, 2011. Kaplan, Robert D. The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate. Random House, 2012. Nye, Joseph. The Future of Power. PublicAffairs, 2011. Mahbubani, Kishore. Has China Won? PublicAffairs, 2020. Schweller, Randall. Maxwell’s Ghost: International Relations in a Post-Leviathan World. Columbia University Press, 2021. Acharya, Amitav. “The Emerging Regional Architecture of World Politics.” World Politics, vol. 59, no. 4 (2007): 629–652. Mastanduno, Michael. “Economic Statecraft, Interdependence, and National Security.” International Organization, vol. 54, no. 2 (2000): 207–234. Buzan, Barry. “The Logic and Contradictions of ‘Peaceful Rise/Development’ as China’s Grand Strategy.” The Chinese Journal of International Politics, vol. 7, no. 4 (2014): 381–420. Goh, Evelyn. “The Modes of Asian Order: Power, Governance, and the United States–China Relationship.” International Security, vol. 38, no. 3 (2014): 65–99. Kai He. “China’s Crisis Behavior: Political Survival and Foreign Policy After the Cold War.” Journal of Contemporary China, 2016. Ross, Robert S. “The Problem with the Pivot: Obama’s New Asia Policy Is Unnecessary and Counterproductive.” Foreign Affairs, vol. 91, no. 6 (2012): 70–82.
RAND Corporation. US–China Competition and Implications for Southeast Asia, 2022. CSIS (Center for Strategic and International Studies). The Future of the Indo-Pacific Strategy, 2021. ISEAS–Yusof Ishak Institute. State of Southeast Asia Survey, annual editions (2019–2025).Lowy Institute. Asia Power Index, annual reports. IMF. International Financial Stability Report, various years. World Bank. Global Value Chain Development Report, 2019 & 2021. UNCTAD. World Investment Report, annual editions. Laksmana, Evan A. “Reshaping Indonesia’s Foreign Policy in the Indo-Pacific.” Survival (IISS), vol. 61, no. 1 (2019): 159–160. Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Perdagangan Indonesia. Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia,. Kemenperin. Analisis Industri Hilir Mineral, 2020–2024.LPEM UI. Policy Papers on Indonesia’s Industrialization and Dependency on China, 2020–2023. ASEAN Secretariat. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 2019. WTO. Trade Policy Review: Indonesia, 2020. OECD. Economic Outlook for Southeast Asia, 2022–2025.

Tinggalkan komentar