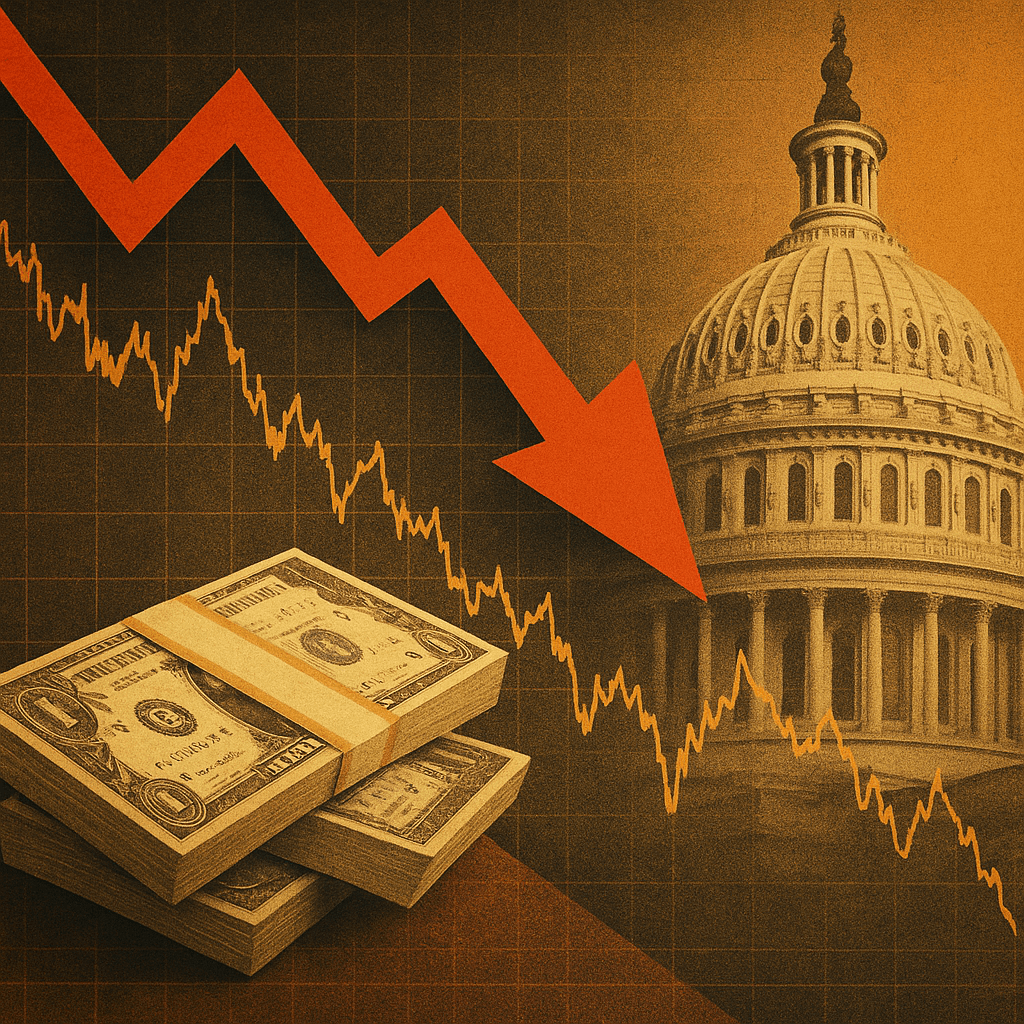
Aku dapat kabar Ira sakit. “ Dia tinggal sendirian di Rumah nya. Hanya di temanin pembantu saja “ Kata Edi. Ira sahabatku. Aku kali pertama mengenalnya di acara bedah buku tahun 1983 “ Bumi manusia “ karya Pramoedya Ananta Toer. Saat itu memang buku itu dilarang oleh rezim Soeharto. Usiaku 20 tahun. Masih sangat muda untuk tahu politik. Usianya lebih tua 3 tahun dariku. Aku terpesona dengan narasi Ira dalam memahami makna kebudayaan dan feodalisme. Mungkin karena dia mahasiswi. Dan aku orang kampung yang hanya tamatan SMA, berusaha menjadi bagian dari budaya metropolitan.
Setamat kuliah, Ira kerja di kantor konsultan dan juga aktifis ormas yang berafiliasi ke partai penguasa. Aku teman curhatnya dalam segala hal. Ira memang tidak berjarak denganku. Makanya aku bingung. Mengapa dia berubah. Setidaknya mengapa kata kata tidak sesuai dengan sikapnya. Beberapa tahun kemudian dia mencalonkan diri jadi anggota legislative dari partai penguasa.
“ Ini politik Ale, kadang harus merangkak di bawah rumah demi dapatkan telur. Tan Malaka bergabung dengan Partai Komunis bukan karena dia komunis tetapi itulah cara dia melawan imperialis. Karena saat itu hanya partai komunis yang punya cantolan kuat secara internasional. “ katanya berusaha meyakinkanku atas pilihannya masuk ke partai penguasa dan akhirnya jadi anggota dewan. Aku berusaha maklum walau aku tidak pernah bisa memahami. Bagaimana orang yang tadinya sangat membenci rezim akhirnya jadi penghuni cangkang rezim.
Setelah Ira jadi anggota dewan, kami sudah jarang bertemu. Akupun sibuk dengan bisnis. Kalaupun kami bertemu, itu karena permintaan dia. Aku tidak bisa menolak. “ Aku bisa gunakan akses politik untuk kemudahan kamu berbisnis. Mengapa kamu tidak manfaatkan itu “ katanya satu waktu. Aku diam saja. Usia emasku, bukan mencari yang mudah. Aku memilih semak belukar, dan berusaha melewatinya. Walau terluka dan kadang terjatuh, itu mendewasakanku.
Belakangan aku tahu Ira sering ikut pertemuan secara gelap dengan kelompok prodem. Dia tidak pindah ke PDI, dan namun dia membantu prodem lewat lobinya dengan elite kekuasaan. Ikut arus dalam perubahan PDI yang diwarnai sengketa kepengurusan antara kubu Megawati dan Suryadi.
***
Awal 1997, Ira datang dengan wajah letih tapi tegas. “Bisa bantu teman-temanku memindahkan dana ke luar negeri?” katanya lirih. Aku menatapnya dalam. “Untuk apa?” tanyaku.
“Situasi politik makin tidak pasti,” jawabnya pendek.
Publik masih anggap semua baik baik saja. Namun bagi sebagian kecil yang paham ritme kekuasaan, udara politik mulai berbau logam, tanda badai yang mendekat. Bagiku sebagai pengusaha. Itu peluang.
Aku segera menghubungi banker di Singapura yang punya cabang di Indonesia. Dalam beberapa hari, jaringan itu terbentuk. Kami membuka rekening-rekening offshore untuk para pejabat dan pengusaha yang gelisah. Semua proses tampak sah: mengisi formulir, menandatangani aplikasi, dan dalam lima menit, uang bisa berpindah ke rekening dolar di luar negeri tanpa melewati batas negara. Secara teknis, itu disebut cross-settlement — transfer antar entitas bank yang punya cabang di Jakarta dan Singapura. Dulu hal ini memungkinkan. Bank asing boleh melalukan cross settlement. Legal. Cepat. Sunyi.
Kami menyebutnya “diversifikasi aset.” Tapi dalam bahasa makroekonomi, itulah bentuk awal dari capital flight. pelarian modal. Dan seperti itulah ekonomi bekerja di negeri ini. Dalam beberapa bulan, ratusan triliun rupiah berpindah ke luar negeri. Setiap pembukaan rekening memberikan fee 0,25%. Bagi kami, operator kecil, ini bisnis biasa. Bagi negara, ini kebocoran tak terlihat.
Uang terus mengalir keluar. Namun tak ada yang berani bicara. Karena di negeri ini, yang paling berbahaya bukan inflasi, tapi kebenaran. Pada awall awal 1997 Indonesia tampak tenang di permukaan. Rupiah kuat di kisaran Rp2.300 per dolar, investor tersenyum, dan media masih dikontrol ketat agar optimisme tetap mengudara. Namun di balik itu, perekonomian telah lama berdiri di atas fondasi rapuh: utang luar negeri, rente birokrasi, kolusi, korupsi, nepotisme melahirkan konglomerasi semu yang disusui oleh kredit negara.
“ Kemenangan partai kamu sebenarnya adalah kemenangan pro demokrasi.” Kataku usai pemilu 1997.
Ira terkejut.” Maksud kamu ?
“ Pemilu 1997 ini, Megawati berhasil menarik simpatik massa islam. Gus Dur mendukung dia. Pertarungan internal PDI dimanfaatkan Megawati untuk melambungkan namanya secara nasional. Kalau itu terjadi, ABRI akan melirik ke dia. “ Kataku.
“ Mengapa ?
“ ABRI itu doktrin ideologinya adalah rakyat. Kalau rezim tidak lagi didukung oleh NU, maka moncong bedil tidak lagi diarahkan ke rakyat tetapi ke istana. Tanpa dukungan militer, rezim pasti jatuh” Kataku. Ira tersenyum. Mungkin dia pura pura tidak tahu. Atau memang dia sekedar menguji pemahaman politik ku.
Kemudian benarlah, Ira cerita panjang lebar soal intrik internal Partainya yang masing masing berusaha menarik ABRI dalam intrik tersebut. Itu dipicu oleh sifat jelous partainya yang melihat Pak Harto semakin dekat dengan kelompok Islam intelektual, yaitu ICMI. “ Sudah saatnya Pak Tua itu dijatuhkan.” Katanya geram.
***
Ketika badai krisis Asia datang dari Thailand, bangunan itu roboh seolah tak pernah memiliki pondasi moral. Rupiah anjlok, bank-bank kolaps, dan harga bahan pokok naik seperti rakit kehilangan tali. Rakyat mulai lapar; mahasiswa turun ke jalan. Namun yang lebih mengerikan dari krisis ekonomi adalah krisis kepercayaan—rezim kehilangan legitimasi, kehilangan arah, kehilangan hati rakyatnya.
Orde Baru bukan hanya jatuh karena angka inflasi atau kurs dolar, tetapi karena kehilangan makna moralnya. Sistem yang dibangun atas kontrol dan ketakutan tidak bisa bertahan ketika rasa takut hilang. Ketika rakyat tidak lagi takut, maka penguasa tidak lagi berkuasa.
Kekuasaan Soeharto retak bukan oleh peluru atau kudeta, tetapi oleh satu hal yang paling sederhana, yaitu kehilangan kepercayaan. Di saat rakyat lapar, pejabat sibuk menyelamatkan dana ke luar negeri. Ketika mahasiswa ditembak, televisi menyiarkan sandiwara tentang stabilitas nasional. Semua orang akhirnya tahu: negara ini telah dijalankan bukan untuk rakyat, tapi untuk melindungi lingkaran sempit yang kenyang oleh rente.
Dan di situ sejarah mengambil alih. Dalam satu pekan Mei 1998, ribuan orang memenuhi jalan, ribuan lainnya mengungsi dari ketakutan yang sama: bahwa bangsa ini telah kehilangan arah. Lalu Soeharto berdiri di depan kamera, dengan suara tua dan berat, menyerahkan kekuasaan yang pernah ia anggap titah Tuhan. Sejarah menutup bab, tanpa tepuk tangan.
***
Ketika Soeharto akhirnya mundur, aku menatap layar televisi bersama Ira. Kami diam lama. Layar menampilkan wajah tua yang letih, bukan kalah oleh demonstrasi, tapi oleh kehabisan napas sistem yang ia bangun sendiri.
Aku berbisik pelan, “Kita jahat ya, Ra ?”
Ia menjawab datar, “Dia lebih jahat.” Jawaban itu sederhana tapi menampar. Dalam sistem yang korup, tidak ada pahlawan. Semua hanya bagian dari mekanisme kehancuran yang saling menular.
Aku sering berpikir, kami bukan perampok, bukan penghianat negara. Kami hanya bagian dari sistem yang menciptakan dirinya sendiri, menjalankan logika tunggal kapitalisme yaitu lindungi aset, selamatkan diri. Tapi logika itu juga yang menghancurkan semuanya. Setiap keputusan rasional secara ekonomi, ternyata destruktif secara sosial. Dalam krisis, manusia berhenti menjadi warga negara; ia hanya menjadi angka di rekening bank. Dan ketika negara tak lagi bisa menjamin rasa aman, setiap orang mulai menulis sejarahnya sendiri, dengan tangannya masing-masing. Elite lebih dulu pindahkan uangnya ke luar negeri. dan rakyat miskin hanya pasrah menerima takdir berikutnya.
Kini aku tahu, currency collapse bukan sekadar runtuhnya nilai tukar, tapi pembalikan hierarki kekuasaan. Ekonomi menjatuhkan politik, dan politik menjatuhkan dirinya sendiri. Bukan karena revolusi, tapi karena kehilangan kepercayaan.
Dan di situlah aku mengerti, bahwa uang, seperti manusia, punya naluri bertahan hidup. Ia akan selalu bergerak ke arah yang paling aman, bahkan jika itu berarti meninggalkan tanah airnya sendiri. Karena pada akhirnya, dalam dunia kekuasaan dan pasar, kepercayaan adalah mata uang terakhir yang menentukan segalanya.
***
Aku datang ke rumah Ira di kawasan Kuningan, jakarta. Saat aku datang dia tunggu di ruang tengah. “ Katanya sakit ? kok engga tidur di kamar” Kataku menyalaminya. Usianya kini 63 tahun. Aku tahu ia aktif di NGO international yang berdedikasi masalah HAM. Dia tetap keliatan cantik dan pancaran mata cerdasnya tidak mengabur. “ Ah capek tiduran terus.” Katanya menyentuh pipiku dengan kedua telapak tangannya. “ Edi yang kasih tahu kamu ya”
“Ya. Katanya kamu sakit” Kataku.
“ Kalau bukan kabar sakit engga mungkin kamu mau kunjungi aku” Katanya tersenyum. Dasar orang politik selalu ada cara bersikap terhadap kelemahan orang lain. Dia tahu aku peduli dia. Dan itu selalu dimanfaatkan.
“Keadaan negeri ini makin kabur, Ale,” kata Ira perlahan. “Sejak periode kedua kekuasaan Jokowi, arah pemerintah tak lagi jelas. Kurs rupiah terus melemah, industri mati perlahan, rente tumbuh di antara puing birokrasi, dan korupsi menjelma kebiasaan sehari-hari. Demokrasi kini tinggal ritual tanpa makna, hanya prosedur yang membungkus kekuasaan. Sementara presiden berhasil mengkudeta lembaga-lembaga demokrasi secara konstitusional. Kita seakan berjalan mundur setelah berdarah-darah memperjuangkan reformasi 1998.”
Ira menatapku teduh, senyumnya pahit. “Awal kemerdekaan dulu,” katanya, “kita melihat cahaya surga di ufuk timur. Tapi kita hanya berdiri di pangkal akar, berusaha menggapai cahaya itu dengan tangan gemetar. Lelah, berdarah, dan menangis. Rezim berganti, tapi cahaya itu memudar. Negeri ini, Ale… sudah lama membusuk sejak Orde Baru. Soeharto jatuh dengan bau amis darah, tapi kita tak pernah berani menyebutnya revolusi. Kita hanya berani berkata: reformasi. Karena setiap kali ditanya mengapa, jawabannya selalu berbeda—dan kemunafikan sudah seperti air susu ibu; mengalir sejak kita lahir.”
Ia berdiri, mengambil dua buku dari rak: Democracy for Sale: Dark Money and Dirty Politics dan Republic, Lost. “Negara,” katanya lirih sambil menatap sampul buku itu, “tak lebih dari sekumpulan manusia yang berkuasa. Para menteri, birokrat, dan politisi—semuanya menyimpan hasrat untuk memperbesar pengaruh dan kekayaan. Dalam dirinya, manusia tetap makhluk yang menolak penderitaan, tapi pada waktu yang sama menjadi serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus.”
Aku menatapnya lama. “Manusia memang punya otak reptil,” kataku akhirnya. “Itulah yang mereka gunakan untuk menipu nurani. Mereka pandai menikmati hasil kerja orang lain lewat pajak, sambil berkhotbah tentang keadilan dan masa depan. Politik telah menjelma seni merampok dengan retorika. Perang atas nama strategi, perampasan lahan rakyat atas nama pembangunan, manipulasi kurs atas nama stabilitas moneter. Semuanya dilegalkan dalam bingkai kenegaraan.”
Ira terdiam. Dalam keheningan itu, aku melihat air matanya perlahan turun. Kami seperti diseret oleh kenangan masa muda — masa ketika kami percaya bahwa perubahan adalah mungkin, bahwa kata “rakyat” masih punya makna sakral.
“Lihatlah, Ale,” katanya dengan suara bergetar. “Kita sudah hidup di bawah tujuh presiden, dan yang kita pelajari hanya satu hal: negara tidak pernah ideal. Ia tak dibangun untuk menyejahterakan semua, hanya segelintir. Demokrasi menjanjikan kesetaraan, tapi justru melahirkan kasta baru: para teknokrat dan oligark yang pintar memanfaatkan kebodohan massa. Tapi apakah itu salah? Tidak sepenuhnya. Karena setiap sistem punya utopianya sendiri, dan di antara utopia dan realitas selalu ada elite yang pandai menulis skenario untuk dirinya.”
Aku menghela napas panjang. “Seperti dulu, setiap rezim datang dengan euforia dan mimpi baru. Tapi akhirnya semua berujung sama, yang kuat memakan yang lemah, yang cerdas menelan yang polos. Sejarah kita seperti lingkaran tanpa ujung.”
Ira tersenyum samar. “Manusia memang membuat sejarah,” katanya mengutip Marx, “tapi tidak dalam kondisi yang mereka pilih sendiri. Rezim jatuh bukan karena doa atau revolusi, tapi karena keadaan yang berubah diam-diam, sebuah tangan tak terlihat yang menarik tirai kekuasaan tanpa suara.” Ia menepuk bahuku pelan. “Seperti kejatuhan Soeharto, kan, Ale? Semua terjadi begitu saja.”
Aku menatapnya. Dalam senja usia kami, kami tak lagi berteriak di jalan. Kami hanya dua manusia yang menatap bangsa dengan rasa pasrah bercampur sayang. Kami tahu, perjalanan kami telah selesai. Tugas berikutnya bukan lagi milik kami — melainkan milik mereka yang muda, yang masih percaya bahwa masa depan bisa diubah. Karena pada akhirnya, seperti yang dulu kami pelajari dari sejarah: Negara boleh jatuh, tapi harapan tidak boleh ikut mati.
Dua puluh kima tahun kemudian, banyak yang lupa bahwa kejatuhan Orde Baru bukan sekadar kejatuhan seorang presiden. Ia adalah refleksi tentang batas kesabaran rakyat, tentang harga keadilan yang ditunda terlalu lama. Dan barangkali, setiap zaman memiliki versi Orde Barunya sendiri. Ketika kekuasaan lebih sibuk memelihara loyalitas daripada moralitas, ketika ekonomi dikelola untuk segelintir, ketika kritik dipandang ancaman, dan ketika rakyat kembali ditenangkan dengan retorika, bukan kesejahteraan..Sejarah tidak perlu diulang, jika kita mau belajar dari keruntuhan masa lalu. Tapi, seperti kata seorang filsuf, bangsa yang melupakan sejarah, akan menontonnya terulang dengan wajah berbeda

Tinggalkan komentar