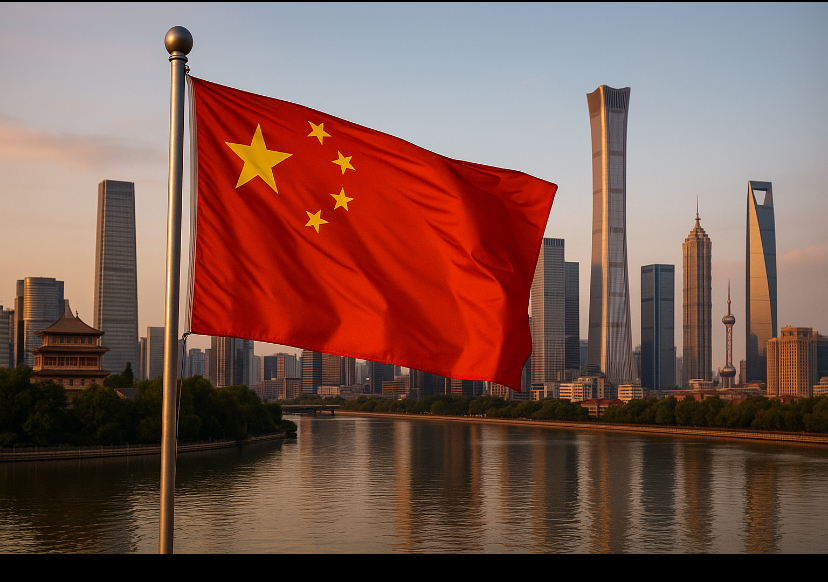
Sore itu, di sebuah lounge hotel yang menghadap ke Sungai Huangpu, saya dan Christine Tan duduk berhadapan. Langit Shanghai berwarna perak kebiruan, dipantulkan oleh kaca-kaca gedung Pudong di seberang sana. Di antara gelas teh hangat dan kertas kerja yang berserakan, kami membahas satu pertanyaan yang selalu menarik bagi ekonom mana pun: bagaimana Tiongkok bisa membangun begitu cepat, tanpa tampak ambruk oleh beban fiskalnya sendiri.
Christine menatap layar laptopnya yang menampilkan grafik dari IMF dan World Bank. “Lihat ini,” katanya pelan, “dalam dua dekade terakhir, panjang rel kereta di Tiongkok meningkat lebih dari tiga kali lipat. Kota-kota tier dua sekarang sudah seperti mini-Shanghai. Tapi defisit fiskalnya relatif stabil. Ajaib, bukan?”
Saya tersenyum.
“Itu bukan sihir, Chris. Itu sistem. Dan di Tiongkok, sistem berarti kendali negara atas tanah.”
Saya menjelaskan pelan, sementara ia menulis di buku catatannya yang rapi. “Di sini, semua lahan perkotaan dimiliki oleh negara. Pemerintah tidak menjual tanah, tapi menyewakannya. Dari hak guna lahan itu, mereka memperoleh dana segar untuk pembangunan. Ketika infrastruktur baru dibangun — jalan, jembatan, MRT — nilai lahan meningkat, dan pemerintah bisa menjual ulang hak gunanya dengan harga lebih tinggi. Begitulah mereka menciptakan siklus pendanaan mandiri.”
Christine menatap saya, lalu berkata, “Jadi tanah bukan beban, tapi modal negara. Negara jadi pemilik leverage terbesar.”
Saya mengangguk.
“Betul. Di Barat, negara berutang lewat obligasi publik. Di sini, negara ‘meminjam’ dari masa depan nilai tanahnya.”
Christine lalu bertanya, “Tapi bagaimana sektor swasta ikut terlibat tanpa menguasai semuanya?”
Saya menatap ke luar jendela, ke arah bangunan Lujiazui yang berkilau. “China membangun sistem kemitraan unik — public-private partnership yang diatur ketat. Ada istilah chengbao — semacam sistem kontrak di mana swasta mengelola aset publik, tetapi wajib menyerahkan bagian keuntungan kepada negara. Negara tetap pemilik izin dan tanah, tapi swasta diberi ruang menciptakan nilai. Namun karena ada kepastian hukum dan adil, investor swasta percaya. “
Christine tersenyum kecil. “Mirip sosialisme yang mempekerjakan kapitalisme sebagai manajer.”
Saya tertawa pelan.
“Ya, mereka memanfaatkan logika laba tanpa kehilangan kontrol. Kapitalisme di sini tak berdaulat — hanya dipekerjakan.”
Kami terdiam sejenak, memperhatikan langit yang mulai gelap.
Lampu-lampu dermaga mulai menyala. Christine membuka percakapan lagi, “Dan hasilnya, mereka punya konektivitas luar biasa. Tapi apakah itu benar-benar adil?”
“Sebenarnya tidak sepenuhnya,” jawab saya. “Model ini memang memperluas konektivitas, menurunkan biaya logistik, memperkuat pasar domestik. Tapi di sisi lain, ada konsekuensi sosial: penggusuran lahan, urbanisasi paksa, dan kesenjangan layanan publik antara migran dan warga kota lama.”
Christine mengangguk pelan. “Pemerataan ekonomi tak selalu berarti pemerataan kesejahteraan.”
“Benar,” jawab saya. “Redistribusi wilayah berhasil, tapi redistribusi sosial belum tentu. Artinya setiap keberangkatan kereta senja akan selalu ada orang yang tertinggal sambil menatap laju kereta dari kajauhan sampai hilang ditelan tikunga.”
Ia mencondongkan tubuh, penasaran. “Dan bagaimana mereka membiayai semua ini tanpa membuat neraca negara jebol?”
Saya menulis di atas tisu dengan pena hitam. “Lihat, mereka punya local government financing vehicles — LGFV. Pemerintah daerah menggunakan entitas ini untuk meminjam dana dengan jaminan aset lahan. Secara resmi, utangnya tidak muncul di neraca fiskal pusat. Tapi tetap ada — tersembunyi.”
Christine memotong, “Jadi semacam off-balance sheet liabilities?”
“Tepat. Tapi bedanya, mereka punya aset nyata untuk menutupnya: tanah, infrastruktur, dan BUMN produktif.”
Saya membuka data di tablet, menampilkan perbandingan aset nasional. “Total aset BUMN Tiongkok sekarang mencapai lebih dari lima kali PDB. Swasta pun hampir sama besar. Jadi ketika mereka berutang untuk membangun, mereka melakukannya dengan jaminan produktivitas nasional, bukan ilusi fiskal.”
Christine mengangkat alis.
“Artinya utang mereka disandarkan pada sesuatu yang nyata — hard assets.”
Saya mengangguk.
“Inilah yang membedakan. Negara lain berutang untuk bertahan, Tiongkok berutang untuk memperkuat dirinya. Mereka mengubah utang menjadi kapasitas ekonomi, bukan defisit politik.”
Christine menatap saya lama, lalu bertanya lirih, “Dan kalau Indonesia ingin belajar dari mereka?”
Saya menatap ke luar jendela lagi. Kapal kargo melintas di sungai, lampunya berpendar seperti lintasan harapan.
“Kita bisa belajar tiga hal,” kataku pelan. “Pertama, kendalikan sumber daya strategis. Tanah, air, energi — jangan serahkan pada rente. Kedua, gunakan konsesi swasta bukan sebagai hadiah, tapi kontrak sosial dengan kewajiban redistribusi. Ketiga, jaga integritas fiskal. Karena kalau korupsi masih dianggap bagian dari tradisi, tak ada model ekonomi yang akan menyelamatkan kita.”
Christine mengangguk, menutup laptopnya, lalu berkata, “China membangun karena mereka punya sistem. Indonesia bisa membangun jika punya nurani.”
Saya diam. Kalimat itu menancap dalam, seperti nyala neon di antara kabut malam Shanghai.
Kami keluar dari lounge. Angin sungai membawa aroma laut dan debu beton. Di seberang sana, kota ini berdiri sebagai monumen dari disiplin kolektif dan visi panjang — bukti bahwa pembangunan bukan sekadar tentang uang, tetapi tentang kehendak yang terorganisir.
Saya menatap Christine, lalu berkata pelan,
“Kadang, negara besar bukan yang paling kaya, tapi yang paling tahu cara memperlakukan tanahnya.”
Christine tersenyum. “Dan rakyatnya,” sambungnya.

Kami berjalan pelan di tepi Bund. Lampu kota Shanghai memantul di air — seperti refleksi dari masa depan yang dibangun dengan prinsip sederhana: bahwa tanah, bila dikelola dengan adil dan disiplin, bisa menjadi jembatan menuju kemakmuran — bukan sumber utang, apalagi sumber kemakmuran segelintir orang.
***
Tiongkok berhasil mengubah wajah ekonominya dalam empat dekade terakhir dengan kombinasi yang tampak kontradiktif — sosialisme negara yang mengendalikan sumber daya strategis dan kapitalisme pasar yang menggerakkan nilai tambah. Dalam arsitektur ini, negara menjadi pemegang hak atas tanah, sementara pasar menjadi penggerak efisiensi dan inovasi. Hasilnya adalah simbiosis antara kekuasaan politik yang sentralistik dan dinamika ekonomi yang kompetitif.
Di bawah sistem ini, tanah bukan sekadar ruang hidup, melainkan leverage fiskal dan pembangunan. Pemerintah pusat maupun lokal dapat memanfaatkan lahan negara untuk memperoleh pendapatan dari hak guna (leasing) dan pengembangan kawasan. Pendapatan ini menjadi modal pembiayaan infrastruktur tanpa harus sepenuhnya membebani APBN. Skema ini menciptakan circular model: pembangunan meningkatkan nilai lahan – lahan menghasilkan pendapatan baru – pendapatan digunakan membangun kembali.
| Infrastruktur | Panjang / Kuantitas Terakhir* | Keterangan |
| Rel kereta secara keseluruhan | ~ 162.000 km (2024) | “Total operational length of lines reached 162.000 km in 2024.” |
| Rel kereta cepat (High-Speed Rail, HSR) | > 48.000 km (2024) | Termasuk jalur kecepatan tinggi — bagian dari total rel. |
| Jalan tol / Expressway | ~ 190.700 km (diperkirakan untuk akhir 2024) | Data publik menyebut ~184.000 km di akhir 2023, estimasi naik. |
| Jalan raya nasional & jalan negara | > ~ 1.900.000 km (2024, seluruh jaringan jalan) | Mengacu pada jaringan jalan nasional yang sangat besar. |
| Jalur komunikasi optik (fiber-optic) | ~ 67.12 juta km (kilometer kabel serat optik, Juni 2024) | Infrastruktur telekomunikasi dasar, bukan persis “jalur komunikasi” seperti jalan, tapi relevan. |
Negara kemudian mengundang sektor swasta untuk menjadi mitra pembangunan melalui sistem konsesi dan pengelolaan cluster ekonomi. Wilayah dikembangkan menjadi zona campuran antara cluster komersial (perumahan, industri, logistik, perdagangan) dan cluster sosial (transportasi publik, perumahan rakyat, sekolah, dan layanan umum).
Prinsip yang diterapkan jelas, “Dari keuntungan kapitalis untuk mendanai keadilan sosialis.”
Negara memperoleh pajak dan pendapatan dari Land value capture dari adanya infrastruktur jalan toll, kereta komersial, kereta cepat, dan sistem telekomunikasi. Sementara hasilnya digunakan untuk membiayai layanan publik yang bersifat sosial. Dalam struktur ini, Tiongkok tidak melihat kapitalisme sebagai musuh, tetapi sebagai alat negara untuk memperluas kemakmuran bersama.
Namun, keberhasilan ini tidak tanpa konsekuensi. Pertumbuhan masif infrastruktur menyebabkan munculnya beban keuangan tersembunyi di tingkat lokal — terutama melalui Local Government Financing Vehicles (LGFVs), yaitu badan-badan pembiayaan daerah yang menjaminkan lahan atau proyek untuk memperoleh dana. IMF dan beberapa lembaga riset internasional mencatat adanya potensi risiko dari utang pemerintah daerah dan unreveal loan (utang di luar neraca resmi).
Meski demikian, Tiongkok mampu mengantisipasi risiko ini secara sistematis dengan langkah-langkah strategis, yaitu Sentralisasi pengawasan fiskal: Beijing memperkuat kontrol terhadap pembiayaan lokal dengan audit dan restrukturisasi LGFV. Kebijakan swap debt-to-bond: sebagian besar utang lokal dikonversi ke obligasi jangka panjang berbiaya rendah. Pemanfaatan aset negara sebagai buffer: bukan hanya kas, tetapi aset produktif BUMN dijadikan basis jaminan makro.
Kunci daya tahan ekonomi Tiongkok terletak pada imbangan antara utang dan aset. Walau tingkat leverage tinggi, total aset BUMN Tiongkok mencapai lebih dari lima kali PDB, sementara aset korporasi swasta juga memiliki skala yang sebanding. Dengan kata lain, utang Tiongkok didukung oleh aset nasional yang sangat besar dan produktif, bukan oleh janji kosong fiskal.
Dari perspektif makro, hal ini berarti setiap ekspansi infrastruktur tidak hanya menciptakan beban, tetapi juga meningkatkan kapasitas produktif nasional — memperkuat balance sheet negara.
Aset produktif seperti jaringan listrik, pelabuhan, kereta cepat, dan telekomunikasi menjadi instrumen ekonomi yang terus menghasilkan arus kas dan nilai tambah jangka panjang. Inilah yang disebut model leverage produktif — utang digunakan untuk menciptakan aset riil, bukan sekadar membiayai konsumsi atau subsidi.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, model Tiongkok menawarkan pembelajaran penting: kemakmuran tidak dibangun dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa cerdas aset nasional di-leverage untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Syarat utamanya adalah: Integritas fiskal dan hukum — agar pengelolaan aset negara tidak menjadi arena rente. Konsistensi kebijakan — sehingga kepercayaan investor dan publik tetap terjaga. Rasionalitas pembangunan — proyek infrastruktur harus memiliki nilai sosial dan ekonomi yang seimbang, bukan sekadar prestise politik.
Kesimpulan.
Tiongkok menunjukkan bahwa pembangunan masif bukan mustahil jika dikelola dengan disiplin fiskal, tata kelola kuat, dan legitimasi sosial yang terjaga. Negara bukan sekadar pemberi proyek, tetapi arsitek keseimbangan antara kapitalisme dan sosialisme.
Di bawah filosofi bahwa “setiap jengkal tanah adalah milik rakyat melalui negara,” Tiongkok membuktikan bahwa pembangunan dapat menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar akumulasi. Mereka membangun bukan dengan utang semata, tetapi dengan leverage dari aset nasional yang hidup dan berputar. Dan di sanalah letak perbedaan mendasar: Ketika negara lain sibuk berutang untuk bertahan, Tiongkok berutang untuk memperkuat dirinya.
Referensi
IMF (International Monetary Fund). People’s Republic of China: Staff Report for the 2024 Article IV Consultation. Washington, D.C., 2024. World Bank. China Economic Update: Balancing Productivity and Debt. Washington, D.C., Juni 2023. Asian Development Bank (ADB). Financing Urban Infrastructure in China: Leveraging Land and Local Assets. Manila, 2022. Liu, Zhi & Xue, Lan. China’s Infrastructure Development and Financing: Balancing Growth and Debt. Journal of Asian Public Policy, Vol. 15, No. 3, 2023. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). State-Owned Enterprises in China: Efficiency and Governance Reform. Paris, 2021.. Harvard Kennedy School – Ash Center. China’s Urban Transformation: Land, Debt, and Local Governance. Cambridge, MA, 2023. Naughton, Barry. The Chinese Economy: Adaptation and Growth. MIT Press, 2021. Fang, Kai & Zhao, Ming. Fiscal Federalism and Land-Based Finance in China. China Economic Review, Vol. 79, 2024. Zhang, Li & Lardy, Nicholas. China’s Debt Dilemma: Assets, Leverage, and the Future of Growth. Peterson Institute for International Economics, 2024. State Council of the People’s Republic of China. Guidelines on Strengthening Local Government Debt Management. Beijing, 2023.

Tinggalkan komentar