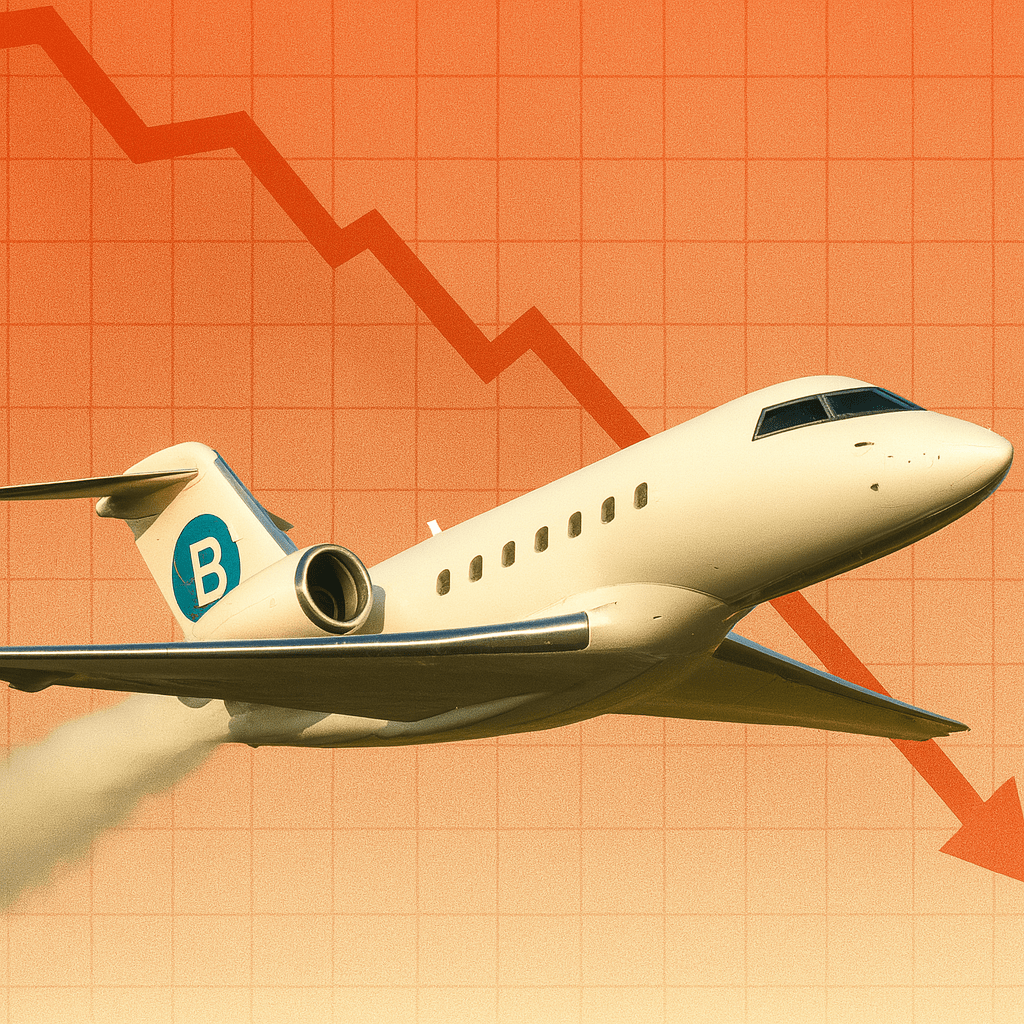
Suasana sore di Sapphire Lounge Executive seperti biasa: aroma kopi arabika bercampur wangi kulit koper dan suara lembut pengumuman keberangkatan. Dari balik kaca besar, pesawat tampak berbaris di landasan, menunggu giliran terbang menuju langit yang penuh ketidakpastian—seperti ekonomi negara yang sedang diguyur stimulus.
Aku duduk di pojok, membaca brief fiskal kuartal IV: pemerintah yakin konsumsi akan tumbuh 5,5% berkat program stimulus. Lalu, seorang wanita duduk di kursi sebelah. Wajahnya cantik, cerdas, berbalut blazer krem dan kacamata tipis. Ia melirik dokumen di tanganku. “Angka yang menarik,” katanya sambil tersenyum. “Tapi Anda kelihatan tidak terlalu yakin.”
Aku menatapnya, sedikit heran tapi senang dengan keberanian pembukaannya. “Saya hanya berpikir,” jawabku pelan, “bahwa stimulus karena produksi melemah itu bagus. Tapi kalau stimulus hanya untuk mendorong konsumsi, itu seperti menuang bensin ke api kecil—terang sekejap, tapi berasap lama.”
Ia menatapku serius.
“Jadi Anda tidak percaya pertumbuhan bisa datang dari konsumsi?”
“Percaya,” kataku, “tapi hanya kalau mesin produksinya sehat. Sekarang, PMI kita di bawah 50, ekspor lesu, kapasitas industri turun. Dalam kondisi begini, menambah konsumsi justru memperbesar uang beredar tanpa menambah barang. Hasilnya inflasi. Dan inflasi itu seperti utang moral: makin lama disangkal, makin mahal menebusnya.”
Wanita itu menyandarkan punggungnya, mengaduk kopi perlahan.
“Tapi masyarakat butuh dorongan daya beli, bukan?”
“Benar. Tapi daya beli itu seperti sayap burung—tidak berguna kalau ototnya lemah. Kalau ingin rakyat kuat membeli, yang harus diperkuat bukan dompetnya, tapi pabriknya, kebunnya, pasarnya. Konsumsi itu efek, bukan sebab.”
Ia tertawa kecil, suaranya ringan tapi menggoda.
“Anda bicara seperti ekonom yang baru saja patah hati oleh angka.”
Aku ikut tertawa.
“Angka memang sering mematahkan hati—apalagi kalau dijadikan ilusi. Kadang pemerintah jatuh cinta pada persentase PDB, padahal pertumbuhan sejati lahir dari produktivitas, bukan belanja tambahan.”
Ia menatapku lekat, kali ini lebih personal.
“Menarik. Saya suka orang yang bisa bicara tentang ekonomi tanpa membuatnya terdengar membosankan.” Ia berhenti sejenak. “Kalau boleh tahu, Anda siapa sebenarnya?”
Aku tersenyum.
Wanita itu menatapku lama, seolah menimbang sesuatu di kepalanya. lalu bersuara pelan tapi tajam, “Saya masih heran,” katanya, “mengapa di negara kita, setiap tahun investor mengajukan izin ke BKPM dengan angka fantastis, tapi realisasinya kecil sekali. Bukankah sampai tahun ini, nilai investasi yang mangkrak sudah di atas seribu triliun rupiah?”
Aku menatap keluar jendela, memandangi pesawat yang baru saja lepas landas—perlahan, mantap, dan pasti.
“Karena pesawat modal tak bisa terbang kalau ruang udaranya penuh kabut regulasi,” jawabku pelan.
Ia tersenyum, seperti menunggu penjelasan lebih ilmiah.
“Kabut regulasi?”
Aku mengangguk.
“Ya. Iklim investasi kita tidak buruk karena kekurangan uang, tapi karena kelebihan izin. Di atas kertas, Indonesia sudah punya omnibus law, OSS, dan berbagai deregulasi. Tapi di lapangan, birokrasi kita masih seperti labirin yang dibangun oleh orang yang tak ingin ada jalan keluar.”
“Jadi masalahnya bukan sistem, tapi mentalitas?”
“Lebih tepatnya: insentif. Sistem apa pun akan gagal kalau pejabat lebih dihargai karena menunda daripada mempercepat. Dalam teori kelembagaan, Douglass North menyebutnya institutional inertia—lembaga yang secara formal berubah, tapi perilakunya tetap feodal. Kita mengira sudah modern karena berkas sudah digital, padahal mentalitasnya masih analog.”
Wanita itu mengangguk pelan, matanya menatapku dalam.
“Saya pernah dengar istilah cost of doing business, tapi di sini, tampaknya ada cost of waiting.”
Aku tertawa kecil.
“Benar. Investor tak hanya bayar pajak dan upah, tapi juga waktu—yang di negeri ini sangat mahal karena tiap hari diukur dengan izin, rekomendasi, dan tanda tangan.”
“Lalu bagaimana dengan kebijakan fiskal dan insentif pajak yang katanya ramah investasi?”
Aku menyesap kopiku dulu sebelum menjawab.
“Secara teori, itu bagus. Tapi insentif pajak hanya efektif di negara dengan predictable governance. Di sini, regulasi bisa berubah setiap musim. Kadang menteri ekonomi bicara efisiensi, sementara lembaga lain menambah layer pengawasan baru. Akibatnya, investor global tidak melihat return, tapi uncertainty premium.”
Wanita itu menatapku seperti dosen yang baru menemukan mahasiswa menarik di seminar.
“Anda bicara seperti akademisi,” katanya lembut. “Kalau begitu, apa yang harus dilakukan pemerintah?”
“Sederhana tapi sulit,” kataku. “Bukan lagi soal menarik investor, tapi menjaga mereka tetap tinggal. Investasi tidak lahir dari janji, tapi dari kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan kejelasan insentif. Tiga hal itu adalah trinitas yang paling sulit dijaga di negeri demokrasi muda—karena setiap pergantian pejabat berarti pergantian kebijakan.”
Ia bersandar, menatap langit melalui kaca besar lounge.
“Menarik. Saya jadi paham mengapa banyak proyek berhenti di tengah jalan. Tapi apakah Anda tidak takut bicara sejujur itu? Di lounge seperti ini, kata-kata bisa terdengar sampai ke ruang tunggu diplomatik.”
Aku tersenyum.
“Kebenaran ekonomi selalu terdengar, tapi jarang didengar. Lagi pula, bicara tentang investasi di negeri sendiri bukan subversi, tapi patriotisme yang sepi.”
Ia tertawa kecil, lalu menatapku lagi dengan ekspresi lebih lembut.
“Anda tahu, percakapan ini lebih berharga daripada banyak seminar yang saya datangi.”
Suara boarding call baru saja berhenti. Lounge mulai lengang. Wanita itu—yang sejak tadi lebih banyak mendengarkan dengan penuh minat—menatapku dengan ekspresi ingin tahu.
“Boleh saya tanya sesuatu?” katanya sambil memutar sendok di cangkir kopinya. “Bagaimana Anda menilai kompetensi Purbaya sebagai Menteri Keuangan? Di media, dia sering bicara sangat berani, kadang seolah tak ada filter.”
Aku tersenyum kecil.
“Pertanyaan yang berani juga,” kataku. “Tapi begini, jabatan Menteri Keuangan itu sejatinya jabatan politik, bukan teknokrat murni. Ia diangkat berdasarkan hak prerogatif Presiden, bukan ujian kompetensi makroekonomi.”
Wanita itu mengerutkan kening sedikit, tapi tak menyela.
“Meski begitu,” lanjutku, “jabatan itu punya batas ruang gerak yang jelas. Ada undang-undang yang mengatur standar kepatuhan fiskal dan moneter—defisit maksimal 3% dari PDB, rasio utang, batas pembiayaan, transparansi APBN, dan koordinasi dengan BI. Jadi, siapapun Menkeunya, sejauh ia patuh pada kerangka itu, pasar akan tetap percaya.”
“Maksud Anda, personal competence tidak terlalu penting?”
“Bukan tidak penting, tapi tidak absolut. Yang dijaga adalah institusinya, bukan individunya. Rupiah dipercaya bukan karena nama menteri, tapi karena tata kelola fiskal yang konsisten. Obligasi negara—SBN—dibeli investor global bukan karena mereka suka Purbaya, tapi karena mereka percaya mekanisme fiskal Indonesia masih disiplin.”
Ia tampak berpikir, lalu tersenyum tipis.
“Tapi kadang komentarnya di media agak… ceplas-ceplos, tidak seperti teknokrat biasanya.”
Aku mengangguk pelan, menatap ke arah barista yang sedang menutup espresso machine.
“Ya, itu bukan gaya teknokrat, tapi gaya pasar modal. Purbaya itu lama di bursa—dia tahu fungsi isu dalam membentuk persepsi. Di dunia keuangan, isu adalah alat untuk menggerakkan harga sebelum data datang.”
“Jadi dia sedang bermain dengan persepsi?”
“Tepat sekali,” jawabku. “Ia ingin menjadi head of the curve—mendahului pasar dengan wacana. Kalau ia bicara duluan, pasar menyesuaikan, dan pemerintah punya ruang manuver psikologis. Tapi strategi semacam itu berbahaya bila dilakukan saat fundamental ekonomi rapuh.”
“Kenapa?”
“Karena di pasar keuangan, kepercayaan itu seperti kaca tipis. Sekali retak oleh pernyataan yang tak didukung data, ia pecah jadi volatilitas. Kalau defisit fiskal melebar, inflasi belum terkendali, dan rupiah tertekan, maka issue bukan lagi alat, tapi bola panas yang bisa mengguncang stabilitas politik.”
Wanita itu menatapku lama, kemudian tersenyum.
“Anda bicara seperti insider, tapi terdengar seperti dosen filsafat ekonomi.”
Aku tersenyum, mengangkat bahu.
“Mungkin karena ekonomi, pada dasarnya, bukan tentang angka, tapi tentang kepercayaan—dan politik adalah cara paling efisien untuk mengatur siapa yang percaya pada siapa.”
Wanita itu memutar cangkirnya perlahan, menatap ke arah jendela tempat pesawat menunggu giliran lepas landas. “Boleh saya jujur?” katanya pelan. “Suami saya… orang sukses. Ia memanjakan saya dengan uang, rumah, dan semua yang bisa dibeli. Tapi tidak dengan waktu. Hari-hari kami kering, percakapan kami tinggal formalitas. Kadang saya merasa bukan istri, tapi aksesoris.”
Aku diam sesaat. Hanya suara mesin espresso dari jauh yang terdengar.
“Aksesoris?” tanyaku perlahan.
“Ya,” katanya lirih. “Bagian dari pencitraan kesuksesan. Ia memberi segalanya kecuali dirinya. Dan semakin lama, yang tersisa hanya kemewahan yang dingin.”
Aku menatapnya—mata yang indah, tapi tampak menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan oleh kosmetik mahal atau gaun berkelas.
“Tidak ada hubungan yang sempurna,” kataku. “Bahkan pernikahan yang terlihat indah di foto pun adalah arena kompromi, kadang tanpa jeda, kadang tanpa keadilan. Tapi dari situlah kebahagiaan yang nyata lahir, yaitu ketika kita belajar berdamai dengan realitas, bukan melawannya.”
Ia menatapku dengan pandangan yang campur antara ingin mengerti dan ingin menolak. “Berdamai dengan realitas? Jadi kita harus menyerah pada kekosongan?”
Aku menggeleng pelan.
“Tidak menyerah. Menerima bahwa hidup bukan tentang kepenuhan, tapi tentang makna dari kekurangan. Seperti ekonomi, tak pernah ada keseimbangan sempurna, hanya fluktuasi yang terus diusahakan agar stabil. Begitu juga cinta, ia bukan soal siapa memberi lebih banyak, tapi siapa yang tetap bertahan saat nilai tukarnya menurun.”
Ia terdiam. Di matanya ada pantulan cahaya lampu lounge yang bergetar halus. “Lucu ya,” katanya lirih, “kita bicara tentang pasar, defisit, dan kebijakan… tapi ternyata yang defisit bukan hanya fiskal, tapi juga perasaan.”
Aku tersenyum.
“Ya. Dalam ekonomi manusia, defisit kasih sayang sering lebih berbahaya daripada defisit anggaran. Karena tidak ada bank sentral yang bisa menebusnya.”
Ia menatapku lebih dalam, seperti ingin mengingat kalimat itu.
“Jadi menurut Anda, apa yang harus saya lakukan?”
Aku menatap pesawat di luar yang sedang bersiap di landasan, mesinnya berderu, lampu strobo berkedip di antara kabut senja.
“Mungkin berhenti menghitung berapa yang hilang, dan mulai menghargai apa yang masih tersisa. Kebahagiaan itu bukan perasaan terus-menerus senang, tapi kemampuan untuk menemukan makna bahkan di saat sedih.”
Ia tersenyum—kali ini tulus, lembut, dan agak getir. “Kata-kata Anda terdengar seperti doa yang pernah saya lupakan.”
“Doa dan ekonomi punya satu kesamaan,” kataku, “keduanya butuh iman. Bedanya, di ekonomi kita beriman pada kebijakan; dalam hidup, kita beriman pada kemungkinan.”
Hening. Ia menatapku lama, lalu berbisik, “Saya tidak tahu siapa Anda, tapi pembicaraan ini… membuat saya merasa manusia lagi.”
Aku menatapnya. Senyumku pelan, sedikit pahit seperti kopi hitam di meja. Sekretaris bersama petugas sudah masuk ke lounge. Itu tanda saatnya masuk pesawat. “Sayang sekali, pesawat saya sudah siap. Moga takdir mempertemukan kita lagi. “
“Sebelum Anda pergi… boleh saya tahu nomor telp Anda?”
Aku jawab hanya dengan senyum, meski matanya menyiratkan kecewa yang elegan. Aku berjalan perlahan menuju gerbang, meninggalkan aroma kopi dan tatapan yang tertinggal di antara kilau kaca lounge. Dan dalam hati, aku teringat kalimat lama dari Keynes “Markets can remain irrational longer than governments can remain disciplined.” Mungkin juga cinta begitu.
Dari kaca lounge, kulihat ia masih menatap, mungkin masih berpikir apakah yang barusan ia dengar adalah teori ekonomi… atau sekadar pengakuan seorang pria yang terlalu lama menunggu pertumbuhan—dalam ekonomi, dan mungkin juga pria tua yang tak henti berharap negeri ini makmur..

Tinggalkan komentar