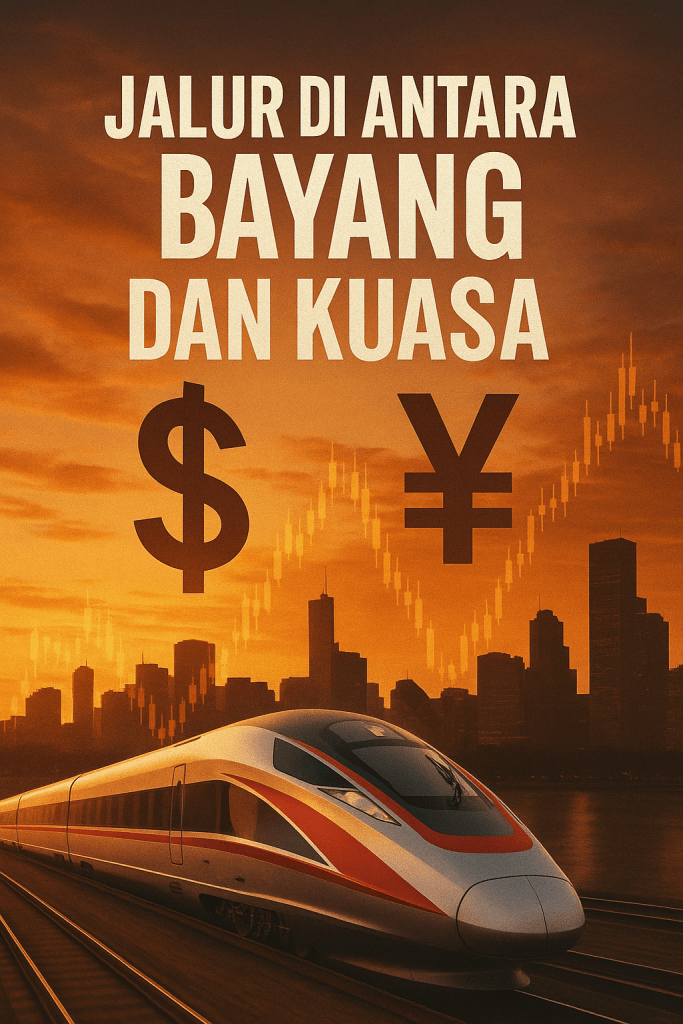
Pagi itu, langit Republik Garuda memantulkan cahaya pucat di atas Istana Merdeka Nusantara. Burung-burung beterbangan dari pepohonan taman istana ketika iring-iringan sedan hitam meluncur melewati gerbang barat. Di kursi belakang, Sabaruddin menatap berkas tebal di pangkuannya: peta koridor rel, tabel valuasi tanah, dan satu lembar di sampulnya bertuliskan: “Land Value Capture — Koridor Baja Nusantara.”
Hari itu ia tak sekadar menjual proyek. Ia menjual kepercayaan fiskal. Sebuah konsep yang, di tangannya, berubah dari teori ekonomi perkotaan menjadi alat negosiasi geopolitik.
Di ruang kerja Presiden Ardhanegara, dinding putih penuh foto proyek: tol, bandara, pelabuhan, dan jembatan. Di meja jati besar, laporan keuangan negara menampilkan deretan angka merah: defisit primer 1,7% PDB, yield surat utang 7,2%, subsidi energi menembus ambang aman.
Ketukan halus di pintu memecah hening.
“Pak, Sabaruddin sudah tiba,” ujar Sekretaris Negara.
“Silakan masuk.”
Sabaruddin melangkah dengan tenang. Ia menunduk hormat, lalu meletakkan map di atas meja Presiden.
“Pak, proyek kereta cepat ini tidak perlu jaminan negara. Dengan Land Value Capture, nilai tanah di sepanjang koridor akan meningkat. Dari situ investor menutup kembali modalnya.”
Presiden menatap dengan alis terangkat.
“Tanpa jaminan fiskal sama sekali?”
“Tanpa, Pak. Skemanya Business to Business. Joint Venture antara PSN dan JRG, masuk koridor Southern Silk Corridor. Pendanaannya dari Himalaya Development Bank. Negara cukup menyiapkan lahan dan memberikan kepastian tata ruang.”
Presiden menyandarkan tubuh.
“Kedengarannya terlalu indah untuk jadi nyata. Jelaskan ke saya secara teknis, apa itu Land Value Capture.”
Sabaruddin membuka lembar kedua presentasinya, menunjuk grafik sederhana berisi dua kurva.
“Begini, Pak. Dalam teori ekonomi perkotaan, setiap proyek infrastruktur besar menciptakan eksternalitas positif — akses meningkat, mobilitas naik, ekonomi sekitar tumbuh. Akibatnya, nilai tanah di sekitar proyek naik secara eksogen — bukan karena usaha pemilik tanah, tapi karena investasi publik.”
Presiden mengangguk perlahan.
“Nah,” lanjut Sabaruddin, “LVC adalah mekanisme untuk menangkap kembali sebagian kenaikan nilai itu ke kas publik. Pemerintah, melalui kebijakan, menangkap sebagian — misalnya 30% dari kenaikan itu — lewat pajak, sewa, atau kontribusi lahan.”
Presiden menatap peta di meja. “Dan itu cukup untuk menutup biaya proyek?”
“Jika dirancang dengan baik, bisa, Pak. Contoh: Hong Kong MTR. Mereka membangun jalur metro tanpa dana APBN. Pemerintah memberi mereka hak pengembangan properti di atas stasiun. Nilai tanah di situ naik, dijual ke developer, dan keuntungannya digunakan untuk membiayai rel. Mereka menyebutnya Rail plus Property Model.”
Presiden mengangguk. “Jadi Anda ingin meniru Hong Kong?”
“Menyesuaikan, Pak. Kita tak punya sistem pertanahan seefisien itu. Tapi prinsipnya sama — infrastruktur menghasilkan nilai, dan nilai itu harus kembali ke negara. Kalau tidak, semua manfaat publik akan bocor jadi rente privat.”
Presiden tersenyum tipis. “Anda bicara seperti ekonom, bukan kontraktor.”
“Karena ini bukan proyek fisik, Pak. Ini eksperimen fiskal. Kita ingin membuktikan bahwa public infrastructure bisa dibiayai oleh kenaikan nilai pasar yang ia ciptakan sendiri.”
Presiden berdiri, berjalan ke jendela, memandangi taman istana yang tenang. “Masalahnya, teori sering kalah oleh tanah, Udin. Begitu rencana proyek bocor, harga lahan naik lebih dulu. Yang untung justru spekulan, bukan negara.”
“Betul, Pak. Itulah kenapa kuncinya ada di land governance — penguasaan lahan sebelum proyek diumumkan. Pemerintah harus punya otoritas pengelola tanah, land banking authority, yang bisa membeli lebih dulu, menahan, lalu melepas setelah nilai naik. Dengan begitu, kita tangkap nilai tambah sebelum menguap jadi rente.”
Presiden berbalik menatapnya.
“Dan kalau gagal?”
“Kalau gagal,” kata Sabaruddin dengan nada datar, “negara akan tetap membayar — hanya saja lewat jalur yang lebih rumit. Melalui subsidi bunga, penjaminan tak langsung, atau bahkan PMN. LVC akan kehilangan maknanya, dan proyek ini berubah dari investasi menjadi liabilitas politik.”
Keheningan panjang. Presiden menatap berkas itu lagi, lalu berkata pelan: “Kau tahu, dalam politik, realisme kadang lebih berguna daripada teori.”
“Saya tahu, Pak,” jawab Sabaruddin. “Tapi teori kadang satu-satunya hal yang tersisa setelah realitas membakar semuanya.”
Presiden tersenyum samar.
“Kalau sulit, justru menarik. Sakura menunggu terlalu lama dengan studi mereka. Kita butuh sesuatu yang bisa diceritakan.”
Arka Santoso, Menteri Perhubungan, masuk beberapa menit kemudian, membawa map biru. Presiden menyerahkan berkas dari Sabaruddin. “Pelajari ini. Konsepnya LVC.”
Arka membuka halaman pertama. “Menarik. Tapi butuh kedisiplinan lahan yang mustahil di negara ini.”
“Mungkin,” kata Presiden pelan. “Tapi kalau berhasil, kita akan punya sejarah baru — membangun tanpa uang negara.”
Sabaruddin tersenyum kecil, menatap keluar jendela. Ia tahu, di negeri yang haus simbol, bahkan teori ekonomi bisa berubah jadi alat politik — dan di tangan yang tepat, sebuah konsep bernama Land Value Capture bisa menjadi mantra paling berbahaya yang pernah diucapkan di ruang istana.
***
Sore itu, ruang rapat di lantai delapan Gedung Cakrawala Transportasi dipenuhi lembar peta, peta satelit, dan kertas kerja tebal berjudul “Evaluasi Teknis Model Pembiayaan LVC — Koridor Baja Nusantara.”
Arka Santoso, Menteri Perhubungan, duduk di ujung meja. Di sekitarnya hadir Dr. Kania Wiradipura, pakar kebijakan fiskal; Ir. Dimas Raditya, ahli geodesi dan tata ruang; serta Dio Prasetya, ekonom muda lulusan London School yang baru pulang dari ADB.
Arka membuka rapat tanpa basa-basi.
“Kita semua tahu ide Sabaruddin sudah sampai ke Presiden. Kita harus menilai bukan dari ideologi, tapi dari feasibility. Saya ingin dengar: LVC ini logis atau hanya retorika?”
Dr. Kania menyesap kopinya, lalu berkata tenang: “Secara teori, Pak, Land Value Capture memang elegan. Ia berangkat dari prinsip Henry George—bahwa kenaikan nilai tanah akibat investasi publik seharusnya dikembalikan ke publik. Tapi, seperti semua teori Public Finance, keindahannya sering berhenti di papan tulis.”
“Masalahnya di mana?” tanya Arka.
“Dua, Pak. Pertama, disiplin lahan. Tanpa land banking authority, negara tak bisa mengontrol kenaikan nilai sebelum proyek diumumkan. Kedua, transparansi valuasi. Appraisal tanah kita masih sangat rentan moral hazard. Begitu koridor diumumkan, harga naik tiga kali lipat — bukan karena nilai ekonomi, tapi karena rumor.”
Dio menimpali dengan nada muda tapi tajam.
“Di atas kertas, LVC bisa menutup 20–30% biaya proyek. Tapi kalau spekulasi terjadi lebih dulu, nilai tambah itu sudah dimakan pasar. Hasil akhirnya, negara tetap keluar uang, hanya lewat mekanisme lain — PMN, penjaminan, atau fiscal transfer terselubung.”
Ir. Dimas menambahkan sambil menunjuk peta besar di layar. “Jalur yang diusulkan Sabar itu melewati delapan kabupaten. Lima di antaranya belum punya rencana detail tata ruang yang disahkan. Artinya, tak ada dasar hukum untuk menentukan zona kenaikan nilai. Kalau ini dipaksakan, kita masuk wilayah abu-abu antara kebijakan publik dan rente politik.”
Arka menyandarkan tubuh, menatap mereka satu per satu. “Jadi, kalian semua sepakat ini berisiko?”
Dr. Kania mengangguk.
“Berisiko, tapi bukan mustahil. Kalau pemerintah berani membentuk Urban Value Authority, seperti di Hong Kong atau Seoul, LVC bisa jadi instrumen off-budget financing yang efisien.”
“Masalahnya,” sela Dio, “di negara seperti kita, off-budget sering berubah jadi off-accountable.” Semua tertawa kecil, tapi getir.
Arka membuka berkas dari mapnya: Policy Brief ADB, 2019. Ia membaca keras-keras: “LVC sukses jika: (1) lahan dikuasai publik sebelum proyek dimulai, (2) nilai tambah dapat diukur objektif, (3) hasil tangkapan digunakan kembali untuk pelayanan publik.” Ia berhenti, menatap kosong ke luar jendela. “Kita gagal di ketiganya.”
Dr. Kania menatapnya.
“Tapi Bapak tahu, Presiden tak mencari kesempurnaan ekonomi. Beliau mencari simbol politik. Speed narrative. LVC adalah cara untuk mengatakan: kita membangun tanpa utang baru.”
“Padahal,” ujar Dio, “utang itu tetap ada — hanya berubah nama.”
“Benar,” sambung Dimas. “Dan ketika cost overrun muncul, mereka akan ubah peraturan. Seperti yang pernah terjadi di proyek Skyline Urban Rail di negara tetangga: dari B2B, berubah jadi G2G lewat sovereign backdoor guarantee.”
Arka berdiri, berjalan ke papan tulis. Ia menggambar lingkaran besar bertuliskan “Nilai Tanah Naik”, lalu panah ke “Kenaikan Rente”, lalu ke “Kehilangan Fiskal”. Kemudian ia menulis di bawahnya: “Kita bukan kekurangan ide. Kita kekurangan tata kelola.”
Ia menoleh ke timnya.
“Sabar pikir ia menjual konsep, tapi sebenarnya ia sedang menawarkan kita ilusi. Tapi ilusi ini indah, dan di politik, kadang keindahan lebih berguna daripada kebenaran.”
Dr. Kania menatapnya lama.
“Dan kalau Presiden memutuskan lanjut?”
Arka menatap papan tulisnya. “Kita ikuti. Tapi kita catat semuanya Karena suatu hari nanti, ketika proyek ini membengkak, laporan-laporan inilah yang akan menjadi catatan dosa—atau pembenaran.”
Suasana hening. Hanya bunyi pendingin ruangan yang terdengar, seperti desis panjang sebuah rel yang mulai bergetar dari kejauhan. Dio menatap ke luar jendela dan berbisik lirih: “Setiap infrastruktur besar dimulai dari mimpi, tapi berakhir sebagai akuntansi.”
Beberapa jam kemudian, Arka menulis memo internal kepada Presiden “Land Value Capture dapat dijadikan sumber pembiayaan kreatif jika syarat-syarat kelembagaan dipenuhi. Namun tanpa kontrol lahan, nilai tambah akan bocor, dan tanggung jawab fiskal berisiko kembali ke APBN.” “Dengan hormat, saya merekomendasikan pendekatan bertahap, bukan total.”
Ia menutup laptopnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri: “Dalam sejarah pembangunan, semua orang ingin menjadi pahlawan kemajuan. Tak banyak yang mau menjadi penjaga neraca.”
***
Sore hari. Lounge Hotel Mulia Nusantara beraroma teh oolong dan kayu manis. Lampu gantung berpendar lembut di langit-langit marmer. Di meja sudut dekat jendela, Sabaruddin, Li Wei dari JRG, dan Chen Jun dari Himalaya Development Bank (HDB) duduk mengitari meja kaca bundar. Tiga cangkir oolong mengepul, seperti simbol tiga kepentingan yang sedang mencari bentuk: politik, tanah, dan uang.
Li Wei membuka percakapan dengan nada formal namun tajam.
“Presiden Anda tampak tertarik,” katanya dalam bahasa Inggris beraksen lembut. “Tapi bagi kami, proyek ini tak bisa dimulai tanpa jaminan lahan dan kepastian izin. Kami bicara soal aset dasar, bukan hanya narasi kebijakan.”
Sabaruddin mengangguk pelan.
“Itu sebabnya saya membangun kerangka Land Value Capture. Jika koridor kita kuasai sejak tahap pra-konstruksi, kenaikan nilai tanah bisa dikonversi menjadi financial leverage. Nilai masa depan tanah—future appreciation—bisa kita jadikan agunan untuk pinjaman tahap pertama. Semakin cepat kita kuasai, semakin besar capturable value sebelum pasar bergerak liar.”
Chen Jun meletakkan cangkirnya perlahan, senyum tipis di wajahnya. “Di negeri kami,” katanya, “kami menyebutnya urban alchemy—tanah berubah jadi emas. Tapi kuncinya bukan tanahnya, melainkan siapa yang menulis kontrak pertama atasnya.”
Udin menatapnya lurus. “Di sini, alkimia bekerja di bawah matahari, Pak Chen. Semua orang bisa melihat prosesnya, tapi tak ada yang benar-benar menguasai bayangannya.”
Li Wei tertawa kecil.
“Bayangan yang Anda maksud itu apa? Mafia tanah? Atau pejabat daerah yang menjual dua kali?”
“Lebih dalam dari itu,” jawab Udin. “Bayangan itu adalah selisih antara nilai ekonomi dan nilai politik. LVC menuntut kita menangkap kenaikan nilai yang diciptakan publik, tapi dalam praktiknya, yang pertama menangkap justru orang-orang yang paling dekat dengan keputusan.”
Chen Jun mengangguk.
“Jadi Anda ingin mengamankan nilai sebelum politik menyentuhnya?”
“Bukan mengamankan,” kata Udin. “Menginstitusionalisasi. Kalau negara bisa mengubah future land appreciation menjadi securitized asset, proyek ini tidak butuh APBN sepeser pun. Kami buat Special Purpose Vehicle (SPV) yang memegang lahan sepanjang koridor, lalu gunakan sertifikat tanah sebagai underlying untuk obligasi proyek. Investor membeli bukan karena keretanya, tapi karena tanah di bawahnya.”
Chen Jun menatapnya lama.
“Menarik. Jadi uang proyek sebenarnya berasal dari nilai masa depan, bukan dari kas sekarang.”
“Benar,” jawab Udin. “LVC bukan teori ekonomi. Ini mesin waktu fiskal — menarik nilai masa depan ke masa kini, lalu menjualnya dalam bentuk keyakinan bahwa pertumbuhan tak akan gagal.”
Li Wei tersenyum, menyilangkan tangan.
“Dan jika gagal? Kalau harga tanah jatuh sebelum obligasi lunas?”
Udin diam sesaat, lalu menjawab tenang.
“Maka tanah menjadi hutang, bukan aset. Tapi di negeri ini, hutang pun bisa dijustifikasi sebagai pembangunan.”
Mereka bertiga tertawa—pendek, dingin, diplomatik. Di luar jendela, langit sore berwarna tembaga, dan bayangan rel yang belum ada tampak memanjang di kejauhan — seolah menembus cakrawala, menuju utara, menuju kuasa.
Li Wei menatap keluar jendela.
“Anda tahu, Tuan Sabaruddin, kami menyukai cara Anda berpikir. Di dunia finansial, tanah selalu menang. Ia tidak pernah menua, tidak pernah lari. Tapi ia selalu menelan siapa pun yang terlalu percaya padanya.”
Udin tersenyum tipis, menatap cairan teh yang tinggal separuh. “Saya tahu. Karena di balik setiap kenaikan nilai tanah,” katanya pelan, “selalu ada satu hal yang tak pernah berubah: seseorang sedang membayar harga yang tak terlihat.”
***
Tokyo, dini hari. Lampu-lampu Marunouchi masih menyala di antara kabut dingin musim semi. Di lantai 27 kantor Sakura Infrastructure & Cooperation Agency (SICA), Kenji Tanaka menatap layar yang menampilkan siaran pers dari Republik Garuda: “Pemerintah mempertimbangkan penawaran alternatif untuk proyek kereta cepat melalui model B2B bersama Dinasti Timur.”
Ia menatap layar itu lama, lalu berbisik pelan, “Impossible…”
Tanaka menekan tombol intercom.
“Hubungkan saya dengan Duta Besar Matsumoto di Jakarta. Sekarang.”
Beberapa jam kemudian, matahari baru naik di Jakarta. Di kedutaan besar Sakura, ruangan konferensi beraroma kayu hinoki dan kertas tinta segar. Di satu sisi meja, Duta Besar Matsumoto duduk dengan wajah kaku. Di seberangnya, Arka Santoso, Menteri Perhubungan, tampak letih tapi berusaha tenang.
“Tuan Arka,” kata Matsumoto dengan nada berat, “kami sudah enam tahun bekerja bersama tim Anda. Kami biayai feasibility study, riset kebumian, seismic design, dan tremor simulation. Semua dengan teknologi terbaik kami. Dan tiba-tiba, pemerintah Anda bergeser arah? Mengapa?”
Arka menghela napas.
“Proposal Anda tetap berharga, Tuan Dubes. Tapi Presiden ingin model tanpa jaminan negara. Purely business-to-business.”
Matsumoto menatapnya tajam.
“Kami tahu istilah itu. Tapi realitas ekonomi tak bisa diputarbalikkan. Jepang menawarkan pinjaman yen loan dengan bunga 0,1 persen per tahun, tenor 40 tahun. Kami beri masa tenggang sepuluh tahun penuh. Anda tak akan temukan syarat semurah itu di dunia internasional.”
Arka mengangguk pelan.
“Benar, bunga nominal Anda rendah. Tapi kalau dihitung dari cost of fund dan hedging untuk risiko kurs yen terhadap rupiah, total efektifnya bisa di atas dua persen. Sementara Dinasti Timur datang dengan pinjaman berbasis dolar, bunga sekitar tiga persen tapi tanpa sovereign guarantee. Artinya, beban risiko fiskal tidak langsung masuk APBN.”
Dubes Matsumoto memutar cangkir tehnya perlahan. “Tapi tetap saja, risiko itu hanya berubah bentuk, bukan menghilang. Anda pikir pasar tak tahu? Semua investor global akan membaca sinyal itu sebagai hidden sovereign risk. Percayalah, pasar uang lebih cepat dari diplomasi.”
Arka diam, lalu berkata hati-hati: “Presiden melihatnya bukan hanya dari bunga, tapi dari ruang politik. Pinjaman tanpa jaminan berarti tidak perlu dibahas di parlemen. Dalam situasi fiskal sekarang, itu keputusan yang… efisien.”
Matsumoto menatapnya dalam-dalam. “Tuan Arka, ini bukan sekadar bisnis. Ini soal kepercayaan — trust. Kepercayaan itu dibangun dari komitmen jangka panjang, bukan dari bunga jangka pendek.”
Keheningan menggantung di udara. Hanya terdengar dengung lembut pendingin ruangan dan jarum jam yang berdetak.
***
Ruang rapat Istana Merdeka Nusantara sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu putih memantulkan bayangan di meja panjang jati tua, tempat tiga orang duduk dalam diam yang sarat makna: Presiden Ardhanegara, Menko Maritim, dan Sabaruddin (Udin). Di seberang mereka, Arka Santoso, Menteri Perhubungan, membuka map besar penuh catatan.
“Tim Sakura kecewa, Pak,” ujar Arka pelan. “Secara teknis mereka paling siap. Studi enam tahun lengkap — soil dynamic, seismic impact, hydrological model. Tapi mereka minta sovereign guarantee.”
Menko menyela cepat, suaranya kering. “Nah, masalahnya di situ. Sovereign guarantee adalah rantai halus yang menjerat fiskal kita setiap kali kita ingin melangkah cepat.”
Presiden mengetuk meja pelan, satu kali, lalu dua kali. “Kita terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang pinjaman antarnegara. Dulu kita percaya bahwa development loan adalah jalan menuju kemerdekaan ekonomi. Sekarang, utang antarnegara justru jadi bentuk kolonialisme baru: bukan dengan senjata, tapi dengan spreadsheet.”
Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela tempat matahari mulai tenggelam di atas Monas. “Kita perlu model baru: cepat, murah, dan tanpa beban fiskal. Kalau negara ingin bertahan di abad kecepatan, kita tak bisa lagi berjalan dengan langkah birokrasi abad lalu.”
Sabaruddin menimpali dengan nada yakin. “Itulah kenapa saya ajukan skema B2B. JRG siap menandatangani. Pendanaan dari HDB sudah disiapkan, bahkan term sheet sudah mereka kirim lewat jalur diplomatik. Asal lahan clear, groundbreaking bisa dimulai tahun depan.”
Presiden beralih pada Arka. “Bisakah lahan diamankan?”
Arka menarik napas dalam. “Butuh koordinasi lintas kementerian: ATR, BPN, Pemda, dan BUMN. Butuh waktu, Pak. Karena begitu kabar keluar, spekulan tanah akan menyerbu lebih cepat dari buldoser.”
“Kita tidak punya waktu,” jawab Presiden datar. “Bulan depan saya ke Dinasti Timur. Saya ingin sinyal jelas sebelum itu.”
Keheningan turun. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar—dingin, teratur, seperti nafas birokrasi yang sudah kehilangan denyut manusia.
***
Dua minggu kemudian, di ruang sidang Komite Tender Nasional di Bappenas, dua proposal tergeletak di meja panjang. Satu dari Sakura Consortium, tebal 2.400 halaman — penuh grafik, simulasi, dan analisis risiko multi-skenario. Satu lagi dari JRG–HDB, tipis tak sampai seratus halaman, tapi di halaman depannya tertulis dengan huruf besar: “Proyek siap dimulai enam bulan setelah kesepakatan. Tanpa jaminan negara.” Arka membaca dua kalimat itu berulang-ulang. Ia tahu, di dunia politik, kata “tanpa jaminan negara” lebih memikat dari seribu tabel sensitivitas. Kecepatan telah menjadi filsafat baru pembangunan. Dan dalam filsafat itu, kehati-hatian dianggap bentuk kemunduran.
“Kita hidup di era di mana due diligence dikira pesimisme,” pikir Arka. “Dan yang disebut kemajuan hanyalah kemampuan untuk menandatangani lebih cepat dari yang lain.” Ia menghela napas panjang.
Kemudian, malam itu juga, di ruang kerjanya yang sunyi, ia menulis memo empat halaman untuk Presiden:
Kepada: Yth. Presiden Republik Garuda
Perihal: Catatan Teknis Skema Pembiayaan LVC dan Risiko Implementasi
- Tanpa kontrol negara, proyek berpotensi menjadi instrumen rente. LVC akan terhambat oleh spekulasi lahan yang tak terkendali.
- Valuasi tanah akan naik sebelum proyek dimulai, menggerus seluruh potensi value capture.
- Risiko pembengkakan biaya (cost overrun) akan meningkat akibat perubahan desain dan klaim harga lahan.
- Dalam kondisi fiskal seperti saat ini, setiap liquidity squeeze di konsorsium B2B akan kembali ke APBN melalui penjaminan tidak langsung (implicit guarantee).
- Konsep “tanpa jaminan negara” hanya valid bila risiko politik dan lahan sepenuhnya dikelola oleh swasta, yang dalam praktiknya nyaris tak pernah terjadi.
Kesimpulan: “LVC bukan gagal secara konsep, tapi rentan dalam implementasi. Ia butuh negara yang kuat, bukan negara yang tergesa.”
Dua hari kemudian, memo itu bocor ke media. Judul utamanya memenuhi laman portal nasional: “Menteri Perhubungan Kritik Skema Dinasti Timur: Proyek Rawan Rente dan Spekulasi.”
Istana bergolak.
Di ruang kerja Presiden, Sekretaris Kabinet membaca laporan breaking news dengan wajah tegang. Menko Maritim sudah lebih dulu duduk bersilang tangan, wajahnya datar. Presiden hanya diam, menatap layar televisi yang menayangkan potongan berita: wajah Arka dengan kutipan tajam di bawahnya.
“Pak, kita perlu respon resmi,” ujar Sekkab.
Presiden mematikan televisi perlahan, lalu berkata tenang tapi tajam: “Respon resmi nanti. Sekarang saya ingin tahu, siapa yang bocorkan memo itu. Dan satu hal lagi—siapkan keputusan pengganti Menteri Perhubungan.”
Malam itu, di rumah dinasnya yang remang, Arka duduk di beranda memandangi langit Jakarta. Ia tahu nasibnya sudah diputuskan bahkan sebelum matahari terbit. Tapi hatinya tenang. Karena dalam dirinya ia tahu: “Kecepatan bukanlah ukuran kemajuan, jika relnya dibangun di atas tanah yang tak pernah diukur dengan nurani.”
Ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya: “Dalam ekonomi pembangunan, keberanian bukan berarti bergerak cepat, tapi berani menolak saat yang lain berlari menuju jurang.”
Angin malam menggerakkan halaman itu pelan, dan di kejauhan, suara sirene kota terdengar seperti denting rel baja yang belum jadi — menunggu siapa yang akan jadi korban berikutnya dalam upacara yang disebut “pembangunan.”
***
Ruang kerja Presiden siang itu dipenuhi cahaya putih dari jendela besar. Namun suasananya gelap. Di meja jati yang sama tempat Arka dulu memaparkan risiko, kini duduk Sabaruddin dan Menko Maritim. Di hadapan mereka, Presiden Ardhanegara tampak letih, tapi matanya dingin dan mantap.
“Saya sudah baca memo Arka,” katanya tanpa ekspresi. “Dia benar dalam analisis, tapi salah dalam waktu. Kita tidak sedang mencari kebenaran, kita sedang mencari momentum.”
Menko mengangguk kecil. “Arka teknokrat murni. Tapi dunia pembangunan tidak hidup dari logika, Pak. Ia hidup dari belief. Dari kepercayaan bahwa pertumbuhan akan datang karena kita menginginkannya cukup keras.”
Presiden memandangi peta besar di dinding: garis merah jalur kereta cepat yang membelah pulau Jawa seperti urat nadi ekonomi baru. “Belief, ya? Seperti zaman IMF dulu. Mereka datang membawa doktrin: tighten, privatize, liberalize. Sekarang kita menciptakan doktrin versi sendiri: build fast, borrow smart, spend later.”
Sabaruddin menunduk hormat. “Model LVC kita, Pak, memang bukan cuma soal keuangan. Ia adalah narrative economy—cerita tentang negara yang mampu membiayai dirinya sendiri di tengah keterbatasan fiskal. Di dunia yang kehilangan ideologi, narasi semacam ini jauh lebih kuat daripada instrumen ekonomi manapun.”
Presiden tersenyum tipis. “Baiklah, kalau begitu jadikan cerita itu kenyataan.” Ia menandatangani surat keputusan. “Menteri Perhubungan diberhentikan dengan hormat. Tugas pengawalan proyek kereta cepat diserahkan kepada Menteri BUMN.” Tanda tangannya terdengar jelas—suara pena menembus sunyi seperti lonceng kematian birokrasi.
Keesokan harinya, media nasional penuh tajuk: “Presiden Reshuffle Kabinet, Menteri Perhubungan Diganti.”. Bagi publik, ini hanya berita rutin. Bagi para pelaku di baliknya, ini adalah babak baru dari ekonomi politik yang sedang menulis ulang dirinya.
***
Di ruang rapat Kementerian BUMN, Ratna Wirawan, teknokrat yang ditunjuk memimpin Komite LVC, membentangkan lembar konsep. “Tugas utama kita,” ujarnya, “membangun mekanisme LVC yang realistis. Kita harus menilai tanah bukan sebagai aset mati, tapi sebagai financial instrument yang bisa disekuritisasi.”
“Artinya?” tanya Udin.
“Kita bentuk Land Holding Company—SPV di bawah konsorsium BUMN. Lahan di sekitar jalur kereta akan dipetakan, diberi sertifikat hak kelola, lalu digunakan sebagai dasar penerbitan obligasi proyek. Kita jual masa depan hari ini. Investor akan membeli bukan karena mereka percaya pada proyek, tapi karena mereka percaya pada nilai tanah.”
Menko tersenyum tipis.
“Kau tahu, Ratna, dulu IMF menyebut hal itu financial deepening. Sekarang, dunia menyebutnya creative leverage. Kita menciptakan uang dari ekspektasi.”
Ratna menatapnya serius.
“Ya, Pak. Tapi setiap ekspektasi membawa risiko. Kalau nilai tanah tak naik seperti yang diproyeksikan, SPV bisa gagal bayar. Dan karena BUMN kita pemegang saham mayoritas, beban akhirnya akan kembali ke negara.”
Udin menimpali dengan tenang. “Risiko adalah harga dari kedaulatan fiskal. Seperti kata Ha-Joon Chang, ‘semua negara maju melanggar teori ekonomi sebelum mereka sukses’. Kalau kita ingin melompat, kita tak bisa menghitung dulu berapa dalam jurangnya.”
Menko tertawa kecil.
“Saya suka cara berpikir Anda, Udin. Mungkin memang kita butuh sedikit gila untuk melahirkan sesuatu yang waras.”
Beberapa bulan berlalu. Komite LVC berubah menjadi mesin politik pembangunan. Setiap rapat bukan lagi membahas nilai tanah, tapi jumlah kamera yang akan meliput groundbreaking, berapa headline positif yang bisa diatur, dan siapa yang akan berdiri di belakang Presiden saat peletakan batu pertama.
Dalam satu rapat tertutup di Kementerian BUMN, Ratna berkata lirih kepada Udin, “Saya takut, Pak. Konsep LVC ini terlalu cepat jadi slogan. Kita bicara tentang land-based financing, tapi yang bergerak justru rente berbasis koneksi.”
Udin menatapnya. “Ratna, setiap ide besar akan dikorupsi oleh realitas. Tapi biarlah, asalkan masih ada sebagian kecil yang bisa bertahan murni.”
“Dan kalau tak ada yang bertahan?” tanya Ratna.
“Maka yang tersisa hanyalah keyakinan. Karena pada akhirnya, ekonomi pembangunan di negeri ini tak lebih dari teologi yang memakai angka-angka.”
Sementara itu di luar istana, papan-papan bertuliskan “Proyek Strategis Nasional — Jalur Baja Nusantara” mulai berdiri di sepanjang koridor. Harga tanah naik tiga kali lipat dalam sebulan. Kantor notaris dan makelar penuh antrean orang yang baru “mendengar kabar dari dalam.” Uang mulai berputar bahkan sebelum satu meter rel dipasang. Para investor lokal menyebutnya “pesta awal kemajuan.”
Namun di meja rapat istana, Presiden hanya berkata pelan kepada Menko: “Lihat? Ekonomi bergerak. Uang mengalir. Itulah pembangunan—meski kadang kita belum tahu ke mana alirannya.”
Menko menatapnya sebentar lalu menjawab dengan nada filosofis:
“Pembangunan selalu seperti sungai, Pak. Ia membawa kehidupan, tapi juga lumpur. Yang penting, jangan pernah berhenti mengalir, karena kalau berhenti, ia akan jadi rawa.”
Presiden tersenyum kecil.
“Baiklah. Biarkan sungai itu mengalir.”
Ia menandatangani dokumen baru: Peraturan Presiden tentang Komite LVC Nasional. Sebuah lembaga baru lahir—bukan dari hasil perencanaan ekonomi, tapi dari keyakinan bahwa setiap proyek besar adalah mantra kebangsaan.
Malamnya, Ratna menulis catatan pribadi: “Negara ini tak kekurangan rencana, tapi kekurangan jeda. Di antara rencana dan realisasi, selalu ada keinginan untuk terlihat bergerak cepat. Padahal pembangunan sejati bukan tentang kecepatan, tapi tentang keseimbangan antara waktu dan kesadaran.”
Ia menutup laptopnya, menatap ke luar jendela gedung BUMN. Lampu-lampu Jakarta berpendar, seperti jutaan bintang yang tak tahu siapa yang sedang menatap siapa. Dan di kejauhan, bayangan jalur baja itu mulai tampak samar di atas tanah yang belum kering — sebuah rel yang dibangun di atas keyakinan bahwa masa depan bisa dicetak lebih cepat dari kesadaran.
***
Kaca jendela ruang rapat lantai 32 Himalaya Development Bank (HDB) memantulkan warna langit abu-abu pucat. Di dalam, udara dingin berpadu dengan ketegangan yang tak kasat mata. Di ujung meja panjang, Liu Sheng, Wakil Direktur Eksekutif HDB, menatap layar besar yang menampilkan peta Jalur Baja Nusantara dari Jakarta hingga Bandung. Garis merah di tengahnya berhenti di area berwarna abu — tanda tanah yang belum pasti.
“Tranche kedua belum bisa dicairkan,” katanya datar. “Tanpa LVC yang secured, risiko proyek terlalu tinggi. Kami butuh kepastian: siapa yang menjamin? Siapa yang benar-benar menguasai tanah?”
Suara Liu seperti palu. Tak meninggi, tapi dinginnya lebih tajam dari ancaman.
Li Wei, perwakilan dari JRG, mencoba menengahi. “Tuan Liu, kita harus mempertimbangkan konteks politik Garuda. Presiden mereka sudah berjanji bahwa proyek ini tanpa jaminan negara. Bila kita paksa, akan muncul isu kedaulatan.”
Liu mengibaskan tangannya pelan. “Kita tidak bicara politik, Li Wei. Kita bicara sovereign exposure. Di atas kertas memang B2B, tapi seluruh risiko faktual — lahan, izin, resistensi politik daerah — tetap ada di sisi Garuda. Kalau pemerintah mereka tak bisa menjamin itu, we must reconsider our exposure.”
Duta Besar Republik Garuda berdeham pelan, mencoba memecah tegangnya udara. “Pemerintah kami berkomitmen penuh. Presiden sendiri mengawal proyek ini. Namun, tata kelola tanah di daerah memang… kompleks.”
Liu berbalik ke arah Sabaruddin, yang duduk di ujung meja seberang. “Anda dulu yang datang membawa konsep Land Value Capture. Anda menjualnya kepada kami sebagai model pembiayaan yang aman, self-sustained, tanpa jaminan negara. Anda bilang, Garuda bisa mengelola lahan dan governance. Apa yang sebenarnya terjadi?”
Udin menarik napas panjang. “Yang terjadi, Pak Liu, adalah realitas. Pemerintah gagal menyediakan dan mengamankan 3.000 hektar lahan untuk TOD di sepanjang koridor. Begitu rencana diumumkan, harga tanah naik gila-gilaan. Mafia tanah masuk lebih cepat dari survei, dan kekuatan mereka tak bisa disentuh — bahkan oleh istana. Setiap meter tanah punya banyak pemilik: yang legal, yang politikal, dan yang tak terlihat. Kami ingin mengatur nilai, tapi akhirnya nilai yang mengatur kami.”
Liu Sheng bersandar di kursinya, menatapnya dalam-dalam. “Kalau begitu, model bisnis yang kami anggap secured — Land Value Capture sebagai dasar pinjaman proyek — kini berubah menjadi speculative risk. Tanah yang seharusnya menjadi collateral, kini jadi sumber volatilitas. LVC gagal, dan proyek kini hanya bergantung pada pendapatan tiket.”
Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada dingin, “Dan jika itu benar, maka meski 100 tahun berlalu, pendapatan tiket tak akan pernah menutup pinjaman. This project is no longer bankable.”
Keheningan menyelimuti ruangan. Di luar, salju turun perlahan di atas Chang’an Avenue — putih, halus, namun menutup semuanya tanpa meninggalkan warna.
Liu kembali berbicara, kali ini suaranya lebih rendah, tapi lebih tajam. “Masalahnya bukan bunga, tapi kedaulatan fiskal. Garuda ingin kemandirian tanpa disiplin, proyek tanpa biaya fiskal, pertumbuhan tanpa restrukturisasi. Mereka lupa: modal tidak mengenal nasionalisme. Modal hanya mengenal governability.” Li Wei menatap Liu.
“Apakah Anda masih yakin proyek ini layak?”
Liu tersenyum dingin. “Layak secara politik, tidak secara finansial. Tapi dalam dunia pembangunan, kadang politik lebih likuid daripada uang.”
Tawa pendek terdengar di sekeliling meja. Tawa yang lebih mirip bunyi logam beradu. Di luar gedung, lampu-lampu Beijing mulai menyala, memantulkan cahaya di salju — kota ini, simbol kapitalisme negara yang matang, telah lama menghapus batas antara kedaulatan dan leverage.
Liu Sheng menutup rapat dengan satu kalimat terakhir, “Sampaikan ke Presiden Anda. Kalau negara ingin proyek ini jalan, maka negara harus ikut membayar harganya.”
***
Jakarta, malam. Hujan deras membasahi atap kaca kantor Komite LVC Nasional. Di meja kerjanya, Rania Wirawan memegang surat resmi berkop HDB: “Pembiayaan proyek ditangguhkan hingga terdapat dukungan kedaulatan atau jaminan ekuivalen.”
Ia menatapnya lama, lalu menelpon istana. “Pak, HDB menunda pencairan tranche kedua. Mereka anggap proyek tak lagi secure. LVC gagal total karena lahan TOD tidak bisa diamankan. Tanah yang seharusnya jadi sumber nilai justru berubah jadi beban.”
Suara Presiden Ardhanegara terdengar pelan dari seberang sambungan. “Ada opsi. Negara bisa jadi penjamin tidak langsung.”
Rania terdiam.
“Artinya narasi B2B runtuh, Pak. Kita menjual ide bahwa proyek ini tanpa beban fiskal. Kalau negara masuk, LVC berubah jadi LCF — Land Cost Failure.”
Presiden menghela napas.
“Saya tak peduli. Yang penting proyek jalan. Politik juga punya bunga, Rania. Dan kadang, bunga politik lebih mahal dari bunga pinjaman.”
Rania menunduk, memejamkan mata. Ia tahu, keputusan sudah diambil bahkan sebelum percakapan itu dimulai.
Keesokan harinya, di rapat internal Kementerian Keuangan, seseorang berbisik lirih: “Kalau negara jadi penjamin, ini artinya contingent liability masuk ke kas fiskal.”
Seorang pejabat muda menjawab, “Ya. LVC gagal. Sekarang semua hanya bergantung pada tiket dan retorika.”
Semua tertawa kecil — tawa pahit yang hanya dimengerti oleh orang yang tahu bahwa di negeri ini, pembangunan kadang lebih mirip drama keuangan daripada kebijakan ekonomi.
Malamnya, di balkon istana, Presiden berdiri memandangi hujan yang reda. “Mereka pikir ini soal bunga,” katanya pada Menko di sampingnya. “Padahal ini soal waktu. Kita sedang membeli waktu dengan utang.”
Menko menatap langit kelabu di atas Monas. “Setiap bangsa berkembang dengan caranya sendiri, Pak. Bedanya, ada yang belajar dari masa depan, ada yang mengulang masa lalu.”
Presiden tersenyum tipis. “Kalau begitu, kita pilih yang kedua. Karena di sini, sejarah selalu lebih mudah dijual daripada akuntabilitas.”
Suara petir menggema jauh di utara — mungkin di atas jalur rel yang belum rampung. Dan di antara kilatan cahaya itu, tampak siluet tanah basah yang dulunya dijanjikan menjadi emas. Kini ia hanyalah simbol dari satu hal: bahwa pembangunan tanpa tanah adalah mimpi, dan mimpi tanpa realitas adalah utang..
***
Esoknya, Udin dipanggil ke Istana dalam rapat terbatas dengan cabinet.
“Menurutmu, kita harus beri jaminan?” tanya Presiden.
“Kalau tidak, proyek berhenti. Kalau iya, narasi runtuh,” jawab Udin
“Berapa bebannya?”
“Sekitar 4,6 miliar dolar ekuivalen, termasuk risiko kurs. Jika gagal bayar, cadangan fiskal tertekan.”
Presiden menatap keluar. “Kalau proyek berhenti, reputasi hancur. Kalau lanjut, fiskal menanggung.”
Rania menatap lurus. “Pak, ini bukan lagi proyek bisnis. Ini proyek politik.”
Presiden menghela napas. “Baik. Lanjut. Tapi jangan sebut jaminan negara. Cari istilah lain.”
Kepala fiskal: “Government Support Letter. Substansinya cukup untuk HDB, tanpa menyebut ‘garansi’.”
“Siapkan malam ini,” kata Presiden.
***
Dua hari kemudian, HDB menerima surat: “Pemerintah Republik Garuda mengakui kepentingan strategis proyek ini dan berkomitmen memastikan keberlanjutannya. Pemerintah akan memberikan dukungan yang diperlukan guna menjaga kelayakan finansial.”
Liu Sheng tersenyum. “Support letter. Bukan garansi, tapi semangatnya sama.” Ia menandatangani pencairan tahap dua.
“Mereka memilih politik alih-alih kehati-hatian. Seperti yang kita duga.”
***
Di istana, penandatanganan ulang kontrak disiarkan langsung. Presiden Ardhanegara tersenyum: “Simbol kemajuan bangsa.” Tepuk tangan menggema.
Di bangku tamu, Udin ikut bertepuk tangan dengan wajah kosong. Angka-angka di balik senyum itu tak pernah menyeimbangkan neraca.
“Pak Udin, puas?” tanya Rania setelah acara.
“Saya lega proyek jalan. Tapi saya tak tahu—apakah kita sedang membangun rel… atau jerat.”
Rania tersenyum getir. “Rel dan jerat kadang dibuat dari besi yang sama.”
Malam itu Udin menulis: “Dinasti Timur mengirim surat dengan tinta finansial; kita membalas dengan tinta politik. Di antara dua surat itu, tergambar nasib fiskal yang akan kita bayar pelan-pelan.”
***
Di kantor nya yang sederhana. Udin baca berita “GAR siapkan strategi pembayaran pinjaman TriBara. Pemerintah pastikan tak gunakan APBN.”
Udinter senyum tipis. “Kalimat itu sudah tujuh kali diulang sejak 2015,” gumamnya.
Rania datang.
“Lucu, ya. Dimulai dengan janji tanpa APBN, berakhir dengan APBN di setiap simpulnya.”
“Bukan lucu, Bu. Tragis. Yang paling rumit bukan menghitung bunga—tapi harga diamnya semua orang yang tahu.”
Rania menatap Udin sejurus. “Jika di negeri ini olgarki tidak punya otak bandit, mungkin kita akan punya banyak infrastruktur berkelas dunia tanpa harus dibayar APBN, tetapi dibayar dari value ekonomi atas proyek itu sendiri.TOD bukan hanya menjadi self financing tetapi juga memjadi mesin multiplier effect.
“Ya,” jawab Udin “Oligarki itu baik bila terdiri dari kaum hikmat dan bijaksana untuk keadilan social bagi semua, bukan bagi segelintir orang.”
***
Di istana, Presiden Bonanza yang baru setahun memimpin menatap laporan fiskal. Ia hafal angkanya, namun beban tetap sama tiap kali dibaca. Ia tahu proyek itu sudah menjadi simbol—tak ada yang berani membongkarnya. Anggaran meningkat hampir dua kali dari rencana awal. Mark up sebagai efek moral harzard tdak bisa dihindari “Yang penting rakyat melihat hasilnya,” argumen koalisinya. “Kalau harus membayar, ya nanti.” Dia menggeleng geleng kepala sendiri. ” Presiden baik itu memang harus tetapi lugu tidak boleh. Karena dia luar sana banyak bandit berbaju nasionalis.:
Malamnya, Udin menulis baris penutup di diary nya. “Kereta ini cepat, tapi setiap kilometernya dibayar oleh utang yang berjalan lebih lambat dari waktu. Kita membangun rel baja, namun yang melaju di atasnya adalah bayang-bayang komitmen yang tak pernah selesai.”
Di kejauhan, kereta malam melintas. Dalam derak rodanya, tersisa satu pelajaran: Dalam negeri yang terlalu percaya pada kecepatan, rel tak pernah benar-benar lurus—hanya terlihat lurus bila dilihat dari jauh. Rel Bayangan bukan sekadar kisah kereta cepat. Ia tentang bangsa yang menukar ketelitian dengan simbol, dan menjadikan utang sebagai bahan bakar mimpi yang tak sempat dihitung biayanya.
Note :
Sebuah fiksi, thriller politik-ekonomi tentang kecepatan, utang, dan kuasa. Presiden Ardhanegara — teknokrat ambisius; cepat mengambil risiko politik. Sabarudin — konseptor pembiayaan infrastruktur, piawai mengolah narasi fiskal. Arka Santoso — Menteri Perhubungan yang hati-hati, integritas tinggi. Rania Wiranti — Menteri BUMN, mantan banker; tajam dan tegas. Li Wei — Direktur Jiangdao Rail Group (JRG), konglomerat rel lintas benua. Chen Jun — Wakil Hanlong Development Bank (HDB), bank pembangunan dari Dinasti Timur. Kenji Tanaka — Kepala proyek di Sakura International Cooperation Agency (SICA).
PSN – Pilar Sinergi Nusantara: konsorsium BUMN (GAR—Garuda Railways; WAKO—Wahana Konstruksi; DLN—Darma Lintas Nusantara; PAG—Perkasa Agro). GVR – Garuda Velocity Rail: JV PSN × JRG (60:40). SSC – Silk-Sea Corridor: inisiatif geo-ekonomi Dinasti Timur. TriBara: tiga bank BUMN—Mandala Bank, Bahana Rakyat, Nusantara Investama. LVC – Land Value Capture: skema penangkapan nilai tanah di koridor rel.

Tinggalkan komentar